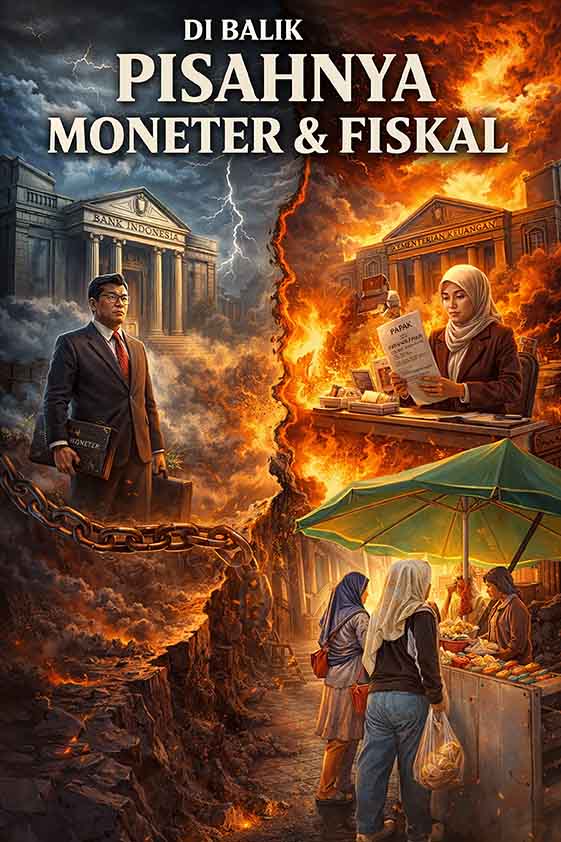INTELEKTUAL YANG KESEPIAN DI TENGAH KERAMAIAN:
MENGGELANDANG DI RUMAH SENDIRI
Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si
(Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
Di zaman ketika ruang publik tampak semakin ramai oleh diskursus, pernyataan, seminar, konferensi, dan diskusi daring yang tak pernah usai, kita justru menyaksikan satu ironi besar: kesepian intelektual. Ia hadir di tengah keramaian, tetapi tidak benar-benar ditemani. Ia berbicara, namun tidak sungguh-sungguh didengar. Ia berada di “rumah” bernama ruang akademik dan publik, tetapi merasa seperti tamu asing bahkan penggelandang di dalamnya sendiri.
Kesepian intelektual bukanlah soal ketiadaan forum atau minimnya interaksi sosial. Justru sebaliknya, ia lahir dari banjir interaksi yang dangkal, serba seremonial, dan miskin keberanian berpikir. Dalam banyak kasus, intelektual hari ini dikelilingi oleh orang-orang yang sepakat, tetapi jarang bertemu dengan mereka yang benar-benar mau berdialog. Keramaian menjadi selimut yang menutupi kegersangan makna.
Fenomena ini semakin terasa ketika intelektual dihadapkan pada tuntutan untuk selalu “relevan”, “aman”, dan “selaras” dengan kepentingan dominan. Ruang berpikir tidak lagi sepenuhnya bebas, melainkan dibatasi oleh berbagai pagar tak kasatmata: kepentingan politik, logika pendanaan, tekanan institusional, hingga budaya populer yang lebih menyukai slogan daripada argumentasi. Di titik inilah intelektual mulai mengalami keterasingan bukan karena ia menjauh, tetapi karena lingkungan sekitarnya tidak lagi menyediakan ruang yang jujur bagi kegelisahan berpikir.
Kesepian intelektual juga berakar pada perubahan fungsi pengetahuan. Pengetahuan yang seharusnya menjadi alat emansipasi, kini sering direduksi menjadi komoditas. Gelar, publikasi, dan sertifikat lebih dihargai daripada keberanian intelektual. Akibatnya, banyak intelektual terjebak dalam rutinitas produksi pengetahuan yang mekanis, kehilangan ruh kritis, dan perlahan menjauh dari denyut persoalan nyata masyarakat. Mereka sibuk, tetapi hampa. Produktif, tetapi sunyi.
Dalam konteks ini, intelektual sering dipaksa untuk memainkan peran ganda yang melelahkan. Di satu sisi, ia dituntut menjadi suara kritis yang mengoreksi kekuasaan dan ketidakadilan. Di sisi lain, ia diharapkan tetap “santun”, “tidak terlalu keras”, dan “tidak menyinggung”. Ketegangan inilah yang membuat banyak intelektual memilih jalan aman: berbicara normatif, mengulang wacana lama, dan menghindari posisi yang berisiko. Namun, pilihan aman ini justru memperdalam kesepian, karena intelektual kehilangan kejujuran pada dirinya sendiri.
Kesepian intelektual semakin kompleks ketika dikaitkan dengan realitas lokal dan daerah. Di banyak wilayah, termasuk di daerah-daerah yang kaya potensi tetapi miskin ruang diskursus kritis, intelektual sering berhadapan dengan situasi dilematis. Ketika ia mengajukan kritik, ia dicap tidak loyal. Ketika ia diam, ia merasa mengkhianati nurani akademiknya. Dalam kondisi seperti ini, intelektual benar-benar menggelandang di rumahnya sendiri menjadi bagian dari masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya diterima ketika berbicara jujur.
Media sosial, yang semula diharapkan menjadi ruang demokratisasi gagasan, ternyata juga menghadirkan paradoks baru. Ia memperluas jangkauan suara, tetapi sekaligus menyederhanakan kompleksitas berpikir. Algoritma lebih menyukai kontroversi instan daripada argumentasi mendalam. Akibatnya, intelektual yang terbiasa dengan penjelasan panjang dan nuansa sering kalah oleh narasi singkat yang emosional. Dalam keramaian digital ini, kesepian intelektual justru semakin nyata: suara ada, tetapi tenggelam dalam kebisingan.
Namun, penting untuk ditegaskan bahwa kesepian intelektual tidak selalu bersifat negatif. Dalam sejarah pemikiran, banyak gagasan besar lahir dari kesendirian. Kesepian bisa menjadi ruang kontemplasi, tempat intelektual berdialog dengan dirinya sendiri dan dengan zaman. Masalah muncul ketika kesepian itu bukan lagi pilihan sadar, melainkan akibat dari penyingkiran struktural dan budaya anti-kritik. Pada titik ini, kesepian berubah menjadi alienasi yang melemahkan daya cipta dan keberanian berpikir.
Krisis kesepian intelektual juga berkaitan erat dengan melemahnya etos dialog. Dialog sejati mensyaratkan keterbukaan, kesediaan mendengar, dan keberanian menerima perbedaan. Sayangnya, banyak ruang diskusi hari ini lebih menyerupai ajang pembenaran posisi masing-masing. Perbedaan tidak diperlakukan sebagai sumber pembelajaran, melainkan ancaman yang harus dieliminasi. Dalam iklim seperti ini, intelektual yang berpikir di luar arus utama akan selalu merasa sendirian.
Lebih jauh, kesepian intelektual mencerminkan krisis rumah intelektual itu sendiri. Universitas, lembaga kajian, dan organisasi intelektual seharusnya menjadi rumah yang aman bagi pertumbuhan gagasan kritis. Namun, ketika institusi-institusi ini terlalu sibuk dengan administrasi, akreditasi, dan citra, fungsi substantifnya sebagai ruang pemikiran bebas perlahan tergerus. Intelektual tetap tinggal di dalamnya, tetapi merasa tidak benar-benar memiliki tempat.
Dalam konteks kebijakan publik dan ekonomi politik, kesepian intelektual memiliki dampak yang serius. Ketika suara kritis terpinggirkan, kebijakan cenderung lahir dari logika teknokratis yang kering nilai, atau bahkan dari kompromi kepentingan sempit. Intelektual yang seharusnya menjadi jembatan antara pengetahuan dan kepentingan publik justru terisolasi. Akibatnya, kebijakan kehilangan kedalaman analisis dan kepekaan sosial.
Menghadapi realitas ini, pertanyaan penting yang harus diajukan bukan sekadar “mengapa intelektual kesepian?”, tetapi “apa yang harus dilakukan agar rumah intelektual kembali layak dihuni?”. Jawabannya tentu tidak sederhana. Ia menuntut perubahan budaya, keberanian institusional, dan komitmen personal. Kita perlu membangun kembali ruang-ruang dialog yang menghargai perbedaan, mendorong debat yang sehat, dan melindungi kebebasan berpikir.
Intelektual juga perlu merefleksikan perannya sendiri. Kesepian tidak selalu datang dari luar; kadang ia lahir dari jarak yang sengaja diciptakan oleh intelektual terhadap masyarakat. Bahasa yang terlalu elitis, sikap merasa paling tahu, dan keengganan untuk mendengar suara akar rumput dapat memperdalam jurang keterasingan. Rumah intelektual tidak bisa dibangun hanya dari menara gading; ia harus berpijak pada realitas sosial yang hidup.
Pada akhirnya, intelektual membutuhkan lebih dari sekadar panggung. Ia membutuhkan rumah ruang yang memungkinkan kegelisahan berpikir tumbuh tanpa rasa takut, tempat kritik tidak dianggap sebagai pengkhianatan, dan perbedaan dilihat sebagai kekayaan. Tanpa rumah seperti itu, keramaian hanya akan menjadi ilusi, dan intelektual akan terus menggelandang di rumahnya sendiri.
Kesepian intelektual adalah cermin dari kondisi sosial kita hari ini. Ia mengingatkan bahwa kemajuan tidak diukur dari seberapa ramai diskusi berlangsung, tetapi dari seberapa jujur dan berani kita berpikir bersama. Jika kita gagal membangun rumah intelektual yang inklusif dan kritis, maka kesepian ini bukan hanya milik para intelektual, melainkan pertanda krisis yang lebih luas dalam kehidupan publik kita.