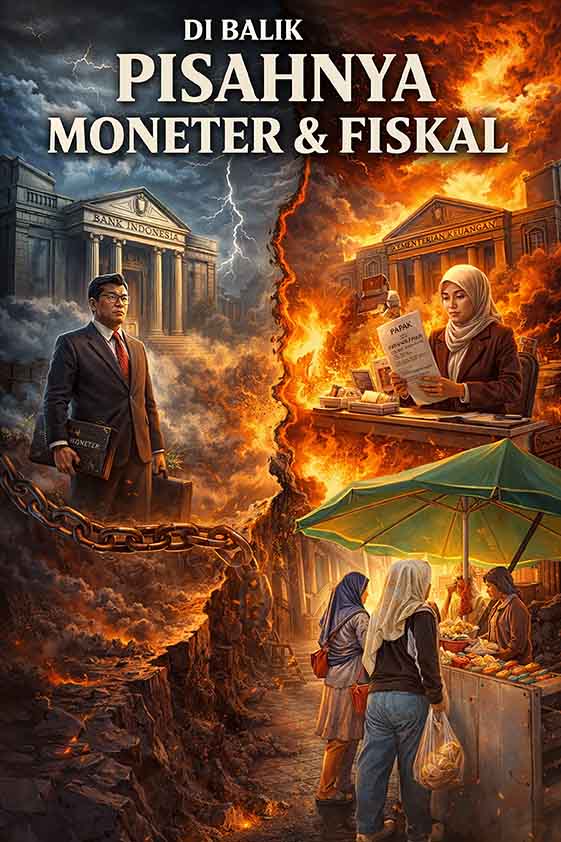BENCANA, NEGARA DAN AMARAH YANG MENUMPUK
Oleh: Radhar Tribaskoro
Banjir dan longsor di Sumatera—terutama di Aceh dan sekitarnya—bukan lagi sekadar peristiwa alam. Ia telah menjelma menjadi krisis politik dan komunikasi.
Ketika air surut dan tanah berhenti bergerak, justru bencana kedua muncul: bentrokan verbal antara pejabat negara dan publik, kemarahan kolektif yang meluap, hingga simbol-simbol lama seperti bendera putih dan bahkan bendera GAM kembali terlihat di ruang publik.
Pertanyaannya lalu bergeser dari soal teknis menjadi soal eksistensial: apakah amarah rakyat Aceh berpotensi memicu konflik baru?
Pertanyaan itu sah diajukan, bukan karena rakyat Aceh gemar berkonflik, melainkan karena sejarah mengajarkan bahwa pengabaian negara terhadap penderitaan publik adalah bahan bakar paling efektif bagi radikalisasi politik.
*Masalah Utamanya Bukan Status Bencana*
Sejak awal polemik, diskusi publik terjebak pada isu yang keliru: *apakah ini bencana nasional atau daerah, apakah bantuan asing boleh masuk atau tidak.*
Padahal, inti persoalan sebenarnya jauh lebih sederhana sekaligus mendasar: apakah penanganan bencana ini sudah dirasakan memadai oleh rakyat yang menjadi korban?
Dalam manajemen bencana modern, status administratif tidak pernah menjadi prioritas utama. Yang menjadi kunci adalah:
– kecepatan respons,
– kejelasan informasi,
– keterbukaan otoritas,
– serta pelibatan publik secara luas.
Tanpa itu semua, negara akan selalu tampak “jauh”, tak peduli seberapa banyak keputusan yang diambil di pusat.
*Transparansi: Kewajiban, Bukan Pilihan*
Otoritas kebencanaan seharusnya menjadi sumber kepastian di tengah kekacauan. Cara paling elementer untuk melakukannya adalah melaporkan keadaan secara rutin dan terbuka:
berapa jumlah warga terdampak,
berapa korban jiwa dan luka,
infrastruktur apa saja yang rusak,
wilayah mana yang sudah dan belum tertangani.
Laporan itu tidak cukup sekali. Ia harus disampaikan secara berkala, dengan angka yang konsisten dan dapat diverifikasi.
Ketika negara diam atau berkomunikasi, sepotong-sepotong, publik akan mengisi kekosongan itu dengan:
rumor, kecurigaan, dan pada akhirnya, kemarahan.
Di titik itulah, simbol-simbol perlawanan lama kembali menemukan momentumnya.
*Solidaritas Sosial Bukan Ancaman*
Ada keganjilan yang sulit dijelaskan dengan akal sehat: penghimpunan dana publik ditakut-takuti soal perizinan, aksi solidaritas diremehkan, sementara politisi tampil memanggul karung beras—sebuah gestur simbolik—lalu makan mewah di restoran.
Dalam setiap bencana besar di dunia, solidaritas sipil justru dilihat sebagai aset, bukan ancaman legitimasi negara. Negara yang percaya diri tidak takut dibantu rakyatnya sendiri.
Bencana adalah momentum membangun kembali kepercayaan sosial: bahwa kita masih satu komunitas politik, satu bangsa, satu nasib.
*Jika Negara Mampu, Buktikan dengan Kerja Nyata*
Tidak ada yang salah jika pemerintah merasa mampu menanggulangi bencana tanpa bantuan asing. Itu adalah pilihan kedaulatan.
Namun kedaulatan bukan pernyataan, melainkan pembuktian melalui tindakan.
Rakyat tidak membutuhkan pidato; mereka membutuhkan dapur umum yang berfungsi, pengungsian yang layak, distribusi logistik yang merata, serta kehadiran negara yang konsisten.
Jika rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa korban terus berjatuhan—bukan lagi karena banjir dan longsor, tetapi karena kelalaian—maka masalahnya akan berubah dari bencana alam menjadi krisis legitimasi negara.
*Belajar dari Dunia: Bencana Tanpa Polemik*
Sejumlah negara menunjukkan bahwa bencana besar tidak harus diikuti kegaduhan politik.
*Jepang* . Dalam tsunami 2011, pemerintah Jepang menetapkan komunikasi publik sebagai prioritas mutlak. Data korban diperbarui hampir setiap hari. Masyarakat sipil, relawan, dan sektor swasta justru dilegitimasi penuh untuk bergerak bersama negara.
*Chile* Negara rawan gempa ini membangun protokol darurat yang jelas: siapa bicara, kapan, dan dengan data apa. Transparansi membuat publik tenang, bahkan ketika kerusakan sangat luas.
*Selandia Baru*. Pemerintah secara sadar menempatkan empati dan kejujuran di depan kamera. Pengakuan atas keterbatasan justru meningkatkan kepercayaan publik.
Dari semua contoh itu, pelajarannya sama:
bukan kekuatan negara yang mencegah konflik pascabencana, melainkan kualitas komunikasinya.
*Akar Masalah dan Pencegahan*
Negara juga tidak boleh berhenti pada penanganan darurat. Bencana ini harus menjadi pintu masuk untuk menyelidiki akar masalah:
– alih fungsi lahan,
– pembabatan hutan,
– tata ruang yang permisif,
– serta kebijakan ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan.
Tanpa evaluasi kebijakan yang jujur, bencana berikutnya tinggal menunggu waktu—dan publik tidak akan memaafkan pengulangan kelalaian.
*Penutup: Jangan Mainkan Api*
Apakah kemarahan rakyat Aceh akan memicu perang baru? Itu tergantung pada satu hal: apakah negara bersedia belajar dan berubah. Rakyat tidak meminta keajaiban.
Mereka hanya ingin diyakinkan bahwa: penderitaan mereka dilihat, suara mereka didengar, dan nyawa mereka dihitung.
Negara yang abai terhadap bencana sedang bermain api.
Dan sejarah Aceh mengajarkan: api yang dipelihara oleh ketidakadilan tidak pernah padam dengan sendirinya.===
Cimahi, 28 Desember 2025