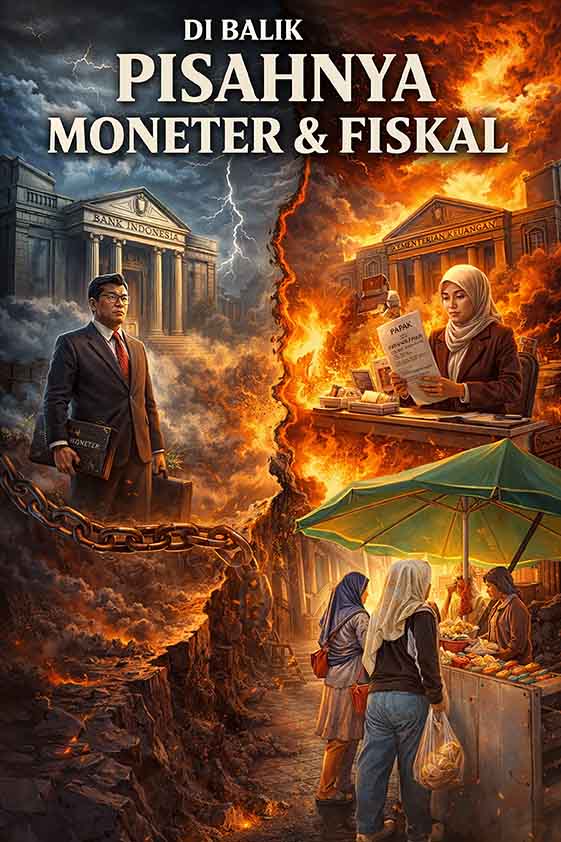KONSTITUSIONALITAS PEMILU INDONESIA: Dari Original Intent hingga Realitas Demokrasi
Oleh: Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Konstitusi Indonesia, dirancang oleh para pendiri Indonesia sebagai grondwet (Undang-Undang Dasar) yang mencerminkan kearifan politik dan konstitusional bangsa Indonesia. Sebuah konstitusi yang lahir dari perdebatan konseptual dan historis, digali dan diejawantahkan dalam bentuk nilai-nilai yang hidup, dari pelbagai ideologi dan kebudayaan yang telah ada dalam Sejarah dunia.
Pada periode penyusunan konstitusi dapat kita telusuri kehendak para pendiri bangsa ini untuk membentuk sebuah negara modern, yaitu negara republik yang andal. Negara yang memiliki karakter politik yang berbeda dengan dengan republik di belahan dunia manapun dengan sistem politik dan konstitusi yang berpedoman pada kearifan Nusantara.
Kehendak untuk mendirikan republik yang memiliki corak keindonesiaan itu dapat kita baca di dalam risalah sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 (masa sidang pertama) dan sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli 1945.
Sepanjang sidang itu ide tentang negara mengemuka, baik mengenai dasar negara, maupun mengenai bentuk negara, serta sistem pemerintahan yang hendak dibangun untuk Indonesia merdeka. Seperti apakah ide tentang Indonesia yang dicita-citakan? “Kita hendak mendirikan negara buat selama-lamanya” kata Soekarno. Negara yang demikian itu, adalah “negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Negara itu menurut Soekarno adalah negara permusyawaratan dan perwakilan.
Negara yang buat semua golongan itulah yang hendak dibangun, dan untuk mencapai negara yang demikian itu, para pendiri bangsa memilih sistem permusyawaratan dan perwakilan sebagai tata cara untuk memilih pemimpin negara (dalam hal ini presiden). Karena itu para perumus konstitusi Indonesia menolah secara gamblang mengenai ide demokrasi liberal ala barat dan mengajukan kritikan yang cukup serius terhadap demokrasi barat itu.
Negara Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, seperti dasar dan bentuk susunan negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (Rechtsgeschichte) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk sesuatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Karena itu Soepomo memberi penekanan tentang hukum dan lembaga sosial masyarakat sebagai bagian dari aliran pikiran dan kebatinan bangsa Indonesia.
Anjuran untuk memilih pemimpin pun tidaklah mutlak, bahkan dalam bentuk monarki sekalipun Soepomo tidak keberatan, tetapi syarat pemimpin itu, harus menyatu jiwa dan dirinya dengan rakyat sembari mengajukan penolakan pada paham demokrasi barat yang individual. Kata Professor Soepomo:
Menurut hemat saya soal republik atau monarkhi itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Yang penting ialah, hendaknya Kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya.
Kepala Negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah Kepala Negara itu akan diberi kedudukan sebagai Raja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai “Führer”, itu semuanya tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik Raja atau Presiden atau Führer, atau Kepala Negara yang bergelar ini atau itu, misalnya bergelar “Sri Paduka yang Dipertuan Besar” atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya. Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun- temurun, atau hanya untuk waktu yang tertentu, itulah hanya mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi Barat, oleh karena pilihan secara sistem demokrasi Barat itu berdasar atas faham perseorangan.
Tuan-tuan sekalian hendaknya insaf kepada konsekuensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya.
Bagi pendiri negara ini, demokrasi barat tidak sesuai dengan karakter politik Indonesia. Soekarno mempertegas, “demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politieke conomische democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie”, Demikian kata Seokarno.
Demokrasi liberal telah membuktikan kegagalan-kegagalan yang cukup serius dalam membentuk pemerintahan yang benar-benar demokratis. Seorang pembela utama demokrasi liberal di awal abad 21, Francis Fukuyama, justru mengkritik praktik, praktik demokrasi liberal diberbagai belahan dunia. Padahal sebelumnya dalam Buku The End History of The Last Man pada tahun 1989 Francis Fukyama begitu yakin bahwa pilihan terakhir ideologi politik negara-negara di dunia adalah demokrasi liberal. Fukuyama mengklaim bahwa di seluruh dunia, orang-orang telah memutuskan bahwa kapitalisme dan demokrasi liberal lebih unggul daripada komunisme otoriter yang dihasilkan oleh Bolshevisme dan Maoisme. Ia berpendapat bahwa kemenangan liberalisme berarti bahwa “Sejarah”—dipahami sebagai perjuangan antara ideologi-ideologi yang bersaing—telah berakhir. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa, seiring berjalannya waktu, banyak negara yang belum menjadi demokrasi kapitalis liberal pasti akan melakukannya, dan bahwa ini akan baik bagi umat manusia.
Kegagalan itulah yang dibaca sedari awal oleh Para perumus konstitusi Indonesia, salah satunya Haji Agus Salim. Menurut Haji Agus Salim Riwayat demokrasi Eropa sudah menunjukkan bahwa suara yang banyak itu hanya sebagian terdiri dari pada aliran yang berkeyakinan tepat sedang sebagian besar adalah suara daripada suatu golongan tengah, yang tidak tentu berkeyakinan sama, dan yang baginya pas asasnya sama saja dapat atau tidaknya tercapai sesuatu soal yang disokongnya dengan suaranya, sehingga jikalau golongan yang kecil tidak mau menyerah karena kalah suara saja dan mau beradu tenaga dengan memaksa usaha golongan yang kecil itu bisa dan mau beradu tenaga dengan memaksa usaha golongan yang kecil itu bisa juga mendapat kemenangan sebagaimana sudah terbukti dalam beberapa negeri di dunia Barat. Di situ bangkit salah satu partai lain dan yang berkata : “Kalau dengan menghitung suara barangkali kita kalah, tetapi kalau memakai kepelan kita menang”.
Kemudian Haji Agus Salim mempertegas pendirinya tentang demokrasi Permusyawaratan Perwakilan:
Itulah sudah terjadi di dunia Barat dalam zaman akhir ini. Kebetulan cara pemufakatan yang kita cari berllainan sekali dariada yang terpakai dalam demokrasi Barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersma itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya.
Tapi bagaimana dengan sistem pemilihan Presiden? Soekiman Wirdjosanjojo, memberikan pemisahan yang jelas mengenai kekuasaan kedaulatan rakyat. Supaya ada sedikit garis atau sistem yang praktis, mengenai soal kekuasaan kedaulatan rakyat, Soekiman mengusulkan supaya Dewan Perwakilan Rakyat disusun oleh dan daripada anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; dengan demikian ada 2 badanlah yang menjadi mandataris atau kuasa kedaulatan rakyat itu, yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Soekiman kemudian menetapkan pendiriannya:
Untuk menyingkirkan keadaan-keadaan keruh yang mungkin timbul dalam perjuangan pemilihan, seperti seringkali sungguh menyala-nyala di negeri yang lain, dan menilik tingkat kecerdasan rakyat kita, maka saya mufakat sekali bahwa Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 4), dan buat sementara waktu tidak langsung oleh rakyat. Dengan kedudukan Presiden sebagai pembikin Undang-undang biasa bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan para Menteri-menteri bertanggungjawab terhadap kepadanya tidak pada Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemerintah secara parlementaire democratie Eropa tidak terpakai; saya sendiri amat setuju (pasal 3). Dengan konstruksi demikian, maka terjaminlah tetap langsungnya stabiliteit pemerintahan yang sungguh menjadi syarat mutlak untuk membentuk negara baru.
Setelah perdebatan panjang yang cukup oleh tim perumus konstitusi, maka disepakatilah bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Ketentuan ini kemudian memberi kewenangan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk mengubah dan menetapkan UUD, menetapkan haluan negara, memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden serta berhak menjatuhkan presiden.
Dengan sistem yang demikian itu, maka sifat kepemimpinan negara seperti yang diharapkan oleh Soepomo, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno, Yamin dan seluruh anggota BPUPKI bukanlah pemimpin yang lahir dari populisme, tetapi pemimpin yang lahir dan diseleksi secara ketat oleh proses dan sistem politik secara alamiah. Pemimpin itulah yang oleh Soepomo disebut sebagai pemimpin yang bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat “badan penyelenggara”, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya.
Dalam negara permusyawaratan dan perwakilan itu, kata Professor Soepomo, negara berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Bentuk negara yang integralistik ini memiliki ciri khas keindonesiaan yang asli, dengan kelembagaan sosial yang bersumber dari kebudayaan masyarakat Indonesia.
II
Risalah perdebatan anggota MPR yang tergabung dalam Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III Badan Pekerja MPR tahun 1999-2002, dalam mengubah UUD 1945, dicatat, salah satunya, menghasilkan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta cara pengisian jabatan presiden dan wakil Presiden. Dua isu ini (pembatasan masa jabatan dan pengisian jabatan presden dan wakil presiden), jelas ditulis secara tegas dalam UUD 1945. Ini berbeda dengan dengan pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Jabatan-jabatan yang disebut terakhir ini tidak disebut secara tegas cara pengisiannya oleh UUD 1945. Menariknya, atas nama “demokrasi” kita memilih “pemilihan langsung” sebagai cara mengisi jabatan ini. Hari-hari ini, pilihan ini terindikasi menyengsarakan kita sebagai bangsa.
Apa yang kita semua maksudkan dengan demokrasi? Adakah bentuk final demokrasi? Apa yang kita maksudkan dengan demokrasi prosedural dan substansial? Bisakah dua hal itu dipisahkan satu sama lainnya? Bagaimana sejarah menampilkan kedua konsep yang multimakna itu? Adakah konsep dalam ilmu hukum tata negara dan politik, yang tidak menempatkan “kesetaraan” antarsesama manusia, sebagai tampilan eksistensial setiap manusia sebagai mahluk berharkat dan bermartabat, yang sedari lahir disandang oleh setiap orang? Kesetaraan, martabat dan kemuliaan setiap orang diberikan bukan oleh kekuasaan. Semua disandang dan dimiliki setiap orang karena mereka adalah manusia dan ini diberi oleh alam – sunnatullah. Darinya keadilan berinduk, dan mengalir; pangkal penciptaan kehidupan yang civilized. Itulah hakikat demokrasi, hakikat republik.
Ada yang menarik yang tersaji dalam Kerangka Acuan yang saya terima. Demokrasi kita naik dan turun, sejauh ini sejak UUD 1945 diubah. Padahal demokrasi dipangiil bangsa ini, karena diyakini sebagai cara andal yang memungkinkan kita semakin cepat dalam mewujudkan cita-cita kita. Mengapa dan apa yang salah? Doctor Margarito Kamis, mengindentifikasi masalah demokrasi ini dengan mensetir Sejarahwan sekaligus negarawan Romawi klasik, Polibyus. Polibyus meminta setiap perancang tatanan berbangsa dan bernegara harus “menjadikan tabiat alamiah manusia” sebagai pusat perhatiannya pada saat merancang tatanan bernegara.
Kredo Polibyus ini, Menurut Margarito, diikuti oleh James Madison, anak muda berumur 32 tahun, perancang awal UUD Amerika Serikat, dengan langgam yang lebih teknis. Berinduk pada perspektif Polibyus, ia tuangkan dalam “Viriginia Plan” rancangan awal UUD, yang didalamnya menggariskan ide-ide tentang tatanan pemerintahan yang hendak dibangun. Berhasrat kuat agar pemerintahan yang akan diciptakan nanti tidak menjadi totaliter, absolut, menghancurkan kebebasan individu, maka rancang bangun sistem harus mencegahnya. Dia segera memasuki isu alamiah manusia, dan menempatkannya pada jantung perspektifnya. Ambition, katanya must be make to counteract ambition” dan the interest of the men must be connected whit the constitutional rights of the place. Menurut Madison, Ambisi kekuasaan harus tunduk pada hak konstitusional setiap warga negara. Ia melanjutkan, dalam kata-katanya “It may be reflection human nature that such devices should be necessary to control the abuses of government. Benar-benar memperhitungkan sifat alamiah manusia, James menegaskan dalam lanjutan pandangannya “If men are angels, no goverment would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary.
Ketakutan terhadap bahaya kediktatoran, absolutism, bahkan konspirasi dan merajalelanya motivasi etno politik turut memandu mereka dalam mendiskusikan cara pemilihan presiden. Akan saya perlihatkan nanti, pemilihan langsung bukan ciri demokrasi. Pemilihan tidak langasung juga bukan cara yang tidak demokratis. Semuanya – kedua cara ini – diperhitungkan oleh para perancang UUD Amerika dalam mencari dan menemukan cara mengiisi jabatan presiden.
Tetapi kita perlu melihat “sindrom busuk” semacam permainan politik, berupa politik uang dalam pemilu. Oleh karena Amerika selalu dijadikan preferensi utama, terlihat menjadi perspektif dominan dalam diskusi-diskusi tentang demokrasi di negeri ini, saya ingin mengutip pandangan pembentuk UUD Amerika tentang sejumlah hal, yang dengannya dapat membantu kita menyatakan tanpa ragu bahwa pemilu langsung sama sekali bukan hal esensial, apalagi menjadi cara yang harus dituruti untuk menghidupkan demokrasi.
Ketika debat memasuki isu pemilihan presiden, yang hendak dipilih melalui Congres, Gubernur Morris memberi respons yang cukup menarik. Kata Morris “Jika Legislatif terpilih, itu akan menjadi pekerjaan intrik, komplotan, dan faksi; itu akan seperti pemilihan orang yang benar-benar berjasa, jarang sekali jabatan yang diberikan kepada orang yang ditunjuk. James Wilson yang berbicara sesudahnya, juga menarik dalam merespon isu ini. Wilson berpendapat “Legislatif berhak atas kepercayaan kita dan kekuasaan yang tak terbatas; dalam hal-hal lain, ia tidak boleh dipercayakan”. Tetapi menariknya, Roger Sherman, pembicara sesudah James Wilson, menegaskan “Masyarakat tidak akan pernah cukup mendapat informasi tentang karakter untuk memilih dengan bijak”. Pandangan berbeda, menariknya muncul lagi.
George Masson, penulis Virginia Declaration of Rights dan sekaligus menjadi benteng pertahanan kebebasan individu, menegaskan bahwa “Warga negara biasa dapat diandalkan untuk memilih pemimpin negara dengan lebih efisien. Akan sama tidak wajarnya jika kita menyerahkan pilihan karakter atau kepala pemerintahan kepada rakyat, sama tidak wajarnya dengan menyerahkan ujian warna kepada orang buta.
Muncul Lagi pandangan berbeda dalam isu ini. Kali ini Elbridge Garry, muncul sebagai penentang pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Menarik, dia menempatkan semangat tertentu – etno politic – loyaitas berbasis daerah-kultur sebagai salah satu alasan penolakannya. Barry berpendapat Jika rakyat memilih eksekutif, kata Gerry, “setiap kelompok terorganisir yang menyatukan orang-orang dari seluruh negeri akan mengendalikan hasilnya”. Isu etnopolitics muncul lagi. Kata Gerry, “Whit the benefit of an existing organization, the Society of the Cincinnati was most likely to choose the nation president.” Gagasan yang saling bersaing ini, terlihat hendak disudahi oleh Luter Martin. Dia hendak membawa konvensi kemeja kompromi. Dia menegaskan “popular election – election for ellectors.” Tapi dalam kata-kata Carrol Berkin, “the convention vote “no”.
Buntu untuk sementara, sebelum akhirnya didiskusikan untuk ekdua kalinya. Diskusi kedua kalinya ini berlangsung pada tanggal 4 September 1787, saat konvensi menerima laporan Postpone Committee. Laporan ini berisi, salah satunya, gagasan “elector” dari setiap negara – dipilih oleh DPR masing-masing negara bagian. Gagasan ini, dalam penilaian Berkin mengagetkan peserta konvensi. Tetapi kekagetan yang sesungguhnya terjadi pada saat muncul gagasan “Ellectoral College.” Berkin menulis “Dickinson may have proposed the “electoral college” (tanda petik dari saya) on that September afternoon, but the idea itself belonged to James Wilson, who had patiently, persistently argued for some form of popular participation in the choice of the national executive since June.
Soal uang, suap-menyuap dan pesta yang diadakan oleh kandidat dalam kampanyennya. Sejarah pemilu menunjukan dengan sangat meyakinkan Romawi Republik berada difront terdepan dalam semua aspek busuk pemilu. Seperti kita saat ini, pemilu di Republik Romawi tenggelam, dalam seluruh aspeknya pada penyuapan, bagi-bagi uang, pesta rakyat, jamuan makan dan seterusnya. Terus terjadi, sehingga memaksa Romawi pun harus terus-menerus mencari dan menemukan cara – menggunakan hukum – UU – menghentikan praktek busuk ini. Sama dengan Amerika sejak tahun 1907 dan kita saat ini, Romawi mengandalkan UU – terdapat 14 UU – diberi nama lex de ambitu – untuk menghentikan praktek busuk ini. Hasilnya? Negatif. Gagal, gagal dan gagal.
Korupsi dalam kehidupan Romawi berputar disekeliling sistem pemilihan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan yang dibutuhkan karena adanya penaklukan wilayah. Syed Husen Alatas, sejarahwan kawakan berkebangsaan Malaysia ini menggambarkan:
“Usaha-usaha untuk menekan korupsi sudah dilakukan sejak tahun 432 Sebelum Masehi, dalam kaitannya dengan berbagai praktek pemilihan. Pada tahun 67 Sebelum Masehi, denda berat dikenakan kepada para calon yang mencoba “menyuap” (tanpa petik dari saya) para pemilih. Hukum yang diperkenalkan oleh Cicero, menjadi konsul mengancam penyuapan dalam rangka pemilihan dengan pengusiran keluar Romawi selama sepuluh tahun. Para calon tidajk boleh memberi dan menerima jamuan makan atau hadiah-hadiah. Para calon tidak boleh menyelenggarakan pertunjukan gladiator atau hiburan-hiburan umum dalam waktu dua tahun masa pencalonannya. Aturan ini pun tidak efektif. Sekalipun demikian, sejarah Romawi menunjukan betapa kecilnya pengaruh aturan untuk mengakhiri korupsi ini. Harga yang harus dibayar untuk jabatan konsul tidak menurun. Peristiwa pada tahun 54 Sebelum Masehi menunjukan angka raksasa sebesar sepuluh juta sestere – setara 100.000.pounsterling – yang diperuntukan bagi pemungutan suara bagian pertama saja.”
III
Dalam pemilu ada pelbagai problem, termasuk isu sara, yang dalam sejarahnya terorkestrasi dengan sangat sistimatis pada pemilu presiden Amerika tahun 1801. Pemilu ini menampilkan John Adam (Presiden incumbent) dan Thomas Jefferson, dua orang hebat dalam sejarah kepresidenan Amerika. Tetapi waktu yang tersedia tidak memungkinkan saya mengungkap detailnya, termasuk problem pemilu sesudahnya. Saya hanya akan menyajikan secara ringkas beberapa fakta tentang omong kosong pemilu bebas dari pengaruh uang kalangan big corporation, yang seluruh aspeknya bersifat oligarkis. Sekali lagi, terdorong oleh kenyataan terbantahkan bahwa demokrasi Amerika selalu dijadikan panduan dalam pembicaraan demokrasi di negeri ini, maka saya akan mengajak kita melihat fakta kecil yang terverifikasi yang akan saya sajikan dibawah ini.
Tahun 1907, untuk pertama kalinya Amerika memiliki UU yang mengatur, dalam makna membatasi “donasi” dari korporasi besar kepada kandidat. UU ini dikenal dengan nama Tillman Act 1907, yang merupakan respon atas problem donasi korporasi besar dalam pemilihan 1904, yang menghasilkan Theodore Rosevelt sebagai Presiden. Tetapi sejarah sangat jelas menunjukan pemilu 1896 yang diikuti William McCinley (Partai Republik dan Wlliam Jenning Bryant (Partai Demokrat), menyajikan data pemilu dikendalikan oleh kalangan oligarki. McCinley menghabiskan uang – diperkirakan sebesar $7000.000 – dibanding Wlliam Jenings Bryan yang diperkirakan menghabiskan uang hanya sebesar $300.000. Kenyataan ini menjadi dasar William D. Harpine menulis “Did the Republic Buy Election?” McCinly, presiden lemah, berada didalam – menurut penilaian Richard B. Backer – control Mark Hannah – donator terbesarnya. Hannah adalah kaki tangan oligarki, dan menjalankan kepentingan mereka. Sekalipun dinilai lemah, tetapi McCinley, menarik sekali, mengambil jalan lain – menolak melaksanakan Anti Trust Act – yag dikehendaki oleh oligarki dengan donasi kepada dirinya. Akibatnya jelas, McCinley di dibunuh.
Dollar for vote, tulis Farah Nawaz, menunjuk donasi bank-bank – corporasi besar – kepada McCinley dalam kampanye presiden 1896, dan kampanye presiden 1904, yang menghasilkan Tedy Rosevelt. Berhenti sejenak pada pemilu 1908, yang menghasilkan William Howard Taft, sebagai presiden yang sangat anti Bank Sentral, sebelum akhirnya oligarki mendanai Woodrow Wilson, Profesor tata negara, pada pemilu 1912. Hasilnya jelas, Wilson keluar sebagai pemenang. Wilson harus memilih politic quid pro quo, dengan cara menandatangani The federal Reserve Act 1913, bank pengiiap darah rakyat, yang ditolak pembentukannya oleh Thomas Jefferson, James Madison dan Andrew Jackson.
Seperti Romawi kuno, yang terus mengalami kegagalan demi kegagalan dalam mengatasi tabiat bawaan – penyupan atau apa yang Amerika sebut dengan donasi dalam pemilu – tahun 1925 Amerika menemukan jalan kedua dalam pertempuran melawan donasi Big Corporation. Kongres membentuk the Federal Corrupt Practices Act, dengan fokus aktifitas pemilihan umum. UU mengharuskan, salah satunya Political Action Committee mengumumkan donasi yang mereka terima. Begitu seterusnya hingga tahun 1974. Tahun ini Congress membentuk Federal Election Campaign Act, “FECA”. Didalam UU, diatur batasan sumbangan kepada kandidat presaiden, termasuk calon legislator.
Saat ini, tulis Ben Holzer, pemerintah federal dan seluruh 54 negara bagian (US) melarang pembelian suara, baik pada tingkat primary maupun pemilihan umum. Selalu begitu, persis seperti Romawi klasik, negara-negara ini mengandalkan hukum dalam pertempuran penuh kemustahilan untuk dimenangkan ini. Holzer menulis “these laws prohibit money.” Larangan ini meliputi sejumlah pembayaran, termasuk pemberian voucher untuk rokok dan makanan kecil. Larang ini, bahkan diperluas meliputi pembelian suara diluar pemilu, walaupun sering dicoba. Cukup menarik, Holzer menulis “Organizations, including New York’s Tammany Hall, organized massive vote buying efforts to purchase elections.
Korporasi dengan uang tak berujungnya itu, terus-menerus menjadi monster bagi pemilu Amerika. Persis Romawi Kuno, yang benar-benar kalah setiap kali melipat-gandakan energi politiknya melawan serbuan uang kalangan oligarki – kaum nol koma nol persen – dalam memenangkan kandidatnya. Kandidat partai, lebih tepat, dalam konteks ini disebut kandidat korporasi. Korporasi, selalu begitu, dengan kekuatan uangnya dapat menemukan celah hukum untuk mempertahankan, bahkan menemukan hak baru diluar ketentuan UU. Kasus berikut membuktikan untuk kesekian kalinya negara sehebat apapun, tidak mampu memenangkan pertarungan melawan korporasi dalam urusan pemilu. Kasusnya Adalah sebagai berikut: Pada pilpres Amerika 2008, Partai Demokrat mengadakan primary election untuk dua kandidat; Obama dan Hillary Clinton. United Citizen (Organisai nir laba) v. Federal Election Commission yang mendapatkan donasi dari korporasi besar, membuat sebuah film dokukenter. Film berdurasi satu jam ini, dibderi judul “Hilllary: The Movie.” Film ini berisi narasi menjelek-jelekan, hinaan dan sejenis terhadap Nyonya Hillary Clinton. FECA melarangnya. Bagi FECA, Bipartisan Campaign Reform Act 2002, melarang pendanaan oleh Korporasi atau individu kaya terhadap kandidat dan PAC serta Superpac (relawan kecil dan relawan besar). Citizen United, selain memiliki sumber dana dari donasi individu anggotanya, juga menerima donasi dari korporasi besar. Larangan FECA, ditolak oleh United Citizen, sekaligus menjadi sebab mereka membawa penolakan FECA itu ke pengadilan. Mahkamah, dengan komposisi 5 banding 4 memutuskan kasus ini. Dalam esensinya putusan ini menyatakan “Larangan UU terhadap donasi independent dari korporasi kepada kandidat, bertentangan dengan amandemen pertama UUD tentang kebebasan berbicara.” Hakim Kennedy, salah satu dari 5 hakim yang menulis pendapat mayoiritas, menyetujui donasi Korporasi kepada kandidat Presiden, memang dapat berakibat quid pro quo corruption, tetapi itu legitimate hanya sejauh untuk membatasi jumlah donasi. Padahal korporasi dengan kekuatan keuangannya mampu menciptakan berbagai macam kekuatan poltiik, tidak hanya merefleksikan kekuatan politik individu, tetapi siapa yang memiliki uang untuk mendukung kebebasan berbicara korporasi.
IV
Sekarang kita sampai pada upaya untuk merefleksikan kembali tentang sistem politik electoral kita. Karena itu ada DORONGAN untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan muncul desakan untuk menyerukan kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945 “yang asli”. UUD 1945 yang asli dimaksud adalah UUD yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian diberlakukan kembali setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Tidak jarang terjadi silang pendapat, kalau diberlakukan UUD yang asli maka jabatan presiden tidak dibatasi dua periode. Kemudian pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mulai pasal 28A hingga pasal 28J hasil perubahan juga lenyap. Kembali ke UUD 1945 yang asli adalah kembali ke “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawatan Rakyat”. Otomatis pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilakukan melalui lembaga MPR, tidak lagi menggunakan pemilihan langsung atau Pemilihan Presiden langsung sebagaimana dalam UUD NRI 1945.
Dorongan untuk kembali kepada sistem permusyawaratan dan perwakilan untuk memilih presiden dan wakil presiden, bersamaan dengan kritikan-kritikan tajam terhadap demokrasi Liberalisme yang berlaku pasca amandemen konstitusi. Liberalisme telah ditantang dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya oleh populis kanan, tetapi juga dari kiri progresif. Bahkan kaum nasionalis dan ultra nasionalis mulai melihat sisi-sisi gelap dari demokrasi liberal selama 15 Tahun terakhir. Kritik dari kuartal ini berkembang dari sebuah tuduhan—benar dengan sendirinya—bahwa masyarakat liberal tidak memenuhi cita-cita mereka sendiri tentang perlakuan yang sama terhadap semua kelompok. Kritik ini meluas dari waktu ke waktu untuk menyerang prinsip-prinsip yang mendasari liberalisme itu sendiri, seperti penempatan hak- haknya pada individu daripada kelompok, premis persamaan manusia universal yang menjadi dasar konstitusi dan hak-hak liberal.
Ketika kritik-kritik keras itu semakin kuat, maka seharusnya bukan institusi politik harus mengevaluasi kegagalan liberalism dalam banyak hal. Kalau demokrasi liberal gagal, maka negara yang menganut konstitusi liberalpun mengalami masalah yang cukup serius. Masalah ini juga yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu lemahnya otoritas Lembaga-lembaga liberal melalui konstitusi liberal tahun 1999-2002. Semangat awal tahun-tahun itu adalah semangat yang cukup jelas bagaimana liberalism terus digunakan untuk membentuk pemerintahan seluruh dunia sebagai perayaan kemenangan Amerika pada perang dingin, dan kehancuran Uni Soviet tahun 1990-an.
Namun setelah semua proses liberalisasi konstitusi dan mendorong Lembaga-lembaga liberal diakomodasi dengan pembentukan Lembaga negara baru, maka konstitusi awal yang disusun dengan semangat kekeluargaan oleh para pendiri bangsa ditinggalkan sepenuhnya. Kebutuhan membentuk institusi baru hanya untuk memperkuat mekanisme chek and balances antara cabang-cabang kekuasaan, tetapi tidak memberikan kemajuan pada peradaban politik Indonesia.
Kegagalan itu terlihat jelas Setelah pilpres 2014, demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, berbagai pelemahan institusional terjadi secara simultan, pelembagaan demokrasi mengalami konvergensi (baca: intervensi yang terkoordinasi), menyebabkan titik kulminasi demokrasi berjalan kearah sistem oligarkis. Hal-hal ini terjadi begitu cepat, tanpa dibayangkan bahkan oleh seorang Ahli Ilmu Politik.
Swa-Demokrasi yang diinginkan pasca-tirani, bukan sekedar kebebasan, bukan sekedar pemilihan langsung. Demokrasi yang dimaksud adalah tercapainya negara kesejahteraan (welfare state) dan negara yang melindungi rakyatnya, yaitu negara dengan sistem kesejahteraan nasional yang memberi amanat negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Namun konsep negara kesejahteraan yang diinginkan memiliki masalah yang mendasar, disebabkan demokrasi untuk mencapai tujuan bernegara yang lebih besar, tetapi demokrasi procedural untuk mencapai tujuan politik elit nasional.
Vitalitas demokrasi justru yang terbangun belakangan ini – meskipun masih disebut demokrasi; justru berkembang dalam bentuk lain disertai dengan fitnah, hoax dan kemunafikan. Demokrasi baru sebatas pada angka-angka electoral, tidak menyentuh bagian mendasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu kesejahteraan dan pembangunan. Dalam pergumulan demokrasi yang demikian, justru membawa kekuasaan untuk membentuk dirinya sebagai pemilik tunggal kebenaran atas semua otoritas publik.
Demokrasi Pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden cukup menggambarkan seperti yang dikatakan Jeffrey Winters sebagai demokrasi kriminal. Demokrasi politik dengan sistem pemilihan langsung belakangan memperlihatkan titik kulminasi demokrasi yang gagal, dengan munculnya banyak problem kepemimpinan yang cukup kompleks. Ada sinyal yang terdeteksi bahwa kita telah mencapai titik klimaks demokrasi, yaitu kemungkinan anarkis dan masuk perangkap oligarki.
Kandidasi presiden yang terseleksi dalam pilpres pasca berlakunya UUD 1945 hasil amandemen, menunjukkan titik terlemah demokrasi langsung. Kandidasi presiden berada dalam kendali partai politik dan pemilik modal. Tetapi, apakah demokrasi pemilihan langsung menjadi alternatif terakhir bagi demokrasi? Atau kita akan mengulangi sejarah yang kurang membanggakan pada pemilu 2014-2019?
Pertanyaan itu sulit untuk dijawab secara pasti. Tetapi, kita harus melihat ke belakang, mungkin ada pelajaran dan kearifan yang bisa kita dapat dari masalah yang kita hadapi sekarang ini. Kita bisa belajar pada eksperimen demokrasi yang pernah dilakukan oleh bangsa ini tahun 1955, atau eksperimen demokrasi 1999, dan atau sesudahnya mulai 2004 sampai saat ini.
Dalam eksperimen demokrasi ada banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi peristiwa-peristiwa kenegaraan yang cukup kompleks setelah belakunya pemilihan presiden secara langsung. Beberapa faktor yang cukup menarik dikaji oleh Drs M. Hatta Taliwang dalam sebuah tulisan yang beredar. Dia mencatat kegagalan pilpres langsung yang cukup lengkap. Menurutnya, beberapa faktor penting yang membuktikan gagalnya eksperimen Pilpres langsung, yaitu adanya dominasi partai politik, kuatnya dominasi oligarki dalam pencalonan presiden, masyarakat terbelah akibat propaganda politik di media sosial karena cenderung pilpres hanya melahirkan dua pasangan calon, alias tidak banyak/alternatif pilihan, dan biaya politik untuk melaksanakannya sangat mahal. Bagi saya, apa yang dikemukakan Hatta Taliwang itu benar – meskipun sebagian dapat dikoreksi. Sebab, melihat fenomena pilpres terakhir, cukup menggambarkan bahwa pilpres langsung hampir menghadapi kegagalan yang cukup serius.
Pemilihan presiden langsung, Kata Furqan Jurdi, telah menimbulkan masalah-masalah yang cukup serius. Misalnya, politik uang cukup menggila. Seorang calon presiden harus memiliki modal cukup besar untuk dapat ikut berkompetisi. Karena modal besar, maka mau tidak mau, harus menggunakan kekuatan pemodal (oligarki) untuk membiayai pencapresan. Kenyataan ini membuat seorang presiden terpilih disandera oleh pemilik modal. Polarisasi sosial terjadi sedemikian berbahaya akibat adanya persaingan politik para calon. Terjadi permusuhan, persekusi terhadap lawan politik dan bahkan fitnah, umpatan, berita hoax menyebar dalam bentuk yang cukup berbahaya bagi integrasi bangsa dan kohesi sosial masyarakat. Rakyat sibuk berkelahi, elite politik sibuk mengejar angka elektoral, sehingga bangsa ini lupa pada pembangunan, tapi sibuk pada suksesi.
Akibatnya masa depan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya terabaikan. Selain persoalan tersebut, Pilpres langsung membuat negara boros anggaran untuk persiapan pemilu. Setiap pemilu, apakah itu pemilihan legislatif, presiden, kepala daerah, suksesi selalu memakan biaya mahal yang harus ditanggung negara. Belum lagi biaya politik para kandidat, yang nanti kalau menang akan dibayar dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemilik modal yang menjadi “bohir politik” untuk dipergunakan kemakmuran oligarki.
Dalam sejarah, pemilihan langsung memiliki kelemahan yang tidak disepelekan. Sejarah Republik Romawi kuno, misalnya, pemilihan langsung hanya melahirkan perang dan pertumpahan darah antara oligarki politik (oligarki panglima) yang menguasai pasukan perang dan uang. Sejarah pemilihan umum adalah sejarah yang dipenuhi dengan politik uang, kemunafikan, janji palsu, serangan fajar dan pertikaian dan pemerasan. Itulah yang akhirnya meruntuhkan Republik Romawi Kuno.
Amerika sebagai moyangnya demokrasi tidak melakukan pemilihan langsung yang melibatkan massa seperti Indonesia. Pemilihan presiden dengan seleksi yang cukup ketat dan berjenjang di Amerika menangkal terjadinya pertikaian dan polarisasi politik. Bahkan dengan cara itu akan terseleksi calon-calon yang berkualitas.
Indonesia terlalu berani untuk mengambil jalan pemilihan langsung, padahal tradisi permusyawaratan telah menjadi tradisi yang hidup di masyarakat dan menjadi falsafah bangsa ini. Pemilihan langsung yang melibatkan massa ini memiliki kelemahan cukup serius. Setelah amandemen UUD, tidak ada satu kamar dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak dipilih langsung. Kesibukan suksesi politik telah menyeret bangsa ini mengabaikan pembangunan yang besar.
Sangat disayangkan, utusan golongan yang diangkat oleh presiden tanpa pemilihan umum juga dihilangkan. Kenapa semua harus dipilih? Padahal kita tahu, mengikuti pemilu artinya membutuhkan biaya besar, siapapun yang terpilih pasti akan berjuang mengembalikan modalnya. Karena itu, opsi utusan golongan harus dipertimbangkan kembali apabila jalan amandemen dibuka oleh MPR.
Di Inggris terdapat dua institusi di Parlemen yang tidak semua dipilih langsung. Wakil-wakil rakyat dipilih dari calon-calon yang diajukan partai-partai politik melalui pemilu disebut House of Commons mempunyai 659 anggota yang terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. House of Commons memegang peranan terbesar dalam menentukan haluan politik negara.
Sebanyak 659 anggotanya (dinamakan Member of Parliamant – MP), dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilakukan lima tahun sekali. Sementara di kamar lain ada House of Lords, yakni kalangan bangsawan yang diangkat bukan berdasarkan pemilihan, namun berdasarkan keturunan (Hereditary Peers). Jumlah anggota House of Lords saat ini 1222 orang, namun yang aktif hanya 360 orang. Di negara demokrasi liberal seperti Inggris, pemilihan Supreme Legislative Authority (gabungan dari House of commons dan House of Lords) tidak semuanya dipilih melalui pemilihan langsung. Sebagian dipilih dan sebagian diangkat berdasarkan gelar kebangsawanan.
Menurut Robert Michael Sebagaimana dikutip oleh Furqan Jurdi, pemilihan massa tidak memungkinkan untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas. Karena massa tidak memahami dan mengetahui secara utuh mengenai fenomena organisasi (negara) pada tingkat elite dengan figur elite itu sendiri. Itulah kenapa para pendiri bangsa memilih presiden dengan sistem quasi presidensial, bukan presidensialIsme. Maka MPR diberi kedudukan sebagai institusi negara tertinggi yang memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan presiden.
Kelemahan mendasar dari amandemen UUD 1945 adalah obsesi besar para perumus untuk membawa suksesi politik semata-mata pada pemilihan langsung tanpa mempertimbangkan nilai-nilai historis, filosofi dan sosiologis masyarakat. Seperti nilai permusyawaratan perwakilan yang menjadi falsafah kepemiluan. Amandemen UUD tahun 1999-2002 terlalu terobsesi pada perubahan politik tanpa pertimbangan nilai-nilai yang menjadi falsafah bangsa Indonesia.