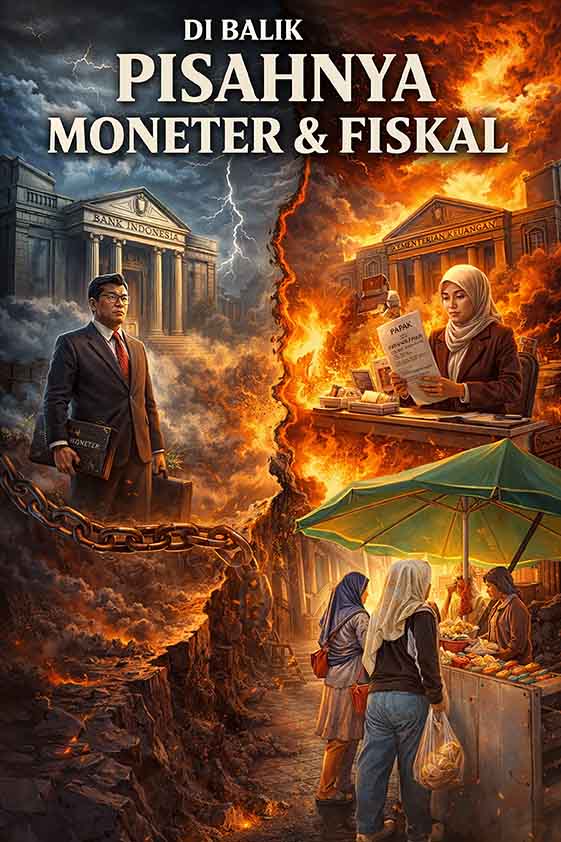KETIKA PERJUANGAN TERASA RECEH, TETAPI LANGIT TETAP MEMBISU
Oleh : Ardinal Bandaro Putiah
Perjalanan ini, jika diceritakan dari permukaan, mungkin akan terdengar remeh. Urusan bersama yang seharusnya sederhana, nyaris tidak layak disebut perjuangan besar. Tidak menyangkut revolusi, tidak pula menggetarkan kekuasaan. Hanya sebuah ikhtiar kolektif yang pada logika manusia semestinya mudah diwujudkan, kesepakatan kecil, kerja gotong royong, sedikit kejujuran, dan kesediaan untuk saling mengalah. Namun justru di situlah paradoksnya bermula. Apa yang tampak receh di mata nalar praktis, ternyata menjelma menjadi beban berat yang menekan batin, menguras energi, dan menyeret kita ke lorong panjang perenungan tentang makna perjuangan itu sendiri.
Di titik inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar mulai mengetuk kesadaran. Mengapa sesuatu yang kita niatkan sebagai urusan bersama, bahkan kita bungkus dengan klaim perjuangan di jalan Allah, justru terasa begitu sulit diwujudkan? Mengapa pintu-pintu kemudahan seakan tertutup rapat, padahal lisan kita penuh dengan doa, slogan, dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan? Apakah Allah sedang menguji kesabaran, atau justru sedang membongkar ilusi yang selama ini kita pelihara tentang diri kita sendiri?
Sering kali kita mengira bahwa kesulitan adalah bukti kemuliaan perjuangan. Semakin berat rintangannya, semakin yakin kita bahwa jalan ini benar. Namun asumsi itu tidak selalu benar. Kesulitan tidak otomatis berarti kebenaran, sebagaimana kemudahan tidak selalu berarti kesesatan. Dalam tradisi iman yang matang, kesulitan justru harus dibaca secara kritis, apakah ia lahir dari resistensi terhadap keadilan, ataukah ia muncul karena ketidakjujuran kita dalam memahami kehendak Allah?
Di sinilah perenungan menjadi tidak nyaman. Sebab sangat mungkin bahwa yang kita sebut sebagai “perjuangan di jalan Allah” sejatinya hanyalah perjuangan ego yang dibungkus ayat dan jargon suci. Kita bergerak, berteriak, menyusun strategi, dan mengerahkan massa, tetapi arah batinnya tidak pernah benar-benar kita luruskan. Kita sibuk memastikan bahwa agenda kita berjalan, namun lupa memastikan apakah agenda itu memang dikehendaki oleh Allah, atau sekadar dikehendaki oleh ambisi kolektif yang kita anggap mulia.
Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong hamba-Nya. Jika Dia berkehendak, urusan yang paling rumit pun bisa selesai dalam sekejap. Maka ketika sebuah urusan yang begitu sederhana terus-menerus menemui jalan buntu, barangkali masalahnya bukan pada kompleksitas persoalan, melainkan pada cacat kesadaran yang kita bawa. Barangkali Allah sedang menahan pertolongan-Nya, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia ingin kita berhenti sejenak, bercermin, dan bertanya dengan jujur siapa dan apa sebenarnya yang sedang kita perjuangkan?
Dalam perjalanan kolektif, sering kali kata “bersama” hanya berhenti sebagai slogan. Kita mengucapkannya dalam forum, menuliskannya dalam dokumen, dan menggaungkannya dalam pidato. Namun dalam praktik, “bersama” itu rapuh. Ia runtuh oleh ego sektoral, oleh hasrat untuk paling benar, oleh keinginan untuk paling berjasa. Kita ingin diakui sebagai penggerak, sebagai pelopor, sebagai penjaga kemurnian perjuangan. Tanpa sadar, orientasi itu menggeser pusat perjuangan dari Allah menuju diri kita sendiri.
Di titik inilah ideologi memainkan peran ganda. Ia bisa menjadi kompas yang menuntun, tetapi juga bisa berubah menjadi tameng untuk membenarkan kesalahan. Kita bersembunyi di balik ideologi, mengklaim kesucian niat, sambil menolak mengakui bahwa ada kepentingan-kepentingan kecil yang menyusup ke dalam gerak kita. Padahal ideologi sejati justru menuntut keberanian untuk mengoreksi diri, bukan sekadar mengoreksi orang lain.
Allah tidak melihat semata-mata pada kerasnya teriakan atau panjangnya barisan. Dia melihat kejujuran orientasi. Bisa jadi sebuah urusan gagal terwujud bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena kita sendiri tidak cukup jujur untuk menyingkirkan ego. Bisa jadi kebuntuan itu adalah cara Allah menyatakan penolakan-Nya terhadap metode, cara, atau bahkan niat yang kita bawa, meskipun secara lahiriah tampak Islami.
Perjalanan ini mengajarkan bahwa tidak semua yang kita niatkan baik otomatis diterima sebagai ibadah. Ada jarak yang harus ditempuh antara niat dan penerimaan. Jarak itu diisi oleh proses penyucian, penyucian niat, penyucian cara, dan penyucian relasi kita dengan sesama. Tanpa proses itu, perjuangan hanya akan berputar-putar dalam lingkaran konflik yang melelahkan, sambil terus mengulang pertanyaan yang sama, mengapa Allah tidak memudahkan jalan ini?
Pertanyaan itu, jika dijawab secara dangkal, akan melahirkan sikap fatalistik atau bahkan sinis. Kita bisa tergoda untuk berkata bahwa zaman sudah rusak, manusia sudah tidak bisa diajak berjuang, atau bahwa kebenaran memang selalu kalah. Namun jawaban semacam itu justru menutup pintu introspeksi. Ia memindahkan seluruh kesalahan ke luar diri, seolah-olah kita tidak memiliki kontribusi apa pun dalam kegagalan tersebut.
Padahal, perenungan yang jujur akan membawa kita pada kesimpulan yang lebih menyentak, mungkin kita belum layak diberi kemudahan. Bukan karena kita kurang cerdas atau kurang bekerja keras, tetapi karena ada ketidaksinkronan antara klaim perjuangan dan realitas batin. Kita ingin hasil yang besar, tetapi enggan merapikan hal-hal kecil dalam diri kita seperti keikhlasan, kesabaran, dan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Urusan yang tampak receh itu, pada akhirnya, menjadi cermin besar yang memantulkan wajah asli kita. Ia menyingkap sejauh mana kita benar-benar siap berjalan bersama, sejauh mana kita mampu menundukkan ego demi tujuan yang lebih tinggi. Ia menguji apakah “bersama” itu sungguh bermakna, atau hanya alat retorika untuk menggerakkan orang lain mengikuti kehendak kita.
Dalam konteks inilah, kegagalan bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan peristiwa ideologis. Ia memaksa kita untuk meninjau ulang fondasi berpikir, cara pandang terhadap perjuangan, dan relasi kita dengan Allah. Ia menantang kita untuk berhenti menjadikan Allah sebagai stempel legitimasi, dan mulai menjadikan-Nya sebagai pusat orientasi yang benar-benar menentukan arah gerak.
Barangkali Allah tidak mempermudah jalan itu karena Dia tidak ingin kita sampai dengan membawa beban ego yang sama. Barangkali Dia sedang memaksa kita untuk memperlambat langkah, membersihkan niat, dan meruntuhkan kesombongan yang tersembunyi di balik jargon-jargon perjuangan. Dalam perspektif ini, kesulitan bukan hukuman, melainkan rahmat yang menyamar.
Perjalanan ini, meskipun melelahkan, sesungguhnya adalah undangan untuk naik kelas dalam memahami makna perjuangan. Dari sekadar aktivisme menuju kesadaran, dari hiruk-pikuk gerakan menuju kedalaman niat. Ia mengajak kita untuk bertanya bukan hanya “apa yang kita perjuangkan”, tetapi “siapa kita ketika berjuang”.
Pada akhirnya, mungkin kita harus berani mengakui satu hal yang paling sulit bahwa tidak semua yang kita sebut sebagai perjuangan benar-benar diperjuangkan untuk Allah. Sebagian adalah perjuangan untuk harga diri, untuk pengaruh, untuk pembenaran identitas. Dan Allah, dengan kebijaksanaan-Nya, menahan kemudahan agar kita tidak semakin jauh tersesat oleh ilusi kesalehan.
Jika ada hikmah dari urusan receh yang terasa begitu sulit itu, maka hikmahnya adalah ini, Allah lebih peduli pada kualitas kesadaran kita daripada kecepatan pencapaian kita. Dia tidak tergesa-gesa seperti kita. Dia menunggu sampai kita benar-benar siap, atau sampai kita jujur mengakui bahwa yang kita kejar selama ini bukan sepenuhnya kehendak-Nya.
Perjalanan ini belum tentu berakhir dengan keberhasilan yang kita bayangkan. Namun jika ia berakhir dengan kesadaran yang lebih jernih, dengan kerendahan hati yang lebih dalam, dan dengan orientasi yang lebih lurus, maka mungkin di situlah letak kemenangan yang sesungguhnya. Sebab dalam perjuangan, yang paling berbahaya bukanlah kegagalan di mata manusia, melainkan keberhasilan yang membuat kita lupa bahwa Allah tidak pernah benar-benar kita libatkan.
Ada fase dalam perjalanan perjuangan ketika kelelahan tidak lagi bersumber dari kerja fisik, melainkan dari benturan batin. Kita lelah bukan karena kurang bergerak, tetapi karena terlalu banyak berharap. Harapan bahwa orang lain akan memahami, bahwa kawan seperjuangan akan bersikap dewasa, bahwa urusan kecil bisa diselesaikan dengan niat baik semata. Namun realitas sering kali menampar lebih keras dari dugaan. Urusan yang seharusnya selesai dalam satu meja, justru berlarut-larut, membusuk oleh prasangka, dan terperangkap dalam labirin ego yang saling meniadakan.
Di titik ini, kita mulai merasa asing dengan perjuangan itu sendiri. Ada jarak yang menganga antara idealisme yang kita yakini dan kenyataan yang kita jalani. Kita merasa telah melangkah jauh, tetapi seperti tidak bergerak ke mana-mana. Kita merasa telah berkorban, tetapi seolah tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Maka muncul bisikan halus, yang pelan-pelan bisa berubah menjadi kegelisahan teologis, mengapa Allah tidak mempermudah jalan ini?
Pertanyaan itu berbahaya sekaligus jujur. Berbahaya jika ia lahir dari kekecewaan yang tidak mau bercermin. Jujur jika ia menjadi pintu masuk untuk menguliti diri sendiri. Sebab iman yang matang tidak takut pada pertanyaan, tetapi iman yang rapuh akan bersembunyi di balik dalih kesabaran palsu. Kita sering diajari untuk menerima takdir, tetapi jarang diajari untuk membaca pesan di balik keterlambatan pertolongan.
Dalam sejarah para nabi dan pejuang sejati, Allah tidak selalu memberikan kemenangan cepat. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah membiarkan kebatilan tumbuh di dalam niat mereka. Jika pertolongan tertunda, itu bukan karena orientasi mereka melenceng, melainkan karena ada fase pembentukan yang harus dilalui. Pertanyaannya adalah apakah penundaan yang kita alami hari ini berada dalam kategori itu, atau justru merupakan tanda bahwa ada yang keliru sejak awal?
Sering kali kita terlalu cepat menempatkan diri dalam posisi “yang benar”, lalu menempatkan orang lain sebagai penghambat perjuangan. Kita menyebut mereka tidak komitmen, tidak ideologis, atau tidak memahami urgensi. Semua istilah itu mungkin benar, tetapi menjadi berbahaya ketika ia hanya diarahkan ke luar, tanpa pernah diarahkan ke dalam. Kita lupa bahwa Allah tidak hanya menguji lawan, tetapi juga menguji mereka yang mengaku berada di barisan-Nya.
Urusan receh yang sulit diwujudkan itu sesungguhnya adalah laboratorium kejujuran. Di sana teruji sejauh mana kita siap menanggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Di sana terlihat apakah kita benar-benar siap berjalan sejajar, atau diam-diam ingin berada di depan sambil tetap menyebutnya kebersamaan. Banyak perjuangan runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kelebihan ego yang tidak terkendali.
Kita sering membicarakan keikhlasan, tetapi jarang mau mengukurnya. Kita mengklaim ikhlas selama tidak ada yang mengganggu posisi kita. Begitu peran kita dipertanyakan, begitu gagasan kita tidak diambil, keikhlasan itu mulai retak. Dari retakan itulah konflik tumbuh. Dan konflik yang lahir dari ego tidak akan pernah diselesaikan oleh doa-doa yang hanya diucapkan di bibir.
Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dada. Dia tidak tertipu oleh simbol, tidak terpesona oleh jargon. Ketika sebuah urusan tidak dimudahkan, bisa jadi karena di dalamnya ada niat-niat kecil yang belum kita akui, tetapi cukup besar untuk menghalangi turunnya pertolongan. Dalam logika iman, ini bukan penghinaan, melainkan peringatan.
Perjuangan ideologis menuntut lebih dari sekadar kesetiaan pada gagasan. Ia menuntut keberanian untuk konsisten antara kata dan laku. Ideologi tanpa etika akan melahirkan kekerasan batin, bahkan jika ia dibungkus dengan dalil. Maka tidak mengherankan jika Allah “menjauh” dari gerakan yang sibuk membela kebenaran, tetapi abai pada keadilan dalam relasi internalnya.
Di sinilah letak tragedi banyak gerakan, mereka lantang berbicara tentang perubahan struktural, tetapi gagal menyelesaikan problem elementer dalam dirinya sendiri. Mereka ingin mengoreksi dunia, tetapi tidak siap dikoreksi. Mereka ingin menegakkan nilai, tetapi enggan menundukkan ego. Maka perjuangan pun menjadi bising, tetapi kosong, bergerak, tetapi tidak melaju.
Urusan bersama yang tampak sepele itu pada akhirnya memperlihatkan wajah asli kita. Apakah kita benar-benar siap berjuang bersama orang-orang yang tidak selalu sejalan dengan kita? Ataukah kita hanya nyaman bersama mereka yang mengiyakan semua kehendak kita? Perjuangan yang hanya mampu bertahan dalam ruang keseragaman bukanlah perjuangan, melainkan perpanjangan dari kenyamanan ideologis.
Allah tidak memerlukan pembelaan yang penuh kemarahan. Dia tidak membutuhkan barisan yang sibuk saling meniadakan. Yang Dia kehendaki adalah kesaksian bahwa nilai-nilai-Nya hidup dalam cara kita berinteraksi, dalam cara kita menyelesaikan konflik, dalam cara kita mengelola perbedaan. Jika kesaksian itu gagal, maka sehebat apa pun klaim perjuangan, ia akan kehilangan makna transendennya.
Pada titik tertentu, kita harus berani mengatakan bahwa mungkin Allah tidak sedang menolak tujuan kita, tetapi menolak cara kita. Mungkin Dia tidak menutup jalan, tetapi memaksa kita untuk berhenti karena kita berjalan dengan membawa beban yang tidak seharusnya. Beban itu bernama kesombongan, klaim kebenaran sepihak, dan keengganan untuk mendengar.
Perjalanan ini, jika direnungi dengan jujur, mengajarkan satu hal yang pahit bahwa niat baik tidak cukup. Ia harus disertai dengan kerendahan hati, kesediaan untuk dikritik, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Tanpa itu, perjuangan hanya akan menjadi panggung panjang bagi pertarungan ego yang melelahkan.
Maka mungkin, urusan receh yang begitu sulit itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari kemenangan palsu. Kemenangan yang diraih tanpa penyucian batin hanya akan melahirkan kesombongan baru. Allah menahan kita, agar kita tidak sampai dengan membawa penyakit yang sama, lalu menyebarkannya dalam skala yang lebih besar.
Di akhir perjalanan ini, kita dipaksa untuk merevisi definisi keberhasilan. Bukan lagi soal tercapainya agenda, tetapi soal lurusnya orientasi. Bukan lagi soal kemenangan di mata manusia, tetapi soal kejujuran di hadapan Allah. Jika kita mampu sampai pada kesadaran itu, maka sesungguhnya perjalanan ini tidak sia-sia, meskipun secara lahiriah tampak gagal.
Barangkali inilah makna terdalam dari perjuangan, bukan tentang seberapa keras kita bergerak, tetapi seberapa bersih kita berjalan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang berani kita lepaskan. Dan bukan tentang seberapa sering kita menyebut nama Allah, tetapi seberapa sungguh kita membiarkan kehendak-Nya mengoreksi langkah kita.
Jika suatu hari jalan itu benar-benar dimudahkan, semoga kita sampai sebagai hamba, bukan sebagai penuntut. Dan jika jalan itu tetap terasa sulit, semoga kita memahami bahwa kesulitan itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan panggilan untuk pulang, pulang kepada keikhlasan, kepada kerendahan hati, dan kepada makna perjuangan yang sesungguhnya.
Wallahu’alam.