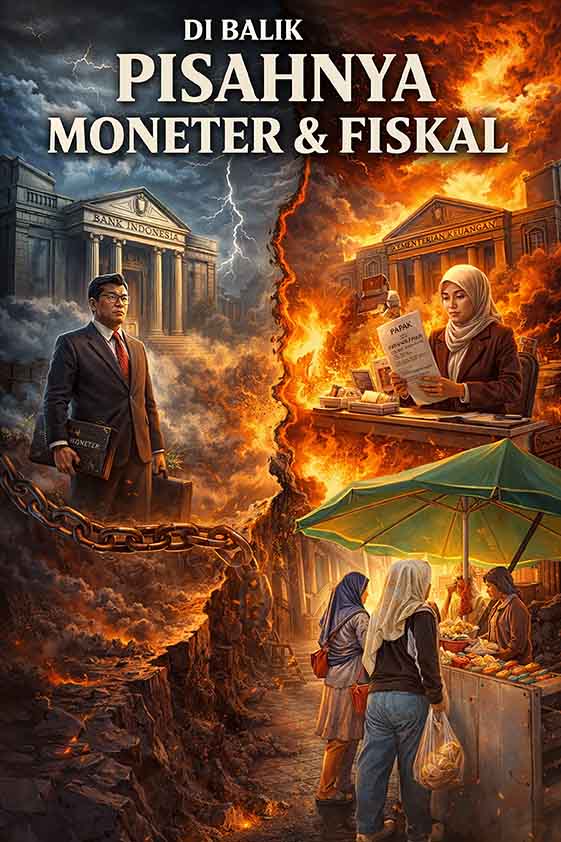Haji, Kekuasaan, dan Logistik Politik : Membaca Kasus Kuota Haji 2024 sebagai Krisis Tata Kelola Publik
Slamet Sugianto*
Update terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024 memberi pesan yang lebih tajam daripada sekadar “penetapan tersangka”. KPK tidak hanya mengumumkan siapa tersangkanya, tetapi juga mengurai *peran* dua aktor inti: Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Menteri Agama, dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA), mantan staf khusus Menteri Agama.¹ Dalam logika penindakan, kejelasan dua aktor ini sangat menentukan: ia menunjukkan bahwa perkara tidak dibaca sebagai kelalaian administratif, melainkan sebagai rangkaian perbuatan yang terstruktur—menghubungkan kebijakan pada level puncak dan eksekusi pada simpul operasional.
Namun, jika kasus ini hanya diletakkan di ruang sidang, negara kehilangan pelajaran terpentingnya. Masalah haji bukan sekadar perkara pidana individual, melainkan krisis tata kelola pelayanan publik yang memengaruhi hak jutaan warga. Haji adalah “barang publik langka” (scarce public good), sekaligus “arena kekuasaan” yang mengandung nilai ekonomi tinggi. Saat negara gagal mengontrol diskresi, pelayanan sakral berubah menjadi komoditas akses. Dan ketika itu terjadi, kita tak lagi berbicara tentang pelanggaran etik personal, melainkan tentang kegagalan sistemik.
*Dari Kebijakan Kontroversial ke Dugaan Penyalahgunaan Wewenang*
Pusat polemik adalah kuota tambahan haji 2024 yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia. Data kuota haji 2024 menunjukkan total kuota Indonesia mencapai *241.000 jemaah*, terdiri dari *213.320 kuota reguler* dan *27.680 kuota khusus*, setelah adanya tambahan *20.000 kuota* yang dibagi rata: 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.² Secara administratif, pembagian ini dipertahankan oleh sebagian pihak sebagai “kebijakan teknis”.³
Namun kritik muncul karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan kuota haji khusus sebesar *8 persen* dari total kuota.⁴ Dengan rumus itu, 8 persen dari tambahan 20.000 seharusnya hanya *1.600 kuota khusus*, sedangkan *18.400* semestinya menjadi kuota reguler. Dalam penjelasan yang dikutip sejumlah media, KPK menegaskan adanya deviasi *8.400 kursi* dari reguler ke khusus akibat pembagian 50:50 tersebut.⁵ Angka 8.400 bukan sekadar statistik; ia adalah peluang keberangkatan yang tertunda bagi ribuan jemaah reguler yang sudah menunggu lama.
KPK kemudian menetapkan YCQ dan IAA sebagai tersangka, serta menerapkan sangkaan *Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor*.¹ BPK masih menghitung nilai kerugian negara secara resmi, tetapi KPK telah menyebut perhitungan awal dugaan kerugian negara bisa melampaui *Rp1 triliun*.⁶ Dalam beberapa laporan media, KPK bahkan dikaitkan dengan narasi pengembalian uang dari penyelenggara haji khusus (PIHK) yang nilainya mencapai *Rp100 miliar* dari pihak tertentu.⁷ Terlepas dari dinamika informasi yang akan diuji di persidangan, pola umumnya jelas: kuota menjadi sumber rente, rente memerlukan akses, akses memerlukan simpul kekuasaan.
*Dua Aktor dan Konstruksi Korupsi Kebijakan*
Penegasan dua aktor (Menag dan staf khusus) menunjukkan konstruksi perkara yang lazim dalam korupsi kebijakan. Pada satu sisi ada aktor puncak yang memiliki kewenangan diskresi, di sisi lain ada aktor operasional yang mengontrol alur implementasi dan relasi lapangan. Dalam tata kelola publik modern, staf khusus sering berfungsi sebagai “gerbang akses” (gatekeeper) yang menjembatani kepentingan eksternal dengan keputusan internal kementerian. Ketika sektor yang dikelola bernilai tinggi dan minim transparansi, simpul gatekeeper menjadi titik paling rentan.
Haji memiliki semua karakter itu: kuota terbatas, permintaan sangat tinggi, biaya ekonomi besar, dan pengawasan publik lemah karena kompleksitas teknis. Itu sebabnya KPK menempatkan kasus ini sebagai korupsi yang berakar pada kewenangan dan diskresi, bukan hanya transaksi kecil.
*Kuota Haji sebagai Hak Publik : Kelangkaan yang Menentukan Keadilan*
Kita perlu mengingat satu fakta kunci: Indonesia menghadapi krisis antrean haji yang ekstrem. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama pernah menyebut jumlah antrean mencapai *5,3 juta orang*.⁸ Ada pula pernyataan pejabat publik dan data yang mengindikasikan angka antrean mencapai *5,4 juta*.⁹ Dengan kuota tahunan sekitar dua ratus ribuan, implikasinya adalah masa tunggu puluhan tahun. Bahkan Ketua Komisi VIII DPR pernah menyatakan masa tunggu rata-rata bisa mencapai *43–49 tahun*.¹⁰
Dalam kondisi demikian, setiap kebijakan yang memindahkan kuota dari reguler ke khusus—apalagi sebesar 8.400 kursi—berpotensi memperlebar ketidakadilan struktural. Kuota reguler adalah jalur mayoritas rakyat. Kuota khusus, karena biayanya lebih tinggi, lebih mudah diakses kelompok berdaya beli lebih besar. Maka, deviasi kuota bukan hanya persoalan prosedur, tetapi persoalan keadilan distributif pelayanan publik.
*Peta Aktor : Negara, Swasta, Penegak Hukum, dan Arena Legitimasi*
Kasus ini tidak bisa dipahami tanpa peta aktor yang lengkap. Ada aktor inti (Menag dan staf khusus), aktor pelaksana (Ditjen PHU), aktor penerima manfaat ekonomi (PIHK dan asosiasi travel), aktor pengawasan (DPR), aktor penindakan (KPK), aktor verifikasi (BPK), serta arena legitimasi (media dan publik). Dalam konteks sosial-keagamaan, NU menjadi faktor stabilitas yang penting, sekaligus arena reputasi.
Relasi antarpihak membentuk siklus: kebijakan menentukan distribusi kuota; distribusi membuka peluang rente; rente menarik aktor swasta; akses swasta memerlukan simpul gatekeeper; gatekeeper menuntut perlindungan politik; perlindungan politik dibangun melalui jaringan sosial-keagamaan. Sementara itu, publik dan media menciptakan tekanan moral, dan penegak hukum menegakkan koreksi.
*Relasi Presiden–Menag: Kewenangan, Delegasi, dan Zona Diskresi*
Dalam sistem presidensial, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan menteri adalah pembantu Presiden. Namun relasi kewenangan tidak berarti Presiden mengatur detail teknis. Presiden memberi arah makro; Menag mengendalikan pelaksanaan sektoral dan diskresi administratif. Dalam praktik kebijakan haji, Presiden tidak menyusun formula distribusi kuota; itu berada dalam kewenangan kementerian.
Karena itu, ketika dugaan penyalahgunaan diskresi terjadi, relasi Presiden–Menag berubah dari “delegasi kewenangan” menjadi “delegasi risiko”. Di akhir masa kekuasaan, pilihan paling rasional bagi Presiden adalah *strategic distancing*: menegaskan hormat pada proses hukum, mengambil jarak, dan mencegah perkara menjalar menjadi krisis legitimasi rezim. Pola inilah yang tampak dalam banyak kasus besar pada masa transisi.
*Politik High Cost: Logistik Kekuasaan dan Ekonomi Akses*
Di sinilah kasus haji harus dibaca dengan jujur sebagai bagian dari politik high cost. Demokrasi elektoral memerlukan pembiayaan: menjaga koalisi, merawat jaringan, mengelola dukungan. Ketika pembiayaan formal partai terbatas, sektor pelayanan publik bernilai tinggi menjadi sasaran ekstraksi rente. Haji merupakan sektor yang sangat rentan karena “akses” dapat diuangkan tanpa tampak seperti transaksi ekonomi biasa—dibungkus oleh legitimasi ibadah.
Dalam konteks ini, kuota tidak sekadar angka; ia adalah aset politik. Ia dapat menjadi alat konsolidasi dukungan, “hadiah sosial”, atau pintu transaksi ekonomi. Bila diskresi melebar, kuota berubah menjadi komoditas. Dan ketika ia menjadi komoditas, maka akan muncul aktor yang berebut kontrol: dari pejabat hingga gatekeeper.
*NU, Konflik Internal, dan Strategi Menjaga Marwah*
Dalam pembahasan sebelumnya, dinamika internal NU penting sebagai latar. NU bukan aktor hukum, tetapi aktor legitimasi sosial. Ketika seorang kader atau figur dekat NU terseret perkara, PBNU menghadapi dilema reputasi. Terlebih dalam konteks konflik internal dan fragmentasi elite, organisasi berkepentingan menjaga jarak institusional agar marwah jam’iyah tidak ikut tenggelam. Tradisi NU menegaskan pemisahan: kesalahan individu tidak ditanggung jamaah.
Sikap semacam ini bukan hanya etis, tetapi rasional. Membela individu justru memperdalam konflik internal dan membuka ruang delegitimasi kepemimpinan.
*Dampak Sistemik: Ketidakadilan, Erosi Kepercayaan, dan Delegitimasi Moral*
Dampak kasus ini bersifat sistemik. Pertama, ketidakadilan akses haji makin menguat: antrean panjang di reguler semakin panjang, sementara jalur khusus menjadi ruang percepatan. Kedua, kepercayaan publik runtuh bukan hanya pada birokrasi, tetapi pada otoritas moral negara. Ketiga, pengelolaan ibadah yang ternoda mendorong sinisme sosial: agama dianggap sekadar instrumen kekuasaan. Keempat, jika penegakan hukum melemah, masyarakat akan membaca bahwa simbol agama menjadi imunitas.
Dampak semacam ini berbahaya bagi kohesi sosial: kekecewaan religius dapat berubah menjadi kekecewaan politik.
*Hikmah Keulamaan Nusantara: Amanah Lebih Tinggi dari Simbol*
Tradisi keulamaan NU–Nusantara menyediakan refleksi etik. KH. Hasyim Asy’ari mengingatkan bahwa kekuasaan runtuh oleh kezaliman. Imam al-Ghazali menegaskan hisab penguasa zalim paling berat. Dalam perspektif ini, penegakan hukum bukan penghinaan terhadap agama, melainkan cara memulihkan amanah. Haji adalah ibadah, tetapi pengelolaannya adalah pelayanan publik yang harus tunduk pada akuntabilitas.
Jika ada satu pelajaran pokok, maka itu adalah: simbol agama tidak boleh menjadi pelindung penyimpangan; justru ia seharusnya menjadi standar moral yang lebih tinggi.
*Penutup: Reformasi yang Harus Dilakukan*
KPK sudah mengunci dua aktor inti. Namun pembelajaran terbesar berada pada reformasi sistem: (1) transparansi kuota end-to-end; (2) audit real-time dan pembatasan diskresi; (3) pemisahan tegas regulator–operator; (4) penguatan sistem daftar tunggu berbasis keadilan; (5) penataan pembiayaan politik agar sektor pelayanan publik tidak terus menjadi tambang rente.
Kasus kuota haji 2024 pada akhirnya adalah ujian tata kelola: apakah negara sanggup menjaga ibadah publik dari ekonomi akses dan logistik politik. Jika gagal, antrean 5,3–5,4 juta orang bukan hanya angka—ia akan menjadi monumen panjang ketidakadilan pelayanan negara.[]
*Catatan Kaki*
1. KPK mengonfirmasi penetapan dua tersangka Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA/Gus Alex) serta sangkaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor; DetikNews, “Timeline KPK Usut Kasus Korupsi Haji hingga Umumkan Yaqut Jadi Tersangka”, 9 Januari 2026.
2. Total kuota haji 2024 mencapai 241.000 dengan rincian 213.320 reguler dan 27.680 khusus; Kemenag NTT, “Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah…”, 25 Maret 2024.
3. Argumen pihak Kemenag terkait pembagian kuota tambahan 10.000 reguler dan 10.000 khusus; BDK Semarang Kemenag RI, 11 Juli 2024.
4. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kuota khusus 8%); Peraturan BPK RI (dokumen UU).
5. Penjelasan deviasi 8.400 kuota dari reguler ke khusus (dari tambahan 20.000); Tempo, 17 Agustus 2025.
6. Perhitungan awal dugaan kerugian negara disebut lebih dari Rp1 triliun; DetikNews, 9 Januari 2026.
7. Pemberitaan pengembalian dana Rp100 miliar oleh PIHK dalam konteks perkara kuota haji; pemberitaan SindoNews (dirujuk dalam rangka pembahasan dinamika informasi publik).
8. Antrean haji Indonesia mencapai 5,3 juta menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag; Kumparan, 24 Maret 2024.
9. Pernyataan antrean mencapai 5,4 juta dan distribusi provinsi; Amphuri, 20 November 2025.
10. Masa tunggu disebut 43–49 tahun (pernyataan Ketua Komisi VIII DPR); Mistar.id, 2 Mei 2025.