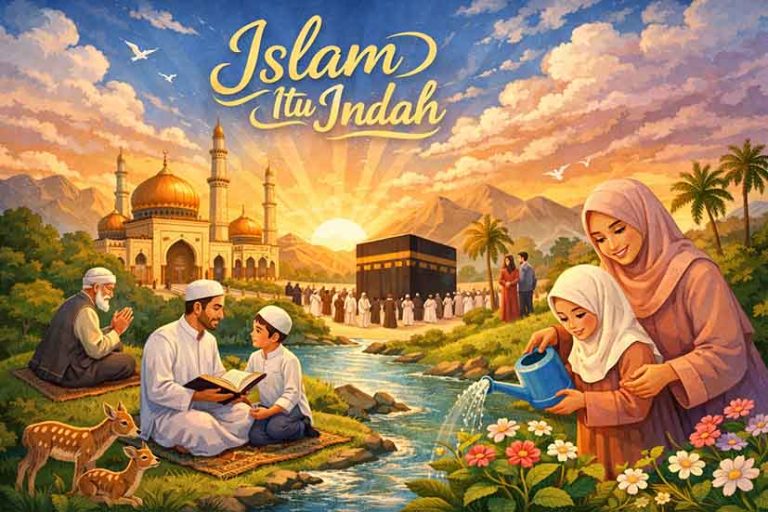DEMOKRASI MENURUT PANDANGAN ISLAM
Dr. Ahmad Yani, SH.,MH
Ketua Umum Partai Masyumi
15 Ramadhan 1446 H/15 Maret 2025 M
Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam
“Kewenangan hanyalah milik Allah. Ia memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepada-Nya. Itulah agama yang benar….”. Mereka bertanya: “apakah kami juga memiliki beberapa kewenangan?” katakanlah: “Semua kewenangan hanya milik Tuhan semata” Barangsiapa yang menegakkan dan memutuskan suatu masalah tidak berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah, maka mereka ini termasuk ke dalam orang-orang kafir”
Kajian mengenai syura dan demokrasi merupakan sesuatu yang menarik bagi kalangan ilmuwan sosial politik terutama dikalangan ilmuwan politik Islam. Karena pembicaraan mengenai kedua istilah ini lebih banyak melahirkan perdebatan yang cukup serius di antara kelompok keagamaan dan ilmuwan politik terutama, kelompok politik Islam “fundamen” yang menganggap demokrasi tidak terdapat dalam Islam dan karena itu konsep demokrasi merupakan kajian yang “menyesatkan” bagi kelompok ini. Pada pihak lain terdapat para ilmuwan dan aktifis politik Islam yang menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang baik untuk digunakan oleh umat Islam saat ini, karena tidak ada konsep politik yang lebih baik dari demokrasi, walaupun demokrasi itu datang dari Barat, tetapi tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip etik yang terdapat dalam Islam.
Kedua konsep ini pada dasarnya memiliki kesamaan tentang keterwakilan politik rakyat melalui sebuah majelis yang khusus dibentuk untuk merumuskan berbagai kebijakan umum tentang pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara, keanggotaan syura dan demokrasi merupakan pilihan rakyat secara bebas diantara calon-calon wakil rakyat yang diajukan oleh partai politik yang eksis, sedangkan perbedaan antara syura dan demokrasi terletak pada kualifikasi keanggotaan wakil-wakil rakyat tersebut. Masalah pemilihan keterwakilan politik antara syura dan demokrasi, kedua menganggap penting untuk diadakan pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu dan mereka yang terpilih merupakan pilihan rakyat dan legitimasi mereka sebagai wakil rakyat dianggap sah.
Syura : Prinsip Politik Islam
Syura bagi “sebagian” umat Islam dianggap sebagai lembaga politik yang paling penting untuk diadakan oleh negara-negara Islam (daulah Islamiyah). Beberapa gerakan Islam yang menekankan pada tradisi Islam periode awal terus memperjuangkan agar terbentuk kepemimpinan umat yang satu yang bisa menegakkan nilai-nilai Islam diatas muka bumi ini. Kita mengenal gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Thahrir di Palestina, Jamaati Islami di Pakistan, Masyumi di Indonesia. Ikhwanul Muslimin, Jamaati Islami, dan Masyumi memiliki pandangan yang positif tentang konsep demokrasi, namun mereka tetap berharap dapat membentuk sebuah lembaga politik Islami seperti syura, tetapi kondisi politik yang mereka hadapi memiliki kesulitan untuk mewujudkan lembaga syura, karena itu mereka menerima konsep demokrasi yang di isi oleh nilai-nilai Islam (demokrasi Islam atau teodemokarsi). Kekuatan-kekuatan politik Islam tersebut sangat mengimpikan sebuah negara daulah Islamiyah yang dapat menegakkan dan menjalankan nilai-nilai Islam atau syariat Islam bisa menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan dalam negara mereka masing-masing.
Dalam pandangan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin misalnya, bahwa sistem politik atau pemerintahan diselenggarakan sesuai dan dalam kerangka landasan-landasan tertentu yaitu : syura (musyawarah), hurriyah (kebebasan), musawah (persamaan), adl (keadilan), taah (kepatuhan), dan amar maruf nahi munkar. Penekanan pada syura sebagai mekanisme penyelesaian segala perselisihan faham diantara masyarakat merupakan persyaratan bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang teratur, diatas masyarakat yang teratur dan baik misi penegakan amar maruf nahi munkar dapat berjalan, diatas semua itu penegakan keadilan menjadi prasyarat penting bagi sebuah negara.
Syura sebagai mekanisme penyelesaian atas perbedaan pendapat diantara kelompok mutlak ada dan menjadi dasar bagi sebuah sistem politik Islam. Sayid Qutub menganggap urgensi syura sebagai wahana untuk menyatukan berbagai pandangan dan pemikiran yang berbeda dikalangan umat Islam, karena itu Syura merupaka hal yang mendasar dalam sistem Islam.
Umat Islam menganggap syura sebagai sesuatu wadah konsultatif dan syura merupakan metode yang berhubungan erat dengan aqidah dan syariat. Prinsip yang dibangun sebagai sebuah kerangka dasar dalam syura terletak pada pendirian yang menganggap, bahwa ketundukan kepada Allah SWT merupakan sebuah kemutlakan dan tidak ada lagi yang harus dipatuhi selain daripada Allah —dengan metode ini, masyarakat Islam tetap terjaga dari ketundukkan kepada kekuasaan dan hawa nafsu penguasa, karena banyak penguasa modern yang telah mendapat mandat dari rakyat —dan dengan mandat tersebut mereka memiliki kewenangan dalam membuat hukum dan mengatur masyarakat sesuai keinginannya.
Syura, kalau ditelusuri akan diketemukan dasar pijakan dalam Al-Quran sebagai upaya membangun masyarakat ideal, masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society), Allah menyebut masyarakat demikian, “Dan segala perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah antara sesama mereka”. Ayat ini dikomentari oleh A. Yusuf Ali sebagaimana berikut ini :
“Musyawarah”. Inilah kata-kata kunci dalam Surah ini, dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seorang yang baik dalam berbagai urusannya, sehingga di satu pihak, kiranya ia tidak menjadi terlalu egoistis, dan, di pihak lain, kiranya ia tidak dengan mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan dalam pandangan tuhan… prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal. Pemerintahan perwakilan modern adalah suatu percobaan — yang tidak bisa disebut sempurna — untuk melaksanakan prinsip itu dalam urusan Negara.
Makna penting dari syura adalah merujukan segala sesuatunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan segala problem yang dihadapi oleh masyarakat. Artinya segala sesuatu urusan —baik yang menyangkut persoalan keagamaan maupun dalam urusan sosial politik harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak ada dari keduanya sumber tersebut —baru dilakukan ijtihad sesuai dengan keyakinan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam melakukan ijtihad diharap melalui mekanisme musyawarah sebagai media konsultatif yang paling utama —dengan melibatkan banyak ulama dan ilmuwan yang berkompoten memberikan pertimbangan atas suatu permasalahan yang dihadapi.
Dengan posisi syura semacam itu akan lebih berdampak positif bagi penciptaan masyarakat ideal yaitu masyarakat bernaung dibawah kendali Tuhan. Hasil syura secara kolektif yang telah dirumuskan oleh jamaah harus mencerminka suara terbanyak atau mayoritas, keputusan-keputusan syura harus menetapkan kerangka kehidupan umat yang berorientasi masa depan. Menurut Al-Ghazali, bahwa obyek Syura mencakup dua hal ; pertama, yang ada teks dalilnya. Syura, disini dilakukan dengan tujuan untuk ditegakkan dan dilaksanakan. Kedua, yang tidak ada teks dalilnya. Untuk yang ini, semua merupakan wilayah syura, sebagai objek studi maupun sasaran aplikasi. Segalam urusan sosial, ekonomi, politik, hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum harus terlebih melalui mekanisme musyawarah para wakil umat dalam syura, karena itu syura harus ditegakkan dengan tidak keluar dari ketentuan dan jiwa Islam.
Menurut pandangan Taufiq Ays-Syawi salah seorang pemikir Islam yang khusus menulis tentang syura sebagai media yang penting bagi umat Islam
“….fitrah manusia sebagai sumber syura, yang mencakup manhaj (metode) bagi solidaritas, keadilan sosial, dan kedewasaan berpolitik akan menjadikan masa depan kemanusiaan tampil dalam bentuk menghormati prinsip kebebasan syura, dan konsisten dengan bentuknya yang komprehensif. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang masa depan syura, maka kita maksud ialah masa depan kemanusiaan dewasa, yang istiqamah diatas petunjuk Allah dan syariat-Nya”
Syura, sebagai misi kemanusiaan dalam pandangan ini —sebagai upaya untuk menjaga fitrah manusia yang telah mendapat risalah Tauhid dari Allah, bahwa manusia memiliki kebebasan sebagai fitrahnya dan untuk kelangsungan kebebasan tersebut mereka berhak terlibat dalam berbagai jaringan kerja dan masuk dalam lingkaran kekuasaan. Kebebasan dalam konteks ini —terkait langsung dengan egalitarianisme ajaran Islam —bahwa setiap orang bebas untuk berbuat apa saja —sepanjang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan yang terpenting tidak melanggar ketetntuan syariat —kebebasan seseorang —masih dibatasi oleh syariat —dan Islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas —termasuk kebebasan seseorang untuk memilih keyakinan keagamaannya.
Masa depan syura menurut pandangan ini tidak relevan dengan demokrasi yang dianut oleh Barat, karena syura tunduk kepada syariat seperti halnya umat dan negara tunduk kepadanya, sementara demokrasi memberikan kekeuasaan dan kedaulatan kepada negara dan menganggap negara bahwa negara berkuasa atas tasyri wadhi (hukum buatan manusia) secara mutlak dan tidak ada kaitannya dengan syariat. Syura hanya berlaku dalam wilayah kekuasaan legislatif dan yudikatif dan hal kekuasaan negara (pemerintahan) syura ditiadakan terutama dalam sejarah kepemimpinan Islam, Taufiq Asy-Syawi mengatakan
Peniadaan syura dalam sejarah negara-negara Islam hanyalah terbatas pada bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan di bidang legislatif dan fakih, para ulama muslim dan ahli-ahli ijtihad mereka tetap melaksanakan syura dengan bebas tanpa campur tangan pihak penguasa.
Kemandirian merupakan sesuatu yang penting bagi masa depannya sendiri serta masa depan syura misi kemanusiaan yang diembangnya. Kalangan Islam yang menganggap syura sebagai sesuatu yang penting bagi sebuah pemerintahan Islam merasa perlu menghadirkan lembaga ini dalam lembaga resmi negara
Betapapun bermakna penting —kehadiran syura dengan misi-misi kemanusiaan yang merupakan tugasnya, adalah melemahnya keyakinan kalangan Islamis terhadap teori-teori politik Islam terutama teori Islam klasik yang menekankan pada hal-hal yang simbolik dan barangkali mengandung substansi Ilahi bagi penegakan nilai-nilai ke-Tuhan-an diatas muka bumi ini. Umat Islam dengan berbagai kemajuan di bidang science dan teknologi telah menyangsikan berbagai tradisi kepemimpinan Islam, dalam catatan sejarah, ada beberapa dinasti Islam yang sempat berkuasa terutama sekali dinasti Muawiyyah dan Abbasyiyah, dua dinasti ini merupakan dinasti yang terbesar dan memiliki pengaruh luas terhadap pengembangan misi Islam. Dalam dinasti Abbasyiyah inilah Islam dapat berkembang dengan pesat hingga sampai ke Eropa, Afrika, India, hingga Asia —suatu perkembangan yang luar-biasa dalam dakwah Islam —selain syiar Islam dikembangkan secara luas dari dinasti sini juga —banyak lahir ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama Islam terkenal seperti empat Imam mazhab, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Imam Al-Gazali dan lain-lain. Islam pada zaman itu menjadi berkembang secara meluas dengan berbagai keunggulan dan kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.
Namun kepemimpinan dalam dinasti-dinasti tersebut dikenal sangat tidak “demokratis” atau kurang mengindahkan nilai-nilai Islam termasuk syura karena mereka menjadi penguasa berdasarkan garis keturunan (kerajaan) dengan sistem kesultanan. Nilai-nilai Islam dalam dinasti-dinasti tersebut —yang sempat berjaya di masa silam tidak di indahkan, bahkan dinasti Ustmani di Turki yang terakhir masih melanggengkan sistem kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Jadi para pemikir baru Islam menganggap sistem pemerintahan Islam dengan mengembangkan kepemimpinan tunggal (khilafah) dan model permusyawaratan melalui syura dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Islam —walaupun dalam teori —kepemimpinan tunggal Islam adalah sangat unggul —namun dalam prakteknya jauh dari apa yang telah termaktub dalam berbagai kitab Islam —terutama karya-karya pemikir Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik.
Dengan kondisi demikian, mereka menerima sistem politik demokratis sebagai sistem politik pemerintahannya. Sistem politik ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dan mendirikan partai politik demi memperjuangkan cita-cita politiknya. Sistem politik demokrasi kerakyatan dengan kebebasan yang luas kepada masyarakat telah membawa kepada berbagai implikasi negatif bagi masa depan misi kemanusiaan, menurut Taufiq bahwa proses demokrasi Barat ketika kapitalisme membuka pintu luas bagi setiap faktor kerusakan moral, penyimpangan sosial, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
Demokrasi memberikan kekuasaan kepada mayoritas dan bahkan memunculkan diktator partai yang telah mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat sehingga kekuasaan mereka peroleh. Sistem demokrasi dalam banyak prakteknya membatasi ekspresi politik golongan agama dalam asosiasi politik mereka, sehingga partai yang berdasarkan agama tidak bisa tumbuh secara bebas dalam sistem demokarsi. Dalam demokrasi pancasila kelompok-kelompok politik berdasarkan agama “dihilangkan”, peran politiknya harus berdasarkan paham nasionalisme dan menonjolkan ideologi negara dan bukan ideologhi keagamaan, politik kooptasi negara terhadap masyarakat berlangsung lama dalam alam demokrasi Pancasila. Berikut pandangan Taufiq mengenai demokrasi
Demokrasi pada sebagian sistem pemerintahan kita melarang didirikan partai-partai agama dan membiarkan pengdiskreditan terhadap Islam dan kaum muslimin. Umat Islam dilarang menerbitkan surat kabar sebagai sarana mengemukakan pendapat atau untuk melakukan pembelaan diri. Bukan hanya itu, mereka pun dihilangkan mendirikan lembaga politik atau partai yang menampilkan pendapat mereka, meski sekedar menangkis orang-orang yang menyerang mereka dalam surat-surat kabar pemerintah serta propagndis asing. Demokrasi membela hak orang munafik dan orang-orang yang tidak beragama, mereka menguasai pusat-pusat informasi dan politik di bawah perlindungan militer sehingga mereka senantiasa mampu memonopoli pusat-pusat kekuatan pers setempat.
Betapa sistem demokrasi yang dilihat dari perspektif Islami yang mengharapkan syura dan khilafah sebagai mekanisme penegakan prinsip-prinsip politik Islam sulit untuk bisa survive. Jadi demokrasi merupakan sesuatu yang hanya akan diperintah oleh rezim berdasarkan motif-motif keagamaan sehingga umat Islam tidak bisa menegakan nilai-nilai agama mereka. Pada awal milenium ketiga ini, betapa kekuatan-kekuatan demokrasi dunia melancarkan serangan terhadap umat Islam melalui media-media dan surat-kabar yang mereka miliki. Pemerintahan demokratis Indonesia juga sedang “menyerang” kelompok-kelompok Islam “militan”, Islam “radikal”, Islam “galak” yang disebutnya sebagai biang dari segala kekacauan dalam negeri. Tindakan pemerintah Indonesia terhadap kalangan tersebut didasarkan atas tekanan dunia international yang mengklaim diri sebagai negara yang demokratis.
Dalam sistem politik demokratis, mendasarkan anggapan pada pemikiran dan rasio manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kita sebagai manusia memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi, namun kemampuan akal manusia bersifat terbatas, subyektif meaning juga dominan, keadilan sulit ditegakkan dan lain-lain. Dari sisi inilah Islam memberikan garis besar kepada umatnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan contoh dari Nabi Muhammad s.a.w. dengan mengikuti Sunnah-Nya. Kedua sumber ini merupakan rujukan utama umat Islam dalam mengatur kehidupan sosial politik mereka diatas dunia ini, sehingga kehidupan ini bermakna bagi penegakan misi kemanusiaan.
Syura sebagai misi umat Islam yang berbeda dengan demokrasi sebagaimana yang telah disinggung diatas adalah berusaha mewujudkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang proporsional antara kebebasan individu dan jamaah dari satu sisi, dan keberadaan kekuasaan umum yang mewajibkan adanya batas-batas atas kemerdekaan yang fitri dari segi yang lain. Jadi syura merupakan lembaga yang mengatur kebebasan individu dan kekuasaan pemerintahan negara secara proporsional, keduanya harus dapat berjalan secara wajar dan seimbang. Pemerintah (negara) tidak boleh membatasi kebebasan individu sepanjang kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan misi dari risalah Islam, dan masyarakat juga harus merelakan segala sesuatunya diatur oleh negara sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Islam dan kehendak umat yang berkembang. Antara negara (pemerintah) dengan masyarakat harus terdapat keseimbangan agar dapat mewujudkan masyarakat yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur.
Kelembagaan politik Islam seperti parlemen adalah sebuah majelis yang mengatur segala urusan kaum muslimin yang ketentuan-ketentuan normatifnya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, mereka tidak memiliki otoritas untuk membuat aturan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, jadi model keterwakilan demikian kalau dapat disebut sebagai teodemokrasi (demokrasi ke-Tuhanan). Sebuah sistem politik yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah harus berdasarkan kepada tiga hal terutama yang berkaitan dengan konsep kedaulatan dan kewenangan membuat hukum seperti yang dikatakan oleh Al-Maududi; pertama, kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan Islam berada di tangan Tuhan dan tidak ada seorangpun yang berdaulat; kedua, wewenang legislatif dan pemberi hukum sejati hanya berada pada Allah SWT dan manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah aturan hukum Allah walaupun dengan suara mayoritas; ketiga, pemerintahan dalam negara Islam harus ditaati sepanjang mereka menegakkan hukum-hukum Allah.
Seorang pemikir Islam yang terkemuka lainnya, Muhammad Iqbal mengemukakan konsep politiknya mengenai demokrasi yang walaupun demokrasi itu sendiri bagi tidak begitu cocok untuk dipraktekkan, tetapi Iqbal menjelaskan gagasan ideal tentang demokrasi seperti dikatakan “…adanya suatu demokrasi dari individu-individu yang bersifat khas, dan dipimpin oleh individu yang sangat khas pula”. Pelaksanaan demokrasi dalam sistem politik Islam bagi Iqbal haruslah ada seseorang yang memiliki kemampuan lebih dan menonjol dari sebahagian yang lain, sehingga memungkinkan demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai ke-Tuahanan dapat terlaksana. Iqbal juga mengatakan, bahwa demokrasi sebuah sistem yang menghitung tetapi tidak menimbang orang
Inilah yang menjadi pedoman politik Islam yang bersumber pada Allah, sedangkan Barat menekankan kepada kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berdaulat penuh dalam demokrasi Barat adalah rakyat secara mayoritas, artinya kekuasaan mayoritas, merekalah yang akan membuat aturan hukum dan berbagai perangkat perundangan-undangan yang diperlukan oleh suatu negara modern mereka yang demokratis.
Demokrasi Dalam Modern Nation-State
Anders Uhlin mengatakan tentang demokrasi Indonesia “The “Third Wave” has obviously failed to have any profound impact on Indonesias political development, as no transition to democracy has take place. In fact the authoritarian New Order regime has proved almost immune to the near global democratization wave of the last decade”. Uhlin adalah seorang peneliti dan pemikir politik tentang Indonesia yang memberikan perhatian kepada praktek politik rezim baru terutama paroh terakhir rezim tersebut berkuasa, dimana mesin politiknya —Golkar meraih suara mayoritas mutlak 75 % pada Pemilu 1997 suatu angka yang cukup dramatis dicapai oleh kekuatan politik dalam kehidupan politik negara yang disebut demokratis dimanapun. Fenomena politik Orde Baru merupakan fenomena lain dari sebuah sistem politik yang disebut demokratis, karena kondisi politik yang personal dan kekuatan otoriter memang menyulitkan berbagai kelompok masyarakat untuk tampil sebagai sebuah masyarakat yang mandiri dan independen. Fenomena tersebut dapat disebut sebagai penyimpangan dari gagasan demokrasi yang semestinya mencerminkan kehendak masyarakat, Uhlin telah dengan baik memberikan pndangannya mengenai dinamika pemikiran politik kalangan intelektual Indonesia yang mengembangkan gagasan demkratis dialam kehidupan politik yang otoriter dan Uhlin banyak memberikan perhatian kepada pemikir-pemikir muslim sebagai kelompok masyarakat yang mayoritas.
Sepintas dapat kita lihat bahwa demokrasi dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan oleh seluruh rakyat dan bukan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Artinya seluruh rakyat memiliki hak yang sama dalam soal pembuatan keputusan, mendapatkan kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintahan serta parlemen (lembaga perwakilan). Keputusan yang dibuat oleh mayoritas hanyalah suatu piranti prosedural untuk mengatasi perselisihan pendapat ketika metode-metode lain (diskusi, amandemen, kompromi) telah dipakai sepenuhnya tetapi gagal. Keputusan mayoritas harus dianggap sebagai keputusan yang demokratis sepanjang tidak membuat kalangan minoritas semakin tidak berdaya.
Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat —yang berkuasa penuh adalah rakyat —dan merekalah yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dan berbagai piranti prosedural yang mengatur pola kehidupan mereka dalam masyarakat. Rakyat memiliki otoritas penuh untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka, karena rakyat memiliki kebebasan. Pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara bebas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan politik, ekonomi dan bahkan atas dasar pengaruh tokoh-tokoh politik, pemimpin yang dipilih tersebut dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Demokrasi juga mengklaim bahwa tidak ada lagi pemerintahan selain pemerintahan oleh rakyat atau “kedaulatan rakyat”.
Di Athena (Yunani) sebagai kota cikal-bakal lahirnya democracy, dalam masyarakat Athena dikenal dengan dua istilah demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi klasik. Demokrasi langsung, bahwa rakyat ikut ambil bagian secara langsung dalam pemerintahan itu sendiri melalui perkumpulan majlis (assembly) atau Ecelesia. Demokrasi langsung bermakna sebagai wujud langsung hak-hak setiap rakyat atau individu untuk masuk ke dalam majlis (assembly) tanpa melalui proses pemilihan seperti yang lazim dalam masyarakat demokratis modern, mereka menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam majlis tersebut, karena itu merupakan hak mereka. Sedangkan demokrasi klasik tidak mengenal kebebasan dalam pengertian modern. Setiap individu harus tunduk dan taat kepada negara, sebagai contoh, tidak ada jaminan kebebasan beribadah bagi individu, tetapi mereka tunduk dan taat kepada negara walaupun negara merampas hak-haka azasi mereka dan memasung kebebasan setiap individu. Keikutsertaan rakyat dalam kekuasaan belum sampai pada tingkat dimana memiliki wewenang membuat undang-undang yang memungkinkan setiap individu mendapat kebebasan, artinya pemerintahan dalam sistem demokrasi klasik hanya mendasarkan pada persamaan didepan hukum negara dan belum sampai kepada pertimbangan-pertimbangan rasional, seperti bagaimana mewujudkan kebebasan setiap individu dalam menjalankan keyakinan agamanya dan bentuk keadilan serta kaidah moral yang mesti diatur bersama oleh rakyat dalam negara.
Model praktek demokrasi yang dilakukan oleh rakyat Athena (Yunani) seperti tergambar diatas masih sangat sederhana dan belum menggunakan instrumen-instrumen politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya serta keamanan yang canggih. Semua rakyat berhak untuk terlibat dalam setiap perdebatan majelis-majelis yang menurut mereka sebagai wadah bagi pembicaraan urusan bersama masyarakat, mereka juga mengatakan —kita juga bergiliran dalam melaksanakan tugas pemerintahan kita itu : dalam Dewan, yang mempersiapkan acara majelis, dalam badan juri warga negara, dan dalam badan-badan penegak hukum yang hampir tidak terhitung jumlahnya. Bagi kita (rakyat Athena), demokrasi tidak hanya membuat keputusan-keputusan dan undang-undang yang penting di dalam majelis, demokrasi juga bertugas dalam jabatan negara.. Pelaksanaan demokrasi dalam masyarakat Athena cukup sederhana dengan proses pelibatan seluruh warga dalam berbagai badan yang dibentuk untuk mengurus kepenting-kepentingan bersama di antara warga negara. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah demokrasi langsung, artinya rakyat terlibat langsung dalam proses politik tanpa mereka mewakilkan kepada orang lain. Istilah keterwakilan politik mayoritas atau istilah-istilah lain yang kerapkali menjadi alat legitimasi tindakan rezim demokratis modern belum dikenal pada masyarakat Athena. Kebijakan politik mereka sedapat mungkin mencerminkan faksi-faksi atau suku-suku yang berada dalam masyarakat, mereka juga menggunakan ukuran-ukuran mayoritas dalam mengambil kebijakan politik bersama dalam masyarakat mereka.
Dalam hal keterwakilan politik mayoritas sebagai prinsip dasar yang dianut oleh demokrasi dan negara harus menerapkan kebijakan politik yang proporsional terhadap rakyatnya, artinya aspirasi dan kondisi masyarakat yang mayoritaslah yang menjadi perhatian utama dan bukan berarti kaum minoritas tidak di dengar, melainkan cerminan dari kebijakan politik negara berdasarkan kepada kepentingan mayoritas sebagaimana yang telah diterapkan oleh masyarakat Yunani dalam bentuk demokrasi langsung, dimana rakyat ikut secara bebas dalam berbagai rapat-rapat majlis. Namun praktek demokrasi dalam banyak negara modern saat ini justru tidak “demokratis”, karena mereka menggunakan standar ganda dalam menerapkan demokrasi. Sebagai contoh dalam negara yang mayoritas kaum muslimin berbagai kebijakan politik negara justru tidak mencerminkan kehendak mayoritas, maka hal ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak demokratis, tidak adil dan tidak berdasarkan kaidah moral.
Keputusan yang diambil dalam mekanisme demokrasi untuk menjamin kepentingan bersama, mengenai tujuan yang hendak dicapai, mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi, mengenai pembagian tanggungjawab dan keuntungan di antara para anggota. Itu semua merupakan keputusan kolektif, yang dibedakan dari keputusan-keputusan individual yang dibuat oleh orang yang hanya mewakili diri mereka sendiri. Praktek-praktek politik yang tidak demokratis di banyak negara yang mengaku demokratis dewasa ini justru tidak lagi mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang mereka anut di negaranya —walaupun demikian menurut para analis politik modern —cara demikian jauh lebih baik dari apa yang pernah dilakukan dalam pemerintahan-pemerintahan Islam klasik yang menerapkan sistem politik monarki.
Sistem demokrasi seperti yang di anut oleh Eropa misalnya, bahwa multi partai politik sebagai cermin dari kebebasan adalah sesuatu yang mutlak ada dan mereka memiliki ikatan-ikatan yang paling pokok dari ikatan-ikatan tersebut ; pertama, ikatan komitmen pada konstitusi dan undang-undang; kedua, ikatan-ikatan untuk memelihara peraturan umum negara; ketiga, ikatan-ikatan untuk menjaga pilar-pilar pokok masyarakat, seperti ideologi yang dianut oleh mayoritas dan sistem politiknya; keempat, ikatan-ikatan untuk memelihara kedaulatan negara dan kewibawaanya; kelima, ikatan-ikatan untuk memelihara hak orang lain; keenam, ikatan-ikatan untuk menjamin kebebasan umum; dan ketujuh ikatan-ikatan untuk memelihara kebebasan keluarga. Multi partai politik yang hidup dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan dari berbagai spesies yang memegang prinsip-prinsip kedaulatan negara.
Ikatan-ikatan yang menjadi kerangka kerja sistem demokrasi di Eropa adalah ikatan-ikatan yang hanya menyangkut persoalan kebaikan kehidupan keduniaan semata, tidak ada satupun penegasan mengenai pentingnya negara menjamin kelangsungan kehidupan keagamaan seseorang. Ikatan-ikatan tersebut merupakan sesuatu yang perlu dan penting untuk ditetapkan sebagai kewajiban bersama warga negara —namun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di akhirat —yang menurut pandangan kalangan agamawan —pasti akan datang —juga mesti diatur oleh negara secara bersama —sepanjang berkait langsung dengan kitab suci —bukan yang baru dan tidak merujuk kepada kitab sucinya. Tanggungjawab warga negara tersebut (dalam konteks kepentingan keduniaan) merupakan hasil dari konsensus yang diselenggarakan dan melibatkan seluruh rakyat, itulah yang menjadi keputusan kolektif negara, karena merupakan keinginan mayoritas.
Banyak keputusan kalangan mayoritas di negara-negara Barat membuat kalangan minoritas baik karena ras, etnik, suku, dan agama menjadi takut dan hidup di negara yang mengaku demokratis tetapi praktek politiknya sangat tidak demokratis, diskriminaasi, dan rakyat minoritas hidup dalam kondisi yang tidak bebas, penuh dengan ketakutan. Diskriminasi warna kulit di United State of America (USA) merupakan contoh terbaik bagi praktek yang tidak demokratis oleh negara yang mengaku demokratis. Di negara yang mayoritas agama (Islam) seperti Indonesia, ketika hendak memperjuangkan penegakkan syariat Islam sebagai representasi dari mayoritas penduduk Indonesia dan perjuangan itu dianggap demokratis, karena mewakili kaum mayoritas, maka banyak pihak yang menentangnya —tidak kurang elit Islam sendiri yang menjadi jurubicara bagi penolakan tersebut —diluar muncul berbagai komentar terutama kalangan Barat —bahwa hal itu dianggap sebagai diskriminasi terhadap kalangan minoritas agama lain. Padahal syariat Islam yang hendak diwujudkan bukan sesuatu yang menakutkan tetapi merupakan dasar praktek agama bagi umat Islam dan tidak untuk umat yang non Islam.
Kondisi politik otoritarinaisme menurut pandangan ini (demokrasi) adalah merupakan “penjara” bagi tumbuhnya kehidupan yang bebas, penguasa cenderung bersifat diktator dan tidak memberi ruang bagi pemikiran-pemikiran alternatif. Menurut Max Weber seorang sosiolog terkemuka mengatakan, bahwa setiap sistem (dominasi) berupaya untuk memapankan dan menanam keyakinan terhadap legitimasinya atau, bahkan secara lebih abstrak, bahwa hadir kebutuhan umum yang dapat terlihat dari setiap kekuasaan….. untuk menjustifikasi diri sendiri — tak dengan sendirinya berarti bahwa sebuah sistem dominasi tak akan dapat mempertahankan diri tanpa keyakinan ini. Setiap rezim dalam setiap negara baik yang demokratis ataupun yang tidak membutuhkan legitimasi, dukungan, atau paling tidak persetujuan tanpa protes agar dapat bertahan, bila sebuah rezim kehilangan legitimasi ia akan berusaha memproduksi legitimasi atau ia akan jatuh.
Dalam rezim totalitarianisme kerapkali loyalitas rakyat diperagakan secara hipokrit oleh individu-individu atau oleh seluruh kelompok pada landasan yang sepenuhnya oportunistis, atau dijalankan dalam praktek untuk alasan-alasan kepentingan pribadi, perilaku dan sikap yang ditampilkan oleh individu dalam konteks ini lebih disebabkan oleh tidak adanya alternatif yang pantas dilakukan secara bebas sehingga Weber menyebut, bahwa orang akan tunduk dari kelemahan dan kepasrahan karena tak ada alternatif yang dapat diterima. Setiap rezim pada prinsipnya tetap akan membutuhkan legitimasi agar tetap bertahan. Cara bagi setiap rezim untuk tetap survive beragam, ada yang menggunakan cara demokratis dan adapula yang menggunakan kekerasan dan dominasi
Dengan kesedian sebuah negara-bangsa untuk mempraktekkan demokrasi dalam kehidupan politik mereka —adalah sepenuhnya membantu segenap warga negara dari hegemoni kekuasaan oleh rezim —sehingga menurut Robert Dahl akan memberikan implikasi-implikasi di antaranya: menghindari tirani, hak-hak azasi, kebebasan umum, menentukan nasib sendiri, otonomi moral, perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, persamaan politik, mencari perdamaian, dan kemakmuran. Menurut Dahl, demokrasi adalah merupakan cara terbaik untuk memerintah negara bila dibandingkan dengan cara-cara yang lain, hal tersebut didasarkan kepada alasan-alasan : pertama, demokrasi menolong tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia pernah dicatat, termasuk di zaman kita, para pemimpin yang didorong oleh rasa gila kebesaran, kelainan jiwa, kepentingan pribadi, ideologi, nasionalisme, keyakinan agama, perasaan keunggulan batin, atau hanya emosi dan kata hati, telah mengeksploitasi kemampuan negara yang luar biasa melalui pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Korban yang ditimbulkan oleh pemerintahan yang lalim ini tidak kalah dari korban yang ditimbulkan penyakit, kelaparan dan perang. Kedua, negara menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak azasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. Keempat, demokrasi membantu untuk melindungi kepentingan pokok mereka, karena hampir semua orang akan memerlukan kelangsungan hidup, makanan, tempat bernaung, kesehatan, cinta, rasa hormat, rasa aman, keluarga, teman-teman, pekerjaan yang memuaskan, waktu luang, dan lain-lain. Demokrasi juga menjamin kesempatan dan kebebasan kepada setia orang untuk membuat berbagai organisasi yang memiliki tujuan, pilihan, perasaan, nilai, komitmen dan keyakinan. Kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri. Dalam sebuah negara yang demokratis seseorang dipastikan akan memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, berdiskusi, memberi pertimbangan, bernegosiasi, dan berkompromi yang dalam keadaan terbaik dapat menunjukkan hukum yang akan memuaskan semua orang. Keenam, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral. Ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. Kedelapan, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain. Kesepuluh, negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
Pemerintahan demokrasi tidak terlepas dari kelemahan seperti pemerintahan lain, pemerintahan demokratis terkadang bertindak secara tidak adil dan kejam terhadap rakyat yang berada di luar tapal batas negaranya, orang-orang yang tinggal di negaranya — orang-orang asing, pendatang baru —bahkan pemerintahan demokratis menurut Dahl tidak kurang jeleknya dari pemerintahan yang demokratis dalam memperlakukan warga negara asing yang tinggal dalam negeri mereka, bahkan melupakan prinsip moral yang mendasar berkaitan dengan persamaan politik di antara warga negara yang disebutnya demokratis. Praketk politik negara demokratis yang disebut kurang dapat berlaku adil dan jujur dalam berbagai sikap dan tindakan politik mereka terhadap pihak lain adalah merupakan fenomena umum dalam banyak isu global mengenai HAM dan demokrasi mutakhir, pasca runtuhnya WTC, dimana AS dengan begitu mudah menuduh dan menyerang negara lain atas nama demokrasi dan HAM, padahal yang dilakukan tersebut tanpa ada fakta otentik mengenai tuduhan mereka terhadap suatu negara yang hendak mereka serang.
Walaupun dalam sistem demokrasi tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi menurut Robert Dahl masih terdapat berbagai keuntungan yang memungkinkan suatu negara memilih konsep demokrasi sebagai sistem politik negaranya seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Efektifnya partisipasi masyarakat dalam suatu negara yang demokratis akan diukur dengan luanya wilayah jangkauan negara, Dahl mengatakan : “semakin kecil unit demokrasi, semakin besar kemungkinan untuk partispasi warga negara dan semakin sedikit kebutuhan warga negara untuk menyerahkan keputusan-keputusan pemerintahan kepada para wakilnya. Semakin besar unit tersebut, semakin besar kapasitasnya untuk menghadapi permasalah an-permasalahan yang penting bagi warga negaranya, dan semakin besar pula kebutuhan warga negara untuk menyerahkan keputusan-keputusan kepada para wakilnya”. Tingkat efektifnya partisipasi langsung warga negara dalam berbagai proses politik adalah sangat tergantung dari luasnya wilayah negara, kalau suatu negara luas wilayahnya terbatas dan kecil, maka keikutsertaan rakyat dalam berbagai pengambilan keputusan politik akan besar dan apabila suatu negara dengan luas wilayah yang besar, maka keterlibatan rakyat juga terbatas
Konteks demokrasi di AS misalnya, kita dapat melacak ketika deklarasi Kemerdekaan AS menunjukkan dengan jelas tentang konsep demokrasi pluralis yang cukup signifikansi dengan konsep kesetaraan dan kebebasaan di antara umat manusia. Disebutkan pula, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, dan mereka telah dikaruniai oleh sang Pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari mereka, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan usaha untuk mencapai kebahagiaan. Apa yang dirumuskan dalam deklarasi kemerdekaan AS tersebut secara eksplisit mengharuskan siapa saja, termasuk Amerika, untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan intrinsik yang dimiliki setiap manusia dan bangsa, serta menjadikan nilai-nilai itu sebagai dasar dalam melakukan kerjasama, dan bukan mengembangkan permusuhan sehingga kehidupan yang manusiawi dan bermoral dapat diraih oleh bangsa mana pun di dunia ini. Dalam sejarah negara AS, mereka memang membela demokrasi seperti misalnya Abraham Lincoln dan beberapa penguasa AS —walaupun yang mereka bela dan pertahankan sesuatu yang tidak “valid”, artinya dalam perspekstif Islam mereka menonjolkan kebebasan dan demokrasi mayoritas. Tetapi penguasa AS belakangan ini justru menjadi penguasa yang hipokrit dan cenderung menjadi manusia kerdil yang hanya bisa melihat dirinya yang paling demokratis dan pembela HAM, padahal yang dilakukan sesuatu yang sangat hina dan jauh nilai-nilia kemanusiaan dan kebebasan sebagaimana yang diperjuangkan oleh para pendahulu mereka. Inilah potret negara demokratis yang sangat diktator dan menjadi negara terorisme yang membahayakan kehidupan negara lain.
Dalam sistem demokrasi modern, proses pengambilan keputusan politik harus didasarkan kepada kehendak mayoritas dan bukan penekanan minoritas terhadap kepentingan mayoritas. Sebuah rezim demokratis dalam konsep politik Barat akan memberi ruang bagi kaum mayoritas untuk mengisi lembaga-lembaga perwakilan secara adil dan atura-aturan hukum yang merupakan cerminan dari kehendak mayoritas. Sementara bagi rezim otoritarianisme, bahwa kebebasan ditutup diganti oleh keterbatasan dan kontrol serta dominasi sehingga public sphere disumbat yang menyebabkan pemikiran-pemikiran alternatif sulit untuk tumbuh dan menjadi pertimbangan bagi suatu kebijakan politik. Model pemerintahan demikian yang hendak diwujudkan melalui konsep demokrasi —sehingga rakyat dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik —menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kasus praktek politik Indonesia dengan demokrasi Pancasila memperlihatkan cara-cara yang tidak demokratis —sejak pemerintahan Soekarno dan Soeharto —walaupun pada zaman Habibie ada upaya yang signifikan untuk membuka kepada banyak kemungkinan bagi keterlibatan warga negara secara luas —zaman Gus Dur juga lebih memperkuat basis masyarakat —sedangkan Megawati masih belum menemukan cara-cara yang lebih maju dari para pendahulunya. Dalam demokrasi Pancasila Orbe Baru —kehendak mayoritas dapat dihalangi oleh kepentingan-kepentingan minoritas dengan didukung oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan ekonomi, politik, hukum dan sosial. Kuatnya ketergantungan kepada kapitalisme Barat yang mempunyai ideologi non-Islam telah membawa pengaruh bagi melunaknya pandangan dan sikap para elit Islam di tanah air. Para pemimpin bangsa sebelum Orde Baru justru jauh lebih maju dalam menerapkan sistem politik yang disebut demokratis —bahkan tokoh-tokoh Islam memiliki sikap yang arif seperti yang nampak dari tokoh Masyumi Muhammad Natsir yang mengemukakan gagasan tentang demokrasi teokrasi (demokrasi Islam), artinya demokrasi diatas dasar prinsip-prinsip dasar agama (Islam), bagi Masyumi demokrasi bukan konsep politik yang harus dijauhi tetapi demokrasi harus diwarnai dengan nilai-nilai Islam.
Syura dan Demokrasi Dalam Timbangan
Antara dua istilah yang dipakai ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan dari sudut pandang masing-masing. Syura memandang demokrasi sebagai sistem politik modern Barat yang mendasarkan diri pada kekuasaan mayoritas yang didasarkan kepada pemilihan umum oleh rakyat (artinya rakyat berdaulat penuh atas sistem demokrasi yang berlaku). Kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan prinsip terpenting dari sistem politik yang demokratis. Namun banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai dasr pemerintahan di negaranya, tetapi cara-cara yang dilakukan justru tidak demokratis seperti diskriminasi terhadap suku, ras, etnik dan agama yang minoritas, kita mengetahui bahwa di AS sebagai negara yang paling demokratis tetapi yang terjadi disana adalah praketk diskriminatif terhadap warna kulit, kulit hitam diberlakukan secara tidak terhormat. Kalau dilacak lebih jauh, kita akan menemukan beberapa tindakan penguasa negara demokratis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mereka sendiri gunakan sementara demokrasi berlandaskan kebersamaan, kebebasan.
Sementara syura yang mengaku sebagai sistem politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusia dan risalah Islam juga tidak terlepas dari penyimpangan dalam sejaran kepemimpinan Islam (khilafah Islamiyah). Para pemimpin Islam masa lalu telah berbuat sewenang-wenang terhadap umat yang dipimpinnya, bahkan umat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai peristiwa politik. Dinasti-dinasti yang berkuasa dalam kepemimpinan Islam masa lalu mengembangkan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan dan orang diluar garis keturunan raja tidak mungkin mendapat kekuasaan tersebut, kecuali melalui perang dan perebutan kekuasaan secara paksa. Orang diluar kerajaan, walau pintar dan cerdas serta alim bagaimanapun tidak akan bisa menjadi penguasa negara, karena sistem politik kerajaan dikembangkan. Sistem demikian tidak mencerminkan ajaran Islam yang memandang semua manusia adalah sama dan sederajat dan mempunyai kesempatan menjadi penguasa diatas muka bumi ini.
Antara syura dan demokrasi terdapat beberapa kesamaan prinsipil yaitu sama-sama memerlukan sebuah lembaga keterwakilan politik untuk membuat berbagai kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam suatu negara yang demokratis. Keterwakilan politik ini merupakan prasyarat terpenting bagi penyelenggaran negara yang baik. Selain itu, syura dan demokrasi masing-masing menggunakan mekanisme pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh rakyat untuk memilih anggota perwakilan, sehingga mereka yang menjadi representase politik dari rakyat merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membela kepentingan mereka terutama proses pembuat kebijakan publik.
Selain persamaan syura dan demokrasi terdapat beberapa perbedaan yang cukup mengganggu keduanya dapat berbaur menjadi satu. Menurut Abdul Hamid al-Anshari dan Muhammad Iqbal dalam bukunya Fiqh Siyasah, Iqbal menyebut ada beberapa perbedaan antara syura dan demokrasi; pertama, kekuasaan majelis syura dalam Islam bersifat terbatas, sejauh tidak bertentangan dengan nash. Majelis syura boleh membicarakan diluar itu, sejuah tidak melanggar koridor kemaslahatan umat dan semangat syariat Islam. Sementara demokrasi menekankan kekuasaan mutlak di tangan manusia tanpa batas, sejauh masyarakat menghendakinya. Kedua, hak dan kebebasan manusia dalam syura dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama. Sedangkan dalam demokrasi kebebasan manusia diatas segalanya. Atas nama demokrasi orang boleh melakukan apa saja, termasuk menetapkan peraturan yang membolehkan perjudian, pelacuran dan sederet perilaku buruk lainnya. Ketiga, syura dalam Islam di tegakkan atas dasar al-haq (kebenaran) yang berasal dari agama. Demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas, walaupun yang banyak itu jauh dari moralitas dan etika agama.
Dari tiga perbedaan diatas nampak sulit untuk memberikan beberapa catatan kalau umat Islam harus menggunakan istilah demokrasi, karena keduanya secara substantif tetap berbeda, karena syura bersumber pada keyakinan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Tuhanan sementara demokrasi menjunjung suara mayoritas walaupun mereka termasuk dalam kategori yang kurang bermoral. Tetapi perbedaan tersebut masih memungkinkan untuk diberi beberapa kerangka atau batas-batas yang memungkinkan umat Islam memakai istilah demokrasi dalam sistem politik pemerintahan mereka. Misalnya saja demokrasi Islam atau demokrasi teokrasi dimana ahli-ahli agama seperti di Iran memegang posisi tertinggi atas agama dan politik atau terjadi penyatuan yang baik antara negara dengan agama. Gagasan Masyumi pada tahun 1950-an misalnya, mengenai demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam dapat dianggap sebagai inovasi umat Islam dalam bidang sosial politik, khususnya berkaitan dengan sistem pemerintahan.
Selain adanya usaha yang dilakukan oleh umat untuk menyesuaikan berbagai konsep politik Islam dengan perkembangan sistem politik dunia, tetap saja demokrasi dan syura berbeda. Kebebasan yang dianut dalam sistem demokrasi seperti kebebasan setiap warga negara untuk memeluk keyakinan, itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mengenai kebebasan memilih keyakinan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran (Yunus: 99) “maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”, dalam surat Al-Baqarah (2:260) Allah lebih tegas lagi mengatakan mengenai kebebasan setiap manusia untuk memeluk agama yang menjadi haknya “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam: sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat”. Prinsip kebebasan yang dianut dalam demokrasi adalah juga merupakan prinsip yang secara tegas telah dijelaskan dalam Islam melalui firman Allah dalam Al-Quran.
Mengenai kebebasan rakyat memilih pemimpin, demokrasi dan syura sama-sama memegang prinsip tersebut. Tetapi ketika berbicara mengenai siapa yang berhak untuk menjadi anggota perwakilan politik baik dalam parlemen maupun dalam pemerintahan, syura dan demokrasi mempunyai pandangan yang berbeda dan bahkan sulit untuk mencapai persamaan. Syura beranggapan yang mempunyai hak menjadi anggota perwakilan dalam syura adalah yang mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan ilmu dalam bidang agama (fiqih), menguasai persoalan publik dan merupakan representase dari berbagai keahlian dalam masyarakat. Sementara demokrasi menganggap siapa saja dapat menjadi anggota perwakilan dalam sistem pemerintahan demokratis sepanjang mereka memenuhi persyaratan demokrasi, artinya kehendak rakyat menjadi landasan bagi orang yang akan duduk dalam parlemen.
Demokrasi dan syura merupakan mekanisme politik untuk menyelesaikan berbagai perselisihan paham diantara anggota yang terwakili dalam majelis perwakilan. Dalam syura ditentukan orang-orang yang menjadi anggota dengan kualifikasi tertentu, yang dapat menjadi anggota syura menurut Hasan Al-Banna terdiri dari tiga golongan; pertama, para ahli fiqih yang mujtahid, yang pernyataan-pernyataannya diperhitungkan dalam fatwa dan pengambilan hukum; kedua, pakar yang berpengalaman dalam urusan publik; ketiga, semua orang yang memiliki kepemimpinan terhadap orang lain, misalnya pimpinan golongan, kepala suku, dll., mereka ini disebut dengan ahlul halli wal aqdi.
Yang dapat memenuhi ketentuan untuk menjadi anggota syura adalah tokoh-tokoh cendekiawan atau ilmuwan dalam tubuh umat Islam. Keterwakilan dalam syura harus menyerap berbagai spesialisasi (spesifikasi) ilmu dari anggota syura yang terpilih melalui mekanisme pemilihan, dan pemilihan dilangsungkan sebagai representasi dari persoalan umat dan untuk kemaslahatan umum. Rasyid Ridha menyebut beberapa spesifikasi yang perlu dimiliki oleh calon-calon wakil rakyat yakni : ahli-ahli agama dan ahli ilmu (intellectuelen); ahli-ahli ketentaraan dan pertahanan negara; ahli-ahli ekonomi dan keuangan; ahli-ahli hukum; ahli-ahli pertanian; ahli usaha-usaha sosial; wakil-wakil kaum buruh; ahli tata negara; kaum wartawan; para dokter; para ahli yang lain. Tetapi ada syarat yang mutlak dimiliki oleh seorang calon yang juga dianut dalam sistem demokrasi yaitu tiap-tiap calon diakui dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wakil mereka. Wakil-wakil inilah yang akan membuat undang-undang dasar negara. Kalau dalam syura undang-undang yang dibuat harus berdasarkan kepada nash-nash (Al-Quran dan Sunnah) sedangkan dalam demokrasi berdasrkan kepada nalar manusia artinya berbagai produk hukum dari negara yang menganut paham demokrasi adalah merupakan cerminan dari kebanykan persoalan yang berkembang dalam masyarakat, walaupun aturan hukum tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Islam)
Dari uraian diatas mengenai siapa saja yang pantas menjadi anggota ahlul halli wal aqdi telah terlihat dengan jelas, bahwa syura menekankan pada penguasaan ilmu agama dan wawasan yang luas serta spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh setiap calon, maka demokrasi memerlukan kecerdasan dan kemampuan sesorang untuk dipilih, tetapi tidak jarang orang-orang yang “kurang cerdas” menjadi anggota parlemen, bahkan tidak tahu persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakatnya sehingga dia harus bertindak bagaimana. Fenomena demikian sering dialami oleh negara yang baru “demokratis” setelah sekian lama diperintah oleh rezim otoriter diktator. Euforia politik dalam masa transisi menuju demokratis inilah masyarakat banyak melampiaskan kebebasan dengan berbagai kegiatan seperti membuat perkumpulan dan membentuk partai politik dengan berbagai motif dan kepentingan, ketika diadakan pesta demokrasi (pemilihan) wakil-wakil rakyat, banyak partai politik tadi yang mencalonkan anggotanya untuk menjadi wakil rakyat walaupun calon tersebut berpendidikan “rendah” dan tidak mengerti persoalan yang dihadapi olerh rakyat apalagi punya keahlian tertentu, sementara rakyat belum begitu terdidik dengan persoalan politik.
Dari keterwakilan dalam syura telah nyata perbedaan dengan sistem demokrasi yang dianut oleh mayoritas negara-negara modern saat ini terutama di Barat. Keterwakilan politik dalam demokrasi tidak didasarkan pada penguasaan ilmu-ilmu agama yang memadai atau bahkan faktor agama tidak menjadi pertimbangan (diabaikan) untuk memilih anggota perwakilan politik, melainkan kepakaran, atau popularitas, tidak menjadi soal punya wawasan kebangsaan atau tidak, memahami persoalan umum itu juga tidak menjadi soal, yang terpenting adalah rakyat menyukainya sebagai pemimpin. Umumnya pemimpin demikian lahir di dalam negara-bangsa yang baru memulai kehidupan politik mereka yang demokratis setelah sebelumnya diperintah oleh rezim diktator-otoriter. Kenyataan ini telah membawa pengaruh dari dominasi barat terhadap negara-negara Islam, sehingga sistem syura yang dimiliki oleh Islam tidak lagi menjadi pegangan bagi para pemimpin Islam dalam menjalankan pemerintahan di negara mereka. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa hampir 200 negara moderns saat ini menggunakan demokrasi sebagai sistem politik pemerintahannya dan termasuk negara-negara muslim.
Polemik mengenai istilah yang perlu dilakukan oleh Islam, apakah tetap memakai syura atau demokrasi, seorang pemikir Islam terpenting abad ini yakni Salim Ali Al-Bahansawi mengemukakan pandangannya, bahwa perlu dilakukan Islamisasi demokrasi agar menjadi lebih baik dan hal ini baginya penting dilakukan oleh umat Islam, mengingat pengaruh pendidikan Barat dan menguatnya penggunaan demokrasi dikalangan Islam; pertama, menetapkan tanggungjawab setiap individu dihadapan Allah dan umat, dan apabila jelas kebenaran baginya tetapi dia condong kepada penguasa atau partai demi kepentingan tertentu, maka dia dipandang sebagai pengkhianat yang menyalahgunakan amanat di dunia dan khirat. Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu” (An-Nisa : 135). Kedua, para wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam bermusyawarah dan dalam tugas-tugas lainnya. Ketiga, Islam tidak memandang mayoritas sebagai ukuran mutlak dalam kasus yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi s.a.w. berbeda dengan demokrasi Barat yang menjadikan suara mayoritas sebagai hak mutlak adalah undang-undang tertinggi. Keempat, komitmen terhadap ajaran Islam dalam hal-hal terhadap yang berkaitan dengan persyaratan jabatan dan tanggungjawab, sehingga hanya orang yang bermoral menghormati diri mereka dan tugas mereka yang dapat duduk di parlemen.
Dalam sistem demokrasi, keadilan merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seorang calon wakil rakyat, dan juga bagi mereka yang akan menduduki sebuah jabatan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Al-Mawardi mendefinisikan keadilan pada diri pejabat, apabila dia berkata jujur, menunjukkan sifat dapat dipercaya, mengekang diri dari hal-hal yang tidak baik, tidak serakah, jauh dari keraguan,dan berkepribadian baik.
Saiful Mujani (2007: 32-34) mengajukkan hipotesis tentang Islam dan budaya demokrasi, antara lain:
Islam dan modal sosial.
Demokrasi membutuhkan aksi kolektif koordinatif, yang dicapai melalui modal sosial, seperti saling percaya antar sesama warga dan jaringan keterlibatan dalam kelompok kewarganegaran (civic engagement). Unsur budaya demokrasi ini, seperti telah dipaparkan sebelumnya, diyakini tidak ada dalam masyarakat muslim,dan islam dianggap bertanggung-jawab atas masalah ini. Bila asumsi ini benar, maka klita bisa berharap bahwa semakin islam seorang muslim, semakin besar ketidakpercayaan pada orang lain. Lebih lanjut, terdapat sejumlah norma agama yang menunjukkan bahwa kaum non-Muslim tidak dapat dipercaya. Hipotesis yang kedua adalah: semakin islami seoarang Muslim, semakin besar ketidakpercayaannya kepada non-Muslim. Modal sosial merupakan “jaringan secular civic engagement “. Karena itu hipotesis ketiga: semakin islami seorang Muslim, semakin kecil keterlibatannya dalam kelompok warga sekuler.
Islam dan Toleransi sosial-politik
Toleransi politik sangatlah penting bagi konsolidasi demokrasi. Islam dan Kristen diyakini sebagai agama dakwah dan misi. Pra penganutnya memiliki kewajiban untuk mendakwahi orang-orang yang tidak percaya padanya. Dipercayai bhwa hal ini merupakan sumber intoleransi kaum Muslim terhadap penganut Kristen, atau sebaliknya. Bila proposisi ini benar, saya berharap bahwa semakian Islam seorang Muslim, ia akan cenderung semakin tidak toleran terhadap orang-orang Kristen. Lebih lanjut,toleransi politik dipahami sebagai kelompok yang paling tidak disukai. Kalau Islam dipandang sebagai sumber toleransi, saya berharap menemukan kenyataan bahwa semakin Islami seorang Muslim, semakin tidak toleran ia terhadap kelompok yang paling tidak ia sukai.
Islam Dan Keterlibatan Politik
Keterlibatan politik (political engagement) atau budaya politik partisipan diyakini sebagai hal penting dalam demokrasi.Sebelumnya telah dipaparkan pandangan bahwa partisipasi politik merupakan sebuah gejala yang asing dalam Islam. Jika asumsi ini benar, semakin Islam seorang Muslim, semakin besar pula kemungkinan ia untuk tidak terlibat dalam politik.
Kepercayaan terhadap institusi demokrasi
Dalam Islam dan literature budaya demokrasi (civil cultur), percaya pada institusi politik berhubungan dengan rasa saling percaya antar sesama warga. Saling percaya antar sesama warga berdampak positif terhadap kepercayaan pada institusi politik, dan percaya pada institusi politik berpengaruh positif terhadap pengautan demokrasi dalam suatu Negara. Kalau diyakini bahwa Islam bertentangan dengan penguatan demokrasi, maka diharapkan Islam juga bertentangan dengan kepercayaan pada isntitusi demokrasi. Karena itu, pada tingkat individu, semakin Islam seorang muslim, semakin tidak percaya ia terhadap institusi demokrasi.
Islam dan Prinsip-prinsip demokrasi.
Klaim bahwa Islam bertentangn dengan demokrasi secara khusus terkait dengan penolakan terhadap Prinsip-prinsip demokrasi seperti kepercayaan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, nilai keebasan dan hak-hak minoritas dan pemilihan umum yang kompetitif. Seperti telah dikupas sebelumnya, kaum muslimin dipercaya lebih dekat dengan budaya politik Islam, dan budaya ini dipercaya bertentangan dengan dukungan terhadap demokrasi dan dengan nilai-nilai dasar demokrasi. Bila klaim ini benar, semakin Islami seorang muslim, semakin ia tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi.
Islam dan dukungan terhadap Negara-bangsa
Seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam tradisi politik Islam, gagasan tentang Negara-bangsa merupakan hal yang asing. Umat Islam lebih mengenal ummah sebagai komunitas politik yang melampaui sekat-sekat Negara-bangsa ketimbang Negara-bangsa itu sendiri. Karena itu, semakin Islami seoarng muslim, semakin ia tidak mendukung Negara bangsa sebagai komunitas politik.
Islam dan partisipasi politik.
Partisipasi politik diyakini sebagai konsep yang asing bagi masyarakat muslim. Partisipasi politik bagi masyarakat muslim terkait dengan karakterisitik obyek dari partisipasi tersebut, apakah terkait dengan kerangkan norma Islam atau tidak. Karena itu, bila obyek partisipasi itu tidak ada kaitannya dengan Islam, partisipasi itu menjadi kecil kemungkinannya. Bila klaim ini benar, semakin Islami seorang muslim, ia semakin tidak berpartisipasi dalam politik kecuali politik itu terkait dengan tuntutan agama.
Islam, keterlibatan politik, kepercayaan pada institusi politik, dan partisipasi politik.
Berbagai studi tentang demokrasi beranggapan bahwa, berbagai kobinasi antara keterlibatan di bidang di bidang politk dan rasa percaya pada institusi politik akan menghasilkan berbagai jenis warga Negara: warga Negara yang setia (allegiant) yang teralienasi (allienated), yang apatis, dan yang naïf (cf. Selligson, 1980). Warga yang setia secara politik akan terlibat di dalam dan percaya pada institusi politik. Warga Negara yang teralienasi secara politis juga akan terlibat dalam insitusi yang ada, namun ia tidak percaya dengan institusi itu dan mempunyai potensi untuk mengganggu jalannya demokrasi. Warga yang naïf adalah mereka yang tidak ingin terlibat di dalam proses politi namun percaya pada institusi politik yang ada. Sedangkan warga yang apatis adalah mereka yang tidak ingin terlibat dalam proses politik dan tidak percaya pada institusi politik yang ada.
Klaim bawa Islam memiliki hubungan negatif dengan demokrasi, dapat dilihat dari bagaiman aIslam berhubungan dengan keempat jenis warga Negara ini. Jika klaim Islam bertentang dengan demokrasi benar, semakin Islami seorang muslim, semakin kecil kemungkinan baginya untuk menjadi warga neara yang setia dibandingkan dengan warga Negara yang teralienasi, naïf dan apatif.
Intoleransi Islam dan partipasi politik.
Bila Islam memiliki hubungan yang negative dengan toleransi, dan toleransi memiliki hubungan yang negative dengan partisipasi politik, seorang muslim yang tidak toleran akan cenderung aktif dalam politik. Pola hubungan ini penting bagi stabilitas demokrasi, yang membutuhkan aktivis yang toleran dan bukan tidak toleran.
Dalam perkembangannya, demokrasi dalam Islam mulai mengalami pelapukan yang begitu memprihatinkan. Sebab banyak diantara para aktifis Islam yang tidak menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang murni dan dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Banyak diantara mereka memberikan sampel kufur terhadap demokrasi, ada yang berargumen, bahwa demokrasi lahir dari para pemikir Barat (bukan dari para pemikir Islam) dan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan orang-orang Barat yang sarat dengan kafir dan Yahudi. Ada juga yang berpendapat, bahwa demokrasi menjadikan rakyat itu sebagai tuhan, sebagaimana yang menjadi asas demokrasi yakni ”dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, inilah yang tidak diterima oleh sebagian kalangan tentang demokrasi. Kemudian dalam demokrasi juga ada namanya ”suara rakyat adalah suara tuhan”, mereka mengatakan bahwa pemimpinlah yang dapat memutuskan semuanya.
“Demokrasi adalah Islam itu sendiri.” Khalid Muhammad Khalid (1974)
Kini di berbagai belahan dunia Islam, salah satu isu terpenting adalah soal kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Ketika banyak negara di dunia mengalami gelombang demokratisasi, negara-negara Islam dan negara-negara Muslim justeru tidak mengalaminya. Yang terjadi malah demokrasi ditanggapi secara negatif.
Yang lebih miris, survei dari Freedom House AS tahun 2001 yang mengukur “Kebebasan dan Demokrasi” di seluruh dunia, menemukan hasil: dari 47 Negara Muslim, hanya 11 Negara yang pemerintahannya dipilih secara demokratis. Sementara 145 Negara non-Muslim, 110 di antaranya telah demokratis. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi masih menjadi masalah besar di Negara Islam.
Lalu, mengapa demokrasi sulit diterima di Negara-negara Muslim? Boleh jadi ada dua faktor yang membuat umat Islam ragu, bahkan sulit menerima konsep demokrasi. Pertama, faktor eksternal: demokrasi diidentikkan dengan sekulerisasi, kapitalisme, dan standar ganda AS, karenanya umat Islam menolak. Kedua, faktor internal berupa sistem dan ajaran yang mempengaruhi proses berfikir umat. Sebab, papar Mohammed Arkoun, tafsir atas wacana Islam selalu didominasi oleh pandangan tradisional. Karena itu wacana demokrasi seakan asing dan bukan Islam.
Mungkin karena adanya sikap seperti ini, demokrasi di Negara Islam dan muslim tidak maju dan berkembang.
Kalau demikian faktanya, lalu apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Apa Islam punya visi tentang demokrasi (visi-ideal)? Kalau ya, apa ada praktek konkret demokrasi dalam Islam (sosio-historis)? Haruskah menjadi fakta pernyataan Huntington bahwa jarang sekali muncul Negara demokratis dari sebuah negara yang penduduknya beragama Islam.
Demokrasi dalam Piagam Madinah
Semua umat beragama di mana pun, termasuk Islam, ketika berhadapan dengan problem-modern kemasyarakatan, biasanya akan mencari akar otentisitas dalam ajaran dan sejarah agamanya. Ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan bagaimana membentuk masyarakat yang ideal, maka yang terbayang dalam benak kita, adalah model, gaya dan praktek Rasulullah dalam menciptakan masyarakat masanya.
Ketika Rasul merasa tidak mungkin menciptakan tatanan ideal masyarakat pada fase Mekkah, maka Hijrah (pindah) ke Madinah merupakan jalan keluar terbaik untuk membentuk masyarakat yang dicita-citakan.
Tindakan pertama, ketika Nabi SAW. sampai di Madinah, adalah mempersaudarakan kaum muslimin sendiri yaitu antara Muhajirin dan Anshar di rumah Anas Ibn Malik. Setelah itu, Nabi melaksanakan langkah keduanya, mengadakan perjanjian dengan Yahudi atas dasar aliansi dan kebebasan beragama.
Tercapainya perjanjian ini, kekuatan sosial-politik Madinah, praktis, berada di bawah kekuasaan penuh Rasulullah. Perjanjian Nabi dengan komunitas Madinah yang multi-etnik dan multi-agama secara formal ditulis dalam sebuah naskah yang dikenal dengan “Piagam Madinah,” as-Shahifah al-Madinah, atau al-Mitsaq al-Madinah.
Di kalangan para sarjana Barat, piagam itu dikenal sebagai “Konstitusi Madinah” (Madjid: 1999;22). Disebut sebagai konstitusi, karena di dalamnya berisi konsensus bersama tentang tata-aturan hidup antar-komunitas di dalam (negara) Madinah. Karena itu, Muhammad Hamidullah menyebutnya sebagai konstitusi pertama di muka bumi yang diumumkan oleh sebuah negara (Bulac: 2001;265-66). Piagam Madinah menjadi pijakan hidup bersama dalam satu komunitas.
Nuktah dan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah dinilai mengandung dasar-dasar demokrasi, antara lain: Pertama, Persamaan (egaliterianisme/al-musawa). Persamaan dan keadilan terkandung dalam pasal-pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40. pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di hadapan hukum, pengadilan dan memperoleh hak sosial sama, pekerjaan umum, penggunaan fasilitas umum, membayar pajak, kesemuanya itu tanpa pandang bulu: tanpa melihat status sosial, agama, suku dan jenis kelamin.
Kedua, kebebasan (freedom/al-hurriyyah). Kebebasan beragama (pluralisme) terkandung dalam pasal 25. Bunyi pasalnya “Kaum Yahudi dari Banu Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat kelaliman dan kejahatan, merusak diri dan keluarga mereka. Komitmen terhadap pluralitas dengan tegas disebutkan “Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana umat Islam bebas menjalankan agama mereka”.
Karena kebebasan yang diberikan piagam ini, Munawwir Syadzali (1991;12) menilai sebagai konstitusi negara (Islam) pertama yang tidak menyebutkan agama negara. Ini berarti negara mengakui semua agama dan tidak memaksakan pada paham satu agama saja. Prinsipnya, penghormatan terhadap praktek ibadah setiap pemeluk agama.
Kebebasan beragama ini benar-benar diterapkan Nabi SAW. Beliau melarang sahabat Hushayn dari
Kebebasan beragama ini benar-benar diterapkan Nabi SAW. Beliau melarang sahabat Hushayn dari Banu Salim Ibn ‘Auf yang memaksa kedua anaknya yang Nasrani agar memeluk Islam, karena Nabi melihat bahwa beragama adalah hak setiap manusia. Begitu juga ketika Kabilah Aus memaksa anak-anaknya yang beragama Yahudi untuk masuk agama Islam dan segera bergabung dengan pasukan Rasulullah, beliau melarangnya.
Dalam pasal 25 ini agama tidak menjadi pemisah untuk hidup dalam sebuah negara. Kaum Yahudi dan Musyrikin tidak di tempatkan di lokasi yang diperangi (dar al-harb) dan kaum muslimin di lokasi aman (dar al-islam). Tapi mereka hidup di satu tempat sebagai umat, satu dengan yang lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan, hidup dengan penuh kedamaian (musalamah). Tidak ada warga kelas dua, karena perbedaan agama. Kebebasan di sini bukan saja agama tapi juga mencakup kebebasan berfikir, berpendapat dan berkumpul.
Ketiga, Hak Asasi Manusia (human rights/huquq al-insan). Walaupun dalam piagam ini tidak secara ekplisit menyebutkan HAM, namun semangat poin-poin di dalamnya telah mencakup aspek ini. Alquran secara tegas memperhatikan dan sangat menghormati hak asasi manusia dengan memuliakannya (QS.al-Isra/17:70). Pengenalan konsep ini dilakukan Rasulullah ketika melakukan “khutbah perpisahan,” “khutbah al-wada’,” “Sesungguhnya hidupmu, hartamu dan harga-dirimu adalah berharga/suci bagi kalian seperti hari ini, bulan ini” di akhir pidatonya Rasulullah menegaskan “bukankah telah kusampaikan,” hingga 3 kali, lalu beliau menyuruh kepada siapa pun yang hadir untuk menyampaikannya kepada yang berhalangan hadir waktu itu (Bukhari: 1994;III/148). Dengan itu, Nabi saw. Ingin menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia: hidup, harta dan martabat. Selain itu, penegasan yang disampaikan Nabi juga menyangkut pertanggungjawaban, kewajiban menunaikan amanah, emansipasi wanita, menghapuskan praktek riba dan menegaskan kembali persaudaraan sesama Muslim.
Islam melihat HAM bukan sebagai hak (huquq), tapi lebih dari itu, yaitu sebagai kewajiban (dlaruriyyat) yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat. Sebab itu, Abu Ishaq al-Syatibi (2001;I/7-8) dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat melihat bahwa hak-hak asasi manusia seperti hak beragama dan menjalankan keyakinannya (hifdz ad-din), hak perlindungan dan keamanan (hifdz al-nafs), hak berfikir dan berpendapat (hifdz al-‘aql), hak berumah tangga dan mempunyai keturunan (hifdz al-nasl) dan hak memperoleh harta (hifdz al-mal) harus dipenuhi. Kalau hak-hak dasar ini tak terpenuhi maka tak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena hanya dengan terpenuhinya hak-hak itu maka pelaksanaan terhadap pemenuhan hak itu menjadi wajib (dlaruriyat).
Keempat, musyawarah (consultation/al-syura). Nuktah ini yang menjadi inti utama dari demokrasi. Sekali lagi, secara tekstual, poin-poin yang ada dalam naskah Piagam Madinah tidak ada yang menyebut secara spesifik. Namun jika diperhatikan secara seksama pasal-pasal yang ada dalam naskah itu menyembulkan semangat bermusyawarah. Bahkan, kelahirannya hasil dari musyawarah antar kelompok agama.
Sebagai sebuah konsep dan sekaligus prinsip, syura dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik Syura maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, syura dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama (Sulaiman: 2001;128).
Dalam praktek sosial di Madinah, Rasul sering menampilkan sikap mendengar pendapat mayoritas seperti dalam peperangan Uhud, Badar, Perjanjian Hudaybiyyah, hingga kehidupan pribadi sekalipun, beliau meminta masukan dari para sahabatnya ketika badai “kabar bohong” (hadist al-ifki) menimpa rumah tangganya (Ibn Katsir: 1996;369 -70). Sikap meminta dan mendengarkan pendapat orang lain, lalu mengikuti suara terbanyak bagian dari sikap kebesaran Rasul dan menunjukkan partisipasi yang kuat dari masyarakat Madinah.
Praktek musyawarah pada masa Nabi saw. masih pada tahap pertama atau embrional, karena itu pelaksanaannya masih terbatas. Pelaksana dari konsep itu dikenal dengan Ahl al-Hilli Wa al-‘Aqdi. Mekanisme yang ada pada masa Rasul ini tidak baku, tapi berkembang mengikuti perkembangan zaman (al-Amin: 2000;207-8). Praktek syura (demokrasi) itu dalam demokrasi modern kemudian berkembang dan dikenal dengan partisipasi. Maka, Piagam Madinah sangat menjunjung dan menekankan partisipasi bukan dominasi, karena sebuah struktur politik yang unitarian atau totaliterian tidak mengizinkan adanya keberagaman.
Karenanya, jika yang dimaksud demokratisasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi karena dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan semau sendiri oleh satu orang atau kelompok orang (Inayat:1998). Sebab itu Islam sangat cocok dengan paham demokrasi yang berkembang baik di Barat, bahkan nilai-nilai demokrasi sangat sesuai dengan substansi ajaran dan nilai-nilai Islam. Demokrasi adalah sarana yang terbaik untuk menggulirkan cita-cita kemanusiaan dan cita-cita kemasyarakatan Islam. Islam mendukung demokrasi dan hak azasi manusia melalui argumentasinya sendiri (Uhlin: 1998;73-5).
Islam memiliki nilai dan prinsip demokrasi secara ideal (Piagam Madinah) dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerus pertama (khulafa al-rasyidin). Prilaku dan praktek masyarakat di Madinah adalah cermin masyarakat ideal yang dicita-citakan. Ini semakin mengukuhkan Madinah sebagai contoh masyarakat yang inklusif, plural, partisipatif, egaliter dan demokratis. Dengan demikian Islam punya contoh masyarakat di masa silamnya yang bisa dijadikan eksemplar bagi pembentukan masyarakat demokratis di masa kini.
Kebebasan beragama ini benar-benar diterapkan Nabi SAW. Beliau melarang sahabat Hushayn dari Banu Salim Ibn ‘Auf yang memaksa kedua anaknya yang Nasrani agar memeluk Islam, karena Nabi melihat bahwa beragama adalah hak setiap manusia. Begitu juga ketika Kabilah Aus memaksa anak-anaknya yang beragama Yahudi untuk masuk agama Islam dan segera bergabung dengan pasukan Rasulullah, beliau melarangnya.
Dalam pasal 25 ini agama tidak menjadi pemisah untuk hidup dalam sebuah negara. Kaum Yahudi dan Musyrikin tidak di tempatkan di lokasi yang diperangi (dar al-harb) dan kaum muslimin di lokasi aman (dar al-islam). Tapi mereka hidup di satu tempat sebagai umat, satu dengan yang lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan, hidup dengan penuh kedamaian (musalamah). Tidak ada warga kelas dua, karena perbedaan agama. Kebebasan di sini bukan saja agama tapi juga mencakup kebebasan berfikir, berpendapat dan berkumpul.
Ketiga, Hak Asasi Manusia (human rights/huquq al-insan). Walaupun dalam piagam ini tidak secara ekplisit menyebutkan HAM, namun semangat poin-poin di dalamnya telah mencakup aspek ini. Alquran secara tegas memperhatikan dan sangat menghormati hak asasi manusia dengan memuliakannya (QS.al-Isra/17:70). Pengenalan konsep ini dilakukan Rasulullah ketika melakukan “khutbah perpisahan,” “khutbah al-wada’,” “Sesungguhnya hidupmu, hartamu dan harga-dirimu adalah berharga/suci bagi kalian seperti hari ini, bulan ini” di akhir pidatonya Rasulullah menegaskan “bukankah telah kusampaikan,” hingga 3 kali, lalu beliau menyuruh kepada siapa pun yang hadir untuk menyampaikannya kepada yang berhalangan hadir waktu itu (Bukhari: 1994;III/148). Dengan itu, Nabi saw. Ingin menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia: hidup, harta dan martabat. Selain itu, penegasan yang disampaikan Nabi juga menyangkut pertanggungjawaban, kewajiban menunaikan amanah, emansipasi wanita, menghapuskan praktek riba dan menegaskan kembali persaudaraan sesama Muslim.
Islam melihat HAM bukan sebagai hak (huquq), tapi lebih dari itu, yaitu sebagai kewajiban (dlaruriyyat) yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat. Sebab itu, Abu Ishaq al-Syatibi (2001;I/7-8) dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat melihat bahwa hak-hak asasi manusia seperti hak beragama dan menjalankan keyakinannya (hifdz ad-din), hak perlindungan dan keamanan (hifdz al-nafs), hak berfikir dan berpendapat (hifdz al-‘aql), hak berumah tangga dan mempunyai keturunan (hifdz al-nasl) dan hak memperoleh harta (hifdz al-mal) harus dipenuhi. Kalau hak-hak dasar ini tak terpenuhi maka tak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena hanya dengan terpenuhinya hak-hak itu maka pelaksanaan terhadap pemenuhan hak itu menjadi wajib (dlaruriyat).
Keempat, musyawarah (consultation/al-syura). Nuktah ini yang menjadi inti utama dari demokrasi. Sekali lagi, secara tekstual, poin-poin yang ada dalam naskah Piagam Madinah tidak ada yang menyebut secara spesifik. Namun jika diperhatikan secara seksama pasal-pasal yang ada dalam naskah itu menyembulkan semangat bermusyawarah. Bahkan, kelahirannya hasil dari musyawarah antar kelompok agama.
Sebagai sebuah konsep dan sekaligus prinsip, syura dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik Syura maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, syura dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama (Sulaiman: 2001;128).
Dalam praktek sosial di Madinah, Rasul sering menampilkan sikap mendengar pendapat mayoritas seperti dalam peperangan Uhud, Badar, Perjanjian Hudaybiyyah, hingga kehidupan pribadi sekalipun, beliau meminta masukan dari para sahabatnya ketika badai “kabar bohong” (hadist al-ifki) menimpa rumah tangganya (Ibn Katsir: 1996;369 -70). Sikap meminta dan mendengarkan pendapat orang lain, lalu mengikuti suara terbanyak bagian dari sikap kebesaran Rasul dan menunjukkan partisipasi yang kuat dari masyarakat Madinah.
Praktek musyawarah pada masa Nabi saw. masih pada tahap pertama atau embrional, karena itu pelaksanaannya masih terbatas. Pelaksana dari konsep itu dikenal dengan Ahl al-Hilli Wa al-‘Aqdi. Mekanisme yang ada pada masa Rasul ini tidak baku, tapi berkembang mengikuti perkembangan zaman (al-Amin: 2000;207-8). Praktek syura (demokrasi) itu dalam demokrasi modern kemudian berkembang dan dikenal dengan partisipasi. Maka, Piagam Madinah sangat menjunjung dan menekankan partisipasi bukan dominasi, karena sebuah struktur politik yang unitarian atau totaliterian tidak mengizinkan adanya keberagaman.
Karenanya, jika yang dimaksud demokratisasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi karena dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan semau sendiri oleh satu orang atau kelompok orang (Inayat:1998). Sebab itu Islam sangat cocok dengan paham demokrasi yang berkembang baik di Barat, bahkan nilai-nilai demokrasi sangat sesuai dengan substansi ajaran dan nilai-nilai Islam. Demokrasi adalah sarana yang terbaik untuk menggulirkan cita-cita kemanusiaan dan cita-cita kemasyarakatan Islam. Islam mendukung demokrasi dan hak azasi manusia melalui argumentasinya sendiri (Uhlin: 1998;73-5).
Islam memiliki nilai dan prinsip demokrasi secara ideal (Piagam Madinah) dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerus pertama (khulafa al-rasyidin). Prilaku dan praktek masyarakat di Madinah adalah cermin masyarakat ideal yang dicita-citakan. Ini semakin mengukuhkan Madinah sebagai contoh masyarakat yang inklusif, plural, partisipatif, egaliter dan demokratis. Dengan demikian Islam punya contoh masyarakat di masa silamnya yang bisa dijadikan eksemplar bagi pembentukan masyarakat demokratis di masa kini.