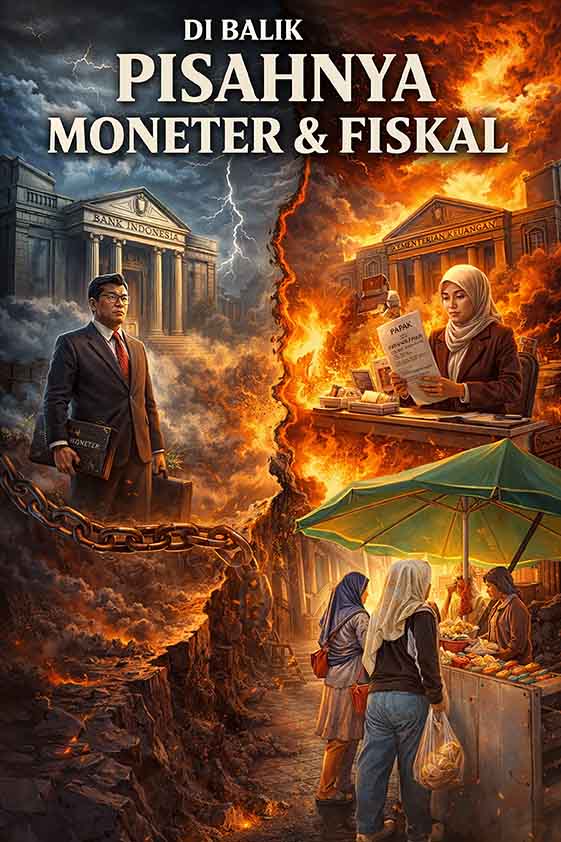“𝙆𝙐𝙃𝙋 𝘽𝙀𝙇𝘼𝙉𝘿𝘼 𝙑𝙀𝙍𝙎𝙐𝙎 𝙆𝙐𝙃𝙋 𝙄𝙉𝘿𝙊𝙉𝙀𝙎𝙄𝘼 ? (“Politik Hukum Nasional, Living Law, dan Orientasi Keadilan Hukum Masa Depan”)
Ahmad Murjoko
𝘿𝙤𝙨𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙖𝙢𝙖𝙩 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙠
Abstract
The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code marks a historic transition from the Dutch colonial penal code to a national criminal law system. This article analyzes the fundamental differences between the Dutch Criminal Code and the Indonesian Criminal Code by examining their legal sources, political-legal orientation, and normative objectives. Using a normative-juridical approach, this study explores the concept of living law, the position of Islam as a material source of law, and the relevance of maqāṣid al-sharī‘ah in shaping future legal justice. The findings indicate that the Indonesian Criminal Code reflects a paradigm shift toward humanistic, constitutional, and value-based justice, aligning with national legal politics and the universal objectives of Islamic law.
Keywords: Indonesian Criminal Code, Legal Politics, Living Law, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Legal Justice
Abstrak
Pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada awal Januari 2026 menandai berakhirnya dominasi hukum pidana kolonial Belanda dan dimulainya era hukum pidana nasional Indonesia. Artikel ini menganalisis perbandingan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia dengan menitikberatkan pada sumber hukum, arah politik hukum, konsep living law, serta posisi Islam dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menunjukkan bahwa KUHP Indonesia merepresentasikan pergeseran paradigma menuju keadilan hukum yang humanis, konstitusional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di masa depan.
Kata kunci:
KUHP Indonesia, Politik Hukum, Living Law, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Keadilan Hukum
Pendahuluan
Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia bergantung pada Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda. Keberlakuannya didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945, namun secara filosofis dan sosiologis KUHP kolonial tidak lahir dari nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Moeljatno, 2008). Kondisi ini menciptakan paradoks antara kemerdekaan politik dan ketergantungan hukum pidana.
Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting politik hukum nasional. KUHP baru tidak sekadar mengganti teks hukum, tetapi membawa misi dekolonisasi hukum, integrasi nilai Pancasila, HAM, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2011).
Permasalahan dan Gap Research
Kajian tentang KUHP baru umumnya berfokus pada isu kontroversial pasal-pasal tertentu. Namun, masih terdapat gap penelitian dalam mengaitkan:
1. Perbandingan paradigmatik KUHP Belanda dan KUHP Indonesia,
2. Politik hukum pidana nasional,
3. Konsep living law,
4. Posisi Islam sebagai sumber hukum materiil,
4. Relevansi maqāṣid al-syarī‘ah terhadap orientasi keadilan hukum masa depan.
Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan integratif antara hukum tata negara dan hukum Islam.
Analisis dan Pembahasan
1. latar Belakang
Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) merupakan bagian integral dari agenda besar politik hukum nasional dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keberadaan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht) yang selama lebih dari tujuh dekade tetap berlaku pasca-kemerdekaan menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum nasional dan realitas sistem hukum pidana yang digunakan (Moeljatno, 2008).
Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip kedaulatan hukum nasional sebagai bagian dari kedaulatan negara. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk hukum untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi (Mahfud MD, 2010). Oleh karena itu, pengesahan UU KUHP harus dipahami sebagai perwujudan politik hukum negara untuk menggantikan hukum pidana kolonial dengan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Sejalan dengan itu, dalam perspektif hukum Islam, hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah). Al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan manusia, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syāṭibī, 1997). KUHP kolonial, yang lahir dari sistem nilai Barat sekuler, tidak disusun dengan mempertimbangkan dimensi moral-religius masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama dan menjunjung nilai-nilai ketuhanan.
Dimensi historis KUHP Indonesia
Dimensi historis KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang hukum pidana Indonesia yang berakar pada sistem hukum kolonial Belanda. Sejak diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië pada tahun 1918 dan efektif berlaku tahun 1918–1946, hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan transplantasi hukum kolonial yang dirancang untuk kepentingan penguasa kolonial, bukan untuk mencerminkan nilai, budaya, dan cita hukum bangsa Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2011).
Setelah Indonesia merdeka, KUHP peninggalan Belanda tetap diberlakukan berdasarkan asas koncordantie dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kondisi ini menciptakan paradoks historis, di mana negara merdeka masih menggunakan instrumen hukum pidana kolonial yang secara filosofis tidak sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan semangat kemerdekaan (Moeljatno, 2008). Upaya pembaruan KUHP sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1960-an, namun mengalami stagnasi panjang akibat dinamika politik dan perdebatan ideologis yang kompleks.
Secara historis, pembentukan KUHP Baru merupakan bagian dari agenda besar dekolonisasi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum nasional pascakolonial harus dibangun berdasarkan pengalaman sosial dan nilai bangsa sendiri, bukan sekadar mewarisi sistem hukum penjajah.
Oleh karena itu, KUHP Baru diposisikan sebagai simbol kedaulatan hukum nasional yang menandai berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana kolonial (Rahardjo, 2009).
Dalam perspektif politik hukum, dinamika sejarah pembaruan KUHP mencerminkan pergulatan antara berbagai kepentingan ideologis, mulai dari nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, hingga nilai-nilai agama. Mahfud MD menegaskan bahwa produk hukum selalu merupakan hasil kompromi politik, sehingga KUHP Baru lahir sebagai titik temu antara tuntutan modernisasi hukum, perlindungan HAM, dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal serta religius masyarakat Indonesia (Mahfud MD, 2010).
Dari sudut pandang hukum Islam, dimensi historis KUHP Baru juga menunjukkan perubahan pendekatan negara terhadap nilai-nilai keagamaan. Jika pada masa kolonial hukum pidana sepenuhnya bersifat sekuler dan positivistik, maka dalam KUHP Baru terdapat pengakuan terbatas terhadap norma yang hidup dalam masyarakat (living law). Hal ini sejalan dengan sejarah panjang kontribusi hukum Islam dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat Nusantara, meskipun tidak diadopsi secara formal sebagai hukum pidana negara (Hooker, 2008).
Dengan demikian, secara historis, KUHP Baru merupakan hasil dari proses panjang pencarian identitas hukum nasional Indonesia. Ia bukan sekadar penggantian teks undang-undang, melainkan refleksi dari perjalanan sejarah bangsa dalam membangun sistem hukum pidana yang berdaulat, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter sosial serta nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia.
Dimensi Yuridis-Konstitusional dan Maqāṣid al-Syarī‘ah
Secara yuridis-konstitusional, pembaruan KUHP merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar UUD 1945 pasca-amandemen, terutama terkait penguatan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan pembatasan kekuasaan negara. Hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan negara harus tunduk pada prinsip konstitusionalisme agar tidak berubah menjadi alat represi (Barda Nawawi Arief, 2010).
Dalam konteks politik hukum pidana, UU KUHP berfungsi sebagai kodifikasi yang menyatukan asas-asas umum hukum pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Muladi menyatakan bahwa tanpa kodifikasi yang kuat, hukum pidana nasional akan kehilangan arah kebijakan dan konsistensi normatif (Muladi, 1995).
Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kodifikasi hukum pidana dapat dipahami sebagai wasīlah tasyri‘iyyah untuk menjaga kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). Ibn ‘Āshūr menekankan bahwa hukum publik harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata kepentingan negara atau penguasa (Ibn ‘Āshūr, 2006). Dengan demikian, pembaruan KUHP memiliki legitimasi normatif baik secara konstitusional maupun secara maqāṣidī.
Landasan Filosofis: Pancasila, Negara Hukum, dan Maqāṣid
Secara filosofis, UU KUHP berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum nasional. Dalam tradisi hukum tata negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai grundnorm etik yang mengarahkan pembentukan dan penegakan hukum (Kaelan, 2016). Orientasi pemidanaan dalam UU KUHP yang menekankan keadilan restoratif dan proporsionalitas pidana mencerminkan pergeseran dari paradigma represif menuju paradigma humanistik.
Pendekatan tersebut memiliki korespondensi kuat dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa tujuan hukum bukanlah penderitaan, melainkan perbaikan dan penjagaan tatanan sosial (al-Syāṭibī, 1997). Pembatasan pidana mati melalui mekanisme bersyarat, serta pengakuan pidana alternatif non-penjara, sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nafs dan raf‘ al-ḥaraj (penghilangan kesulitan) dalam hukum Islam.
Dengan demikian, UU KUHP dapat dibaca sebagai bentuk integrasi nilai Pancasila dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam hukum positif negara modern.
Dimensi Sosiologis: Living Law, Hukum Responsif, dan Kaidah Fiqhiyyah
Secara sosiologis, politik hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat yang religius, plural, dan memiliki tradisi hukum adat yang kuat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang tidak selaras dengan nilai sosial masyarakat akan kehilangan legitimasi sosialnya (Satjipto Rahardjo, 2009).
Pengakuan terbatas terhadap living law dalam UU KUHP mencerminkan politik hukum yang responsif dan kontekstual. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaidah al-‘ādah muḥakkamah, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan nash syar‘i (Zuhaili, 1989). Dengan demikian, pendekatan sosiologis UU KUHP memiliki legitimasi ganda, baik dalam teori hukum modern maupun dalam khazanah ushul fiqh.
Dimensi Politis: Politik Hukum Pidana dan Siyāsah Shar‘iyyah
Secara politis, pembentukan UU KUHP merupakan hasil dari proses legislasi demokratis yang melibatkan tarik-menarik kepentingan antara negara, masyarakat sipil, dan kelompok moral-religius. Dalam perspektif hukum tata negara, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan instrumen dominasi kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, 2015).
Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan legislasi negara dapat dipahami sebagai bagian dari siyāsah shar‘iyyah, yaitu kebijakan penguasa dalam mengatur masyarakat demi kemaslahatan umum. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan negara sah secara syar‘i selama bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Ibn Taymiyyah, 1995).
Dengan demikian, UU KUHP merupakan bentuk kebijakan legislatif negara modern yang dapat dibenarkan baik secara konstitusional maupun secara maqāṣid al-syarī‘ah.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU KUHP merupakan produk politik hukum nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembaruan hukum pidana kolonial, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional dan kemaslahatan universal. Dalam perspektif hukum tata negara, UU KUHP menegaskan kedaulatan hukum nasional dan supremasi konstitusi, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, ia dapat dibaca sebagai instrumen tasyri‘ modern yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah
3. Sumber Hukum KUHP
KUHP Belanda selama ini bersumber pada tradisi hukum Eropa Kontinental yang positivistik dan sekuler. Sebaliknya, KUHP Indonesia bersumber pada Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, nilai sosial, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2015). Dalam politik hukum nasional, sumber hukum ini menunjukkan orientasi kedaulatan hukum dan supremasi konstitusi (Mahfud MD, 2010).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hasil kodifikasi hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan berbagai sumber hukum, baik formal maupun material. Penentuan dan penggunaan sumber hukum dalam KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum nasional, sekaligus dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka etik-normatif dalam hukum Islam. Adapun sumber hukum KUHP terbaru ini adalah sebagai berikut :
a. Pancasila sebagai Sumber Hukum Fundamental
Pancasila menempati posisi utama sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara politik hukum, Pancasila berfungsi sebagai pedoman ideologis dalam pembentukan hukum pidana nasional agar mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial (Kaelan, 2016).
Dalam KUHP baru, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pergeseran paradigma pemidanaan dari represif menuju humanistik, antara lain melalui pengakuan pidana alternatif, keadilan restoratif, dan pembatasan pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum Pancasila tidak hanya bersifat simbolik, tetapi operasional dalam perumusan norma pidana.
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, Pancasila memiliki korespondensi nilai dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl). Al-Syāṭibī menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (al-Syāṭibī, 1997).
Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber hukum KUHP dapat dipandang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam aspek nilai dan tujuan.
b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Sumber Hukum Konstitusional
UUD 1945 merupakan sumber hukum konstitusional yang menentukan batas dan arah pembentukan hukum pidana. Politik hukum pidana Indonesia harus tunduk pada prinsip negara hukum (rechtsstaat), konstitusionalisme, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Bab XA UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2015).
KUHP baru disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional tersebut, antara lain melalui penguatan asas legalitas, proporsionalitas pidana, serta perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum yang membatasi sekaligus melegitimasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana.
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, konstitusi dapat dipahami sebagai instrumen ḥifẓ al-niẓām al-‘āmm (perlindungan tatanan umum). Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa hukum publik harus diarahkan pada penjagaan keteraturan sosial dan kepentingan umum (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Oleh karena itu, penggunaan UUD 1945 sebagai sumber hukum KUHP sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial.
c. Peraturan Perundang-undangan sebagai Sumber Hukum Positif
Secara formal, KUHP merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks ini, undang-undang sektoral pidana yang telah ada sebelumnya menjadi sumber rujukan material, baik untuk diintegrasikan maupun diselaraskan. Politik hukum pidana diarahkan pada kodifikasi dan unifikasi agar hukum pidana nasional tidak terfragmentasi (Muladi, 1995). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan KUHP harus mencerminkan kebijakan hukum pidana nasional (penal policy) yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010).
Dengan demikian, peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum teknis sekaligus kebijakan dalam perumusan KUHP.
Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai wasīlah (sarana) untuk mencapai kemaslahatan. Kaidah taṣarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah menegaskan bahwa kebijakan hukum penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat (Zuhaili, 1989).
d. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)
Salah satu sumber hukum penting dalam KUHP baru adalah pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Secara politik hukum, pengakuan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan hukum yang responsif dan kontekstual (Satjipto Rahardjo, 2009).
Living law dijadikan sumber hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip hukum umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan nilai sosial masyarakat memperoleh tempat dalam hukum pidana nasional, meskipun tetap berada dalam kerangka negara hukum.
Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan terhadap living law sejalan dengan kaidah al-‘ādah muḥakkamah, yakni adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan nash syar‘i. Dengan demikian, living law dalam KUHP dapat dipandang kompatibel dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harmoni sosial (ḥifẓ al-niẓām al-ijtimā‘ī).
e. Prinsip-prinsip Hukum Universal dan HAM
KUHP baru juga menggunakan prinsip-prinsip hukum universal dan norma HAM sebagai sumber hukum material. Hal ini terlihat dari penguatan prinsip proporsionalitas, pembatasan pidana mati, dan perlindungan kelompok rentan. Secara politik hukum, hal ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menjadi bagian dari komunitas internasional (Mahfud MD, 2010).
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, prinsip HAM tidak dipahami sebagai antitesis syariat, melainkan sebagai ekspresi modern dari tujuan perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah). Al-Syāṭibī menegaskan bahwa kemaslahatan manusia merupakan inti dari seluruh hukum (al-Syāṭibī, 1997).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dalam KUHP terbaru bersifat multidimensional, mencakup Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, living law, dan prinsip hukum universal. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini mencerminkan arah politik hukum pidana yang berorientasi pada kedaulatan hukum nasional dan konstitusionalisme.
Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, sumber-sumber hukum tersebut dapat dipahami sebagai instrumen tasyri‘ modern yang secara substantif sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial.
3. Konsep Living Law
Living law adalah hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis. Eugen Ehrlich menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum terletak pada masyarakat, bukan semata pada legislasi (Ehrlich, 1936). Dalam KUHP Indonesia, living law diakui secara terbatas sebagai sumber hukum materiil dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM (Muladi, 1995).
Living law adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis atau dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh legitimasi formal negara, tetapi oleh penerimaan sosial, kepatuhan, dan efektivitasnya dalam kehidupan sehari-hari (Ehrlich, 1936).
Eugen Ehrlich, pelopor konsep living law, menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan hanya pada legislasi atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai, kebiasaan, dan struktur sosial yang hidup di tengah masyarakat (Ehrlich, 1936).
Living Law dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam konteks Indonesia, living law sering dikaitkan dengan hukum adat, norma agama, dan nilai sosial lokal yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat sebelum hadirnya hukum negara. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai institusi sosial yang berinteraksi dinamis dengan masyarakat (Rahardjo, 2009).
Pengakuan terhadap living law juga tercermin secara konstitusional, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan (Asshiddiqie, 2015). Dengan demikian, living law memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional.
Living Law dalam UU KUHP Baru
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara terbatas mengakomodasi konsep living law, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam pemidanaan, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas-asas hukum umum. Pendekatan ini mencerminkan politik hukum pidana nasional yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Barda Nawawi Arief, 2011).
Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut. Negara tetap memegang otoritas untuk menentukan batas-batas berlakunya living law demi mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa living law ditempatkan sebagai sumber hukum materiil, bukan sebagai hukum formal yang berdiri sendiri (Muladi, 1995).
Living Law dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam perspektif hukum Islam, konsep living law memiliki kedekatan makna dengan prinsip ‘urf (kebiasaan) dan maṣlaḥah mursalah, yaitu praktik sosial yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sehingga hukum harus memperhatikan realitas sosial tempat ia diterapkan (al-Syāṭibī, 1997).
Dengan demikian, living law dalam konteks hukum Islam dapat dipahami sebagai ekspresi nilai-nilai syariat yang terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat. Selama nilai tersebut menjaga tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka ia memiliki legitimasi normatif (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Living law merupakan konsep penting dalam pengembangan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual. Ia berfungsi sebagai jembatan antara hukum negara, realitas sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Dalam sistem hukum Indonesia, living law diakui secara konstitusional dan diakomodasi secara terbatas dalam UU KUHP baru, dengan tetap berada dalam kerangka politik hukum nasional dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.
4. Posisi Islam
Dalam sistem hukum Indonesia, Islam tidak berfungsi sebagai hukum pidana formal, melainkan sebagai sumber nilai dan hukum materiil. Konsep ‘urf dan maṣlaḥah dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memperhatikan realitas sosial (al-Zuḥaylī, 1989). Pendekatan ini selaras dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum (al-Syāṭibī, 1997).
Dalam perspektif Islam, hukum tidak dipahami semata sebagai norma tertulis yang bersifat formalistik, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan mengatur perilaku sosial umat. Oleh karena itu, konsep living law memiliki korespondensi kuat dengan karakter hukum Islam yangk bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hukum Islam sejak awal berkembang melalui interaksi antara teks wahyu dan realitas sosial, sehingga praktik sosial umat menjadi salah satu medium aktualisasi norma syariat (Hallaq, 2009).
Islam sebagai Sumber Living Law
Islam dapat diposisikan sebagai sumber living law ketika nilai-nilai syariat telah terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat Muslim. Konsep ‘urf (kebiasaan yang diakui) menunjukkan bahwa Islam memberi ruang terhadap norma sosial yang hidup sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Wahbah al-Zuḥaylī menegaskan bahwa ‘urf yang sahih dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena ia mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat (al-Zuḥaylī, 1989).
Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hadir sebagai sistem yang terlepas dari realitas sosial, melainkan sebagai hukum yang hidup (living sharia), yaitu norma keagamaan yang dijalankan secara sukarela oleh masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial (Kamali, 2008).
Islam, Living Law, dan Negara
Dalam negara modern, khususnya negara bangsa seperti Indonesia, Islam sebagai living law tidak serta-merta menjadi hukum positif negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara Pancasila bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang menafikan peran agama. Negara mengakui nilai-nilai agama sebagai sumber hukum materiil, bukan sumber hukum formal (Asshiddiqie, 2015).
Posisi ini sejalan dengan politik hukum Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan hukum nasional melalui mekanisme demokratis dan konstitusional. Dengan demikian, Islam berfungsi sebagai moral source dan ethical guidance bagi pembentuk undang-undang, termasuk dalam perumusan KUHP baru, tanpa harus diformalkan sebagai hukum pidana agama (Mahfud MD, 2010).
Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Kerangka Living Law
Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memperkuat posisi Islam sebagai living law yang substantif. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kepentingan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan-tujuan ini bersifat universal dan dapat diterjemahkan ke dalam norma hukum negara yang plural (al-Syāṭibī, 1997).
Dalam konteks hukum pidana nasional, nilai-nilai maqāṣid tercermin dalam prinsip perlindungan HAM, keadilan restoratif, pembatasan pidana mati, dan pemidanaan yang proporsional. Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa syariat pada hakikatnya bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum, sehingga relevan dijadikan landasan etis dalam pembentukan hukum modern (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Implikasi bagi Hukum Islam dan Hukum Tata Negara
Dengan memposisikan Islam sebagai living law, terjadi pertautan antara hukum Islam dan hukum tata negara. Hukum Islam berkontribusi pada substansi nilai hukum nasional, sementara hukum tata negara menyediakan kerangka konstitusional untuk mengatur batas dan mekanisme adopsinya. Pendekatan ini mencegah formalisasi syariat yang eksklusif sekaligus menghindari sekularisasi hukum yang kering nilai (Hallaq, 2009; Asshiddiqie, 2015).
Oleh karena itu, posisi Islam dalam living law bukan sebagai hukum positif yang memaksa, melainkan sebagai sumber normatif dan etis yang hidup dalam masyarakat dan memberi arah bagi politik hukum nasional.
Kesimpulan
Islam menempati posisi strategis dalam konsep living law sebagai sistem nilai yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam negara hukum Pancasila, Islam berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang berkontribusi pada pembentukan hukum nasional melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan mekanisme konstitusional yang demokratis
5. Hubungan KUHP Baru dan Keadilan Hukum Mendatang
KUHP baru menggeser orientasi keadilan dari retributif menuju keadilan korektif dan restoratif. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga jiwa, akal, dan harta (Ibn ‘Āshūr, 2006). Keadilan tidak lagi dimaknai sebatas penghukuman, tetapi juga pemulihan sosial.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan fundamental dalam orientasi keadilan hukum di Indonesia. KUHP Baru tidak lagi menempatkan hukum pidana semata sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, perlindungan martabat manusia, dan ketertiban sosial yang berkelanjutan (Barda Nawawi Arief, 2011).
Dalam perspektif politik hukum, KUHP Baru merupakan manifestasi kebijakan negara untuk menggeser paradigma hukum pidana dari pendekatan kolonial-represif menuju pendekatan konstitusional-humanis. Mahfud MD menegaskan bahwa arah politik hukum suatu negara menentukan wajah keadilan yang akan dibangun di masa depan. Dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar, KUHP Baru diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mahfud MD, 2010).
Secara normatif, KUHP Baru mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana, yang memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi pelaku, korban, serta dampak sosial dari suatu tindak pidana. Pendekatan ini membuka ruang bagi penerapan keadilan korektif dan restoratif sebagai bentuk keadilan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan semata (Muladi, 1995).
Hubungan KUHP Baru dengan keadilan hukum mendatang juga tampak dalam pengakuan terbatas terhadap living law. Pengakuan ini mencerminkan upaya negara untuk mendekatkan hukum positif dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum tidak kehilangan legitimasi sosialnya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar hukum yang sah secara formal (Rahardjo, 2009).
Dalam perspektif hukum Islam, orientasi keadilan KUHP Baru memiliki kesesuaian substantif dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah menjaga kemaslahatan manusia, baik pada level individu maupun sosial. Prinsip perlindungan jiwa, akal, harta, dan kehormatan tercermin dalam kebijakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pencegahan (al-Syāṭibī, 1997).
Ibn ‘Āshūr menambahkan bahwa keadilan hukum tidak hanya diukur dari ketegasan sanksi, tetapi dari sejauh mana hukum mampu mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Dalam konteks ini, KUHP Baru berpotensi menjadi instrumen keadilan hukum masa depan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama implementasinya tetap menjunjung prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan HAM (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Dengan demikian, hubungan KUHP Baru dan keadilan hukum mendatang bersifat strategis dan determinatif. KUHP Baru bukan hanya hukum pidana positif, melainkan arah kebijakan hukum negara dalam membangun sistem keadilan yang lebih beradab, berkeadilan sosial, dan selaras dengan nilai-nilai religius serta konstitusional.
6. Pengaruh KUHP Baru terhadap Keadilan Hukum Mendatang
Pengaruh utama KUHP baru adalah terbentuknya sistem hukum pidana yang lebih humanis dan proporsional. Pembatasan pidana mati dan perluasan pidana alternatif mencerminkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari keadilan substantif (Barda Nawawi Arief, 2011).
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pengaruh signifikan terhadap arah dan kualitas keadilan hukum di Indonesia pada masa mendatang. KUHP Baru tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga merekonstruksi paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan represif menuju pendekatan humanis dan konstitusional (Barda Nawawi Arief, 2011).
Dari sudut pandang politik hukum, KUHP Baru merupakan instrumen strategis negara untuk membentuk sistem keadilan hukum yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam menentukan apakah hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan atau sarana keadilan sosial (Mahfud MD, 2010). Dalam konteks ini, KUHP Baru dirancang untuk memperkuat keadilan hukum yang berimbang antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.
Pengaruh nyata KUHP Baru terhadap keadilan hukum mendatang terlihat pada pergeseran orientasi pemidanaan. KUHP Baru memperluas pilihan pidana non-pemenjaraan, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana denda proporsional. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif dan restoratif yang lebih menekankan perbaikan pelaku dan pemulihan korban dibanding pembalasan semata (Muladi, 1995).
Selain itu, pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Baru menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia fundamental. Pendekatan ini menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yang sejalan dengan perkembangan hukum HAM internasional dan prinsip kemanusiaan dalam hukum nasional (Asshiddiqie, 2015).
Pengakuan terbatas terhadap living law juga berpengaruh terhadap keadilan hukum mendatang. Dengan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, KUHP Baru berpotensi meningkatkan legitimasi sosial hukum pidana. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai masyarakat, bukan hukum yang kaku dan terlepas dari realitas sosial (Rahardjo, 2009).
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pengaruh KUHP Baru terhadap keadilan hukum mendatang dapat dinilai positif sepanjang implementasinya konsisten dengan tujuan perlindungan kemaslahatan. Al-Syāṭibī menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk menjaga jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kebijakan pemidanaan yang proporsional dan berorientasi pencegahan (al-Syāṭibī, 1997).
Ibn ‘Āshūr menambahkan bahwa hukum yang baik bukan hanya hukum yang sah secara formal, tetapi hukum yang mampu menciptakan keadilan sosial dan mencegah kerusakan struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengaruh KUHP Baru terhadap keadilan hukum mendatang sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan konsistensi penerapannya di lapangan (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Dengan demikian, KUHP Baru memiliki potensi besar untuk membentuk wajah keadilan hukum Indonesia di masa depan. Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh kesadaran politik, kapasitas institusional, dan komitmen etis seluruh pemangku kepentingan hukum.
7. Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung meliputi legitimasi konstitusional, dukungan politik negara, dan kebutuhan pembaruan hukum.
Faktor penghambat mencakup rendahnya literasi hukum aparat, resistensi sosial, serta potensi multitafsir pasal living law (Mahfud MD, 2010).
Keberhasilan KUHP Baru sebagai instrumen keadilan sosial tidak hanya ditentukan oleh kualitas normatif teks undang-undang, tetapi juga oleh faktor struktural, kultural, dan politik yang memengaruhi implementasinya. Dalam perspektif politik hukum, hukum pidana hanya efektif jika didukung oleh konfigurasi kekuasaan, institusi, dan budaya hukum yang kondusif (Mahfud MD, 2010).
Faktor Pendukung
Salah satu faktor pendukung utama adalah legitimasi konstitusional dan politik KUHP Baru. Sebagai produk undang-undang yang dibentuk melalui mekanisme demokratis, KUHP Baru memiliki dasar konstitusional yang kuat, sehingga secara normatif mampu menjadi rujukan utama dalam mewujudkan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2015).
Faktor pendukung berikutnya adalah orientasi nilai humanis dan keadilan restoratif yang diusung KUHP Baru. Pergeseran dari paradigma retributif ke korektif-restoratif membuka ruang bagi pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial, terutama bagi kelompok rentan (Barda Nawawi Arief, 2011). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.
Selain itu, akomodasi living law menjadi faktor pendukung penting karena memungkinkan hukum pidana lebih responsif terhadap nilai sosial dan kultural masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang hidup dan diterima masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan keadilan substantif dibanding hukum yang bersifat formalistik (Rahardjo, 2009).
Dalam perspektif hukum Islam, faktor pendukung lainnya adalah kesesuaian substantif KUHP Baru dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Tujuan perlindungan jiwa, harta, akal, dan kehormatan tercermin dalam kebijakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pencegahan, sehingga mendukung terwujudnya keadilan sosial yang berkelanjutan (al-Syāṭibī, 1997; Ibn ‘Āshūr, 2006).
Faktor Penghambat
Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang berpotensi menghambat perwujudan keadilan sosial melalui KUHP Baru. Salah satu faktor utama adalah kesiapan aparat penegak hukum. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap paradigma baru KUHP, aparat cenderung menerapkan hukum secara tekstual dan represif, sehingga tujuan keadilan sosial sulit tercapai (Muladi, 1995).
Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Ketidaktahuan publik terhadap substansi dan tujuan KUHP Baru dapat menimbulkan resistensi sosial serta salah tafsir, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sosial hukum pidana (Rahardjo, 2009).
Pengakuan terhadap living law juga menyimpan potensi hambatan, khususnya terkait risiko multitafsir dan diskriminasi. Tanpa pedoman yang jelas, penerapan living law dapat disalahgunakan untuk melegitimasi norma lokal yang bertentangan dengan prinsip HAM dan keadilan sosial. Oleh karena itu, negara tetap harus berperan sebagai pengendali utama melalui prinsip konstitusionalisme (Asshiddiqie, 2015).
Dalam perspektif politik hukum, tarik-menarik kepentingan politik dan ideologis juga dapat menjadi faktor penghambat. Mahfud MD menegaskan bahwa hukum sering kali menjadi arena kompromi politik, sehingga implementasinya dapat terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan keadilan sosial (Mahfud MD, 2010).
Analisis Kritis
Secara teoritik, keberhasilan KUHP Baru dalam mewujudkan keadilan sosial mensyaratkan sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tanpa keseimbangan ketiganya, hukum pidana berpotensi kehilangan fungsi sosialnya. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila hukum dijalankan sebagai sarana kemaslahatan, bukan sebagai alat dominasi (al-Syāṭibī, 1997).
Dengan demikian faktor pendukung dan penghambat KUHP Baru menunjukkan bahwa keadilan sosial bukanlah hasil otomatis dari perubahan undang-undang. Ia merupakan proses yang memerlukan komitmen politik, kesiapan institusional, dan kesadaran etis seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan politik hukum yang konsisten dan orientasi maqāṣid al-syarī‘ah, KUHP Baru berpeluang besar menjadi instrumen keadilan sosial di masa mendatang.
8. Analisis Teoritik Praktik KUHP Baru
Secara teoritik, praktik KUHP baru dapat dianalisis melalui teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan sosial (Rahardjo, 2009). Dalam perspektif siyāsah shar‘iyyah, negara berwenang menetapkan hukum demi kemaslahatan umum selama tidak melanggar prinsip keadilan (Ibn Taymiyyah, 1995).
Praktik penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritik yang menjelaskan hubungan antara norma hukum, kekuasaan negara, dan realitas sosial. Secara teoritik, keberhasilan praktik KUHP Baru sangat ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum (Friedman, 1975).
Dalam perspektif politik hukum, KUHP Baru merupakan instrumen negara untuk mengarahkan praktik hukum pidana menuju tujuan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum menentukan apakah hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang progresif atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Oleh karena itu, praktik KUHP Baru di masa mendatang sangat bergantung pada konsistensi kebijakan negara dalam menjunjung nilai konstitusional dan demokratis (Mahfud MD, 2010).
Dari sudut pandang teori hukum progresif, praktik KUHP Baru idealnya tidak terjebak pada positivisme hukum yang kaku. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk membahagiakan manusia, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan KUHP Baru secara kontekstual dan berkeadilan substantif, terutama dalam perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat luas (Rahardjo, 2009).
Teori keadilan restoratif juga menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik KUHP Baru. Muladi menekankan bahwa keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Praktik KUHP Baru yang mengedepankan pidana alternatif dan pemulihan korban mencerminkan penerapan teori ini dalam sistem hukum pidana nasional (Muladi, 1995).
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik KUHP Baru dapat dinilai dari sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menjaga tujuan pokok syariat, yakni perlindungan jiwa, akal, harta, kehormatan, dan agama. Oleh karena itu, praktik KUHP Baru harus diarahkan pada pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban sebagai manifestasi kemaslahatan publik (al-Syāṭibī, 1997).
Ibn ‘Āshūr menambahkan bahwa keadilan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penerapan sanksi, tetapi sebagai upaya menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, praktik KUHP Baru di masa mendatang dituntut untuk responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Selain itu, pengakuan terbatas terhadap living law dalam KUHP Baru menuntut pendekatan teoritik yang hati-hati. Dari sudut pandang teori pluralisme hukum, praktik hukum pidana harus mampu mengelola keberagaman norma sosial tanpa mengorbankan prinsip HAM dan non-diskriminasi. Negara tetap berperan sebagai penentu batas agar living law tidak digunakan secara arbitrer (Asshiddiqie, 2015).
Dengan demikian, secara teoritik, praktik KUHP Baru di masa mendatang harus ditempatkan dalam kerangka hukum responsif, yaitu hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial, berorientasi pada keadilan substantif, dan berpijak pada nilai konstitusional serta maqāṣid al-syarī‘ah. Tanpa landasan teoritik tersebut, KUHP Baru berpotensi mengalami kegagalan implementasi meskipun secara normatif telah dirancang progresif.
Kesimpulan dan Saran
KUHP Indonesia merupakan produk politik hukum nasional yang menggantikan paradigma kolonial dengan paradigma konstitusional dan humanis. Secara substantif, KUHP baru memiliki kesesuaian dengan nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Diperlukan sosialisasi, penguatan aparat penegak hukum, dan pengawasan yudisial agar tujuan keadilan hukum masa depan dapat tercapai.
Praktik penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritik yang menjelaskan hubungan antara norma hukum, kekuasaan negara, dan realitas sosial. Secara teoritik, keberhasilan praktik KUHP Baru sangat ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum (Friedman, 1975).
Dalam perspektif politik hukum, KUHP Baru merupakan instrumen negara untuk mengarahkan praktik hukum pidana menuju tujuan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum menentukan apakah hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang progresif atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, praktik KUHP Baru di masa mendatang sangat bergantung pada konsistensi kebijakan negara dalam menjunjung nilai konstitusional dan demokratis (Mahfud MD, 2010).
Dari sudut pandang teori hukum progresif, praktik KUHP Baru idealnya tidak terjebak pada positivisme hukum yang kaku. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk membahagiakan manusia, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan KUHP Baru secara kontekstual dan berkeadilan substantif, terutama dalam perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat luas (Rahardjo, 2009).
Teori keadilan restoratif juga menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik KUHP Baru. Muladi menekankan bahwa keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Praktik KUHP Baru yang mengedepankan pidana alternatif dan pemulihan korban mencerminkan penerapan teori ini dalam sistem hukum pidana nasional (Muladi, 1995).
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik KUHP Baru dapat dinilai dari sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menjaga tujuan pokok syariat, yakni perlindungan jiwa, akal, harta, kehormatan, dan agama. Oleh karena itu, praktik KUHP Baru harus diarahkan pada pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban sebagai manifestasi kemaslahatan publik (al-Syāṭibī, 1997).
Ibn ‘Āshūr menambahkan bahwa keadilan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penerapan sanksi, tetapi sebagai upaya menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, praktik KUHP Baru di masa mendatang dituntut untuk responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Ibn ‘Āshūr, 2006).
Selain itu, pengakuan terbatas terhadap living law dalam KUHP Baru menuntut pendekatan teoritik yang hati-hati. Dari sudut pandang teori pluralisme hukum, praktik hukum pidana harus mampu mengelola keberagaman norma sosial tanpa mengorbankan prinsip HAM dan non-diskriminasi. Negara tetap berperan sebagai penentu batas agar living law tidak digunakan secara arbitrer (Asshiddiqie, 2015).
Dengan demikian, secara teoritik, praktik KUHP Baru di masa mendatang harus ditempatkan dalam kerangka hukum responsif, yaitu hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial, berorientasi pada keadilan substantif, dan berpijak pada nilai konstitusional serta maqāṣid al-syarī‘ah. Tanpa landasan teoritik tersebut, KUHP Baru berpotensi mengalami kegagalan implementasi meskipun secara normatif telah dirancang progresif.
Penutup
Perbandingan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana bukan sekadar pergantian norma, melainkan transformasi nilai dan tujuan hukum. KUHP Indonesia menjadi instrumen penting dalam membangun keadilan hukum yang berdaulat, bermartabat, dan berorientasi kemaslahatan.
Daftar Pustaka
al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
Barda Nawawi Arief. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah. Amman: Dār al-Nafā’is, 2006.
Ibn Taymiyyah. Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 1995.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jakarta, 31 Desember 2025
Ahmad Murjoko
𝘿𝙊𝙎𝙀𝙉 𝙎𝙏𝘼𝙄 𝙃𝘼𝙎 𝘾𝙄𝙆𝘼𝙍𝘼𝙉𝙂 /𝙎𝙏𝙐𝘿𝙄 𝙈. 𝙉𝘼𝙏𝙎𝙄𝙍